KLASIFIKASI DAN KEMANFAATAN “JURISPRUDENCE”
Oleh SHIDARTA (Maret 2016)
Pada tulisan sebelumnya, saya sempat menulis tentang apa itu ‘jurisprudence’, yang pada intinya membawa kita pada pemahaman bahwa jurisprudence adalah cabang disiplin hukum yang dikenal sebagai teori [ilmu] hukum. Sebagai suatu cabang disiplin hukum, jurisprudence ini menjadi sangat penting untuk diajarkan di pendidikan tinggi akademis hukum. Apa isi dari jurisprudence ini ternyata sangat bervariasi. Antara satu penulis dan penulis lainnya bisa berbeda bergantung pada penekanan yang ingin diberikan.
Seorang guru besar dari Yale University bernama Wesley Newcomb Hohfeld pada Desember 1914 menyampaikan pidato di depan the Association of American Law Schools, mengangkat isu bertajuk “A Vital School of Jurisprudence, and Law: Have American Universities Awakened to the Enlarged Opportunities and Responsibilities of the Present Day?” Dalam paparannya, Hohfeld menyatakan ada tiga kelompok pembelajaran dan aktivitas yang seharusnya ditawarkan oleh perguruan tinggi hukum di Amerika Serikat pada masa itu (saya kira, juga masih berlaku sampai saat ini), yaitu tentang : (1) the systematic and development study of legal system, (2) the professional and detailed study of the Anglo-American Legal System, dan (3) the civic and cultural study of legal institutions.
Apabila nasihat dari Hohfeld yang telah berjeda waktu lebih dari satu abad itu masih layak kita jadikan acuan, maka kurang lebih kita patut berharap perguruan tinggi hukum kita di Indonesia pun mengajarkan tentang: (1) struktur dan perkembangan sistem hukum Indonesia, (2) studi tentang tradisi hukum yang melatarbelakangi sistem hukum Indonesia, dan (3) kajian empiris terkait lembaga/pranata hukum yang ada di Indonesia. Namun, harus dicatat bahwa penekanan pada tiga poin pembelajaran di atas baru pada batas-batas koridor ilmu hukum dogmatis. Pembelajaran ilmu hukum dalam arti luas, atau biasa yang disebut disiplin hukum, harus bisa menembus demarkasi ilmu hukum dogmatis, sehingga pembelajarannya harus memasuki ranah: (1) struktur dan perkebangan sistem hukum pada umumnya, (2) studi tentang tradisi hukum yang melatarbelakangi suatu sistem hukum, dan (3) kajian empiris terkait lembaga/pranata hukum yang dikenal di berbagai sisem hukum. Makin luas sistem hukum yang dikaji, maka makin mengarah ke area general jurisprudence; namun jika ke arah sebaliknya berarti akan makin menuju ke particular jurisprudence. Sampai kemudian, apabila area kajiannya hanya terbatas pada satu sistem hukum, tepatnya sistem hukum Indonesia, maka ruang lingkupnya sudah keluar dari teritori jurisprudence. Artinya, pembelajaran hukum sudah masuk ke dalam ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum, ilmu hukum positif).
Patut dicatat di sini bahwa Hohfeld yang disebut-sebut namanya dalam tulisan ini tidak membuat pembedaan tentang general dan particular jurisprudence (sebagaimana pernah disampaikan oleh John Austin). Di mata banyak teoretisi hukum, jurisprudence adalah general jurisprudence.
Terkait dengan pembelajaran mengenai struktur dan perkembangan sistem hukum itu, peran jurisprudence sebagai meta-teori hukum positif (artnya teori tentang ilmu hukum dogmatis), menjadi sangat signifikan. Bentham menyebut kajian hukum positif ini sebagai expository jurisprudence (terbagi menjadi dua tipe: otoritatif dan non-otoritatif). Expository jurisprudence ini dibedakannya dengan kajian terhadap ius constituendum, yaitu censorial jurisprudence.
Ketika menjelaskan tentang struktur dan perkembangan sistem hukum, Hohfeld menyebut bidang studi pembelajarannya sebagai general jurisprudence. Ia lalu membedakan cabang-cabang dari general jurisprudence menjadi enam kategori. Keenam cabang itu akan disinggung sekilas dalam tulisan di bawah.
Menurut hemat saya, sebenarnya keenam cabang tersebut tidak sekadar dalam rangka mempelajari struktur dan perkembangan sistem hukum. Keenam cabang itu menyinggung ranah pembelajaran hukum pada umumnya, yang sangat komprehensif, sehingga mencakup juga persoalan tentang tradisi hukum dan kajian empiris terkait lembaga/pranata hukum.
Enam bagian dari general jurisprudence yang disebutkan oleh Hohfled di bawah ini tidak antagonistis satu dengan lainnya, bahkan di beberapa tempat dapat saling tumpang tindih. Keenam kategori itu adalah sebagai berikut:
- historical or genetic jurisprudence;
- comparative or eclectic jurisprudence;
- formal or analytical jurisprudence;
- critical or teleological jurisprudence;
- legislative or constructive jurisprudence;
- dynamic or functional jurisprudence.
Dengan mengambil optik historical jurisprudence, seorang penstudi hukum dapat memahami latar belakang sejarah perjalanan suatu sistem hukum, sehingga mewujud menjadi bentuknya seperti sekarang ini. Melalui kajian historis, dapat diketahui mengapa di suatu kawasan seperti Asia Tenggara misalnya, terdapat demikian beragam tradisi hukum (sistem civil law, sistem common law, sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis, dst.). Kolonialisasi yang menimpa kawasan Asia dan sebagian negara non-Eropa, dari perspektif historis, berkontribusi besar mengubah wajah hukum di lebih dari setengah peta dunia.
Selanjutnya ada comparative jurisprudence yang membentangkan berbagai persamaan dan perbedaan antar-sistem hukum. Sistem hukum yang ada di suatu kawasan tidak dimonopoli oleh hukum negara-negara tersebut, tetapi mengejawantah melalui daya tarik dan daya dorong berbagai kekuatan hukum kawasan lain, bahkan dengan hukum-hukum non-negara, yang notabene sangat pluralistis. Para teoretisi hukum dapat mencermati, misalnya, ada perbedaan pemaknaan terkait konsep hak asasi manusia di berbagai sistem hukum, kendati di banyak sisi juga ada hal-hal yang menyamakannya dan dapat diklaim berlaku universal. Perbandingan ini bisa dilakukan secara komprehensif terhadap keseluruhan sistem hukum, maupun pada konsep hukum yang spesifik, yang di dalam metode perbandingan hukum kerap dikenal dengan macro- dan micro-comparison.
Formal jurisprudence atau analytical jurisprudence selanjutnya berbicara tentang konsep-konsep mendasar di dalam hukum, seperti hak dan kewajiban. Berbeda dengan formal jurisprudence yang menggunakan intrinsic (internal) considerations of logical consistency and system, maka selanjutnya ada critical jurisprudence yang memakai extrinsic (external) considerations. Di sini yang dipakai sebagai alat kritik adalah doktrin di luar ilmu hukum dogmatis, seperti psikologi, etika, politik, sosial, dan ekonomi. “. for only by doing so..,” kata Hohfled, “… shall we elevate the practice of law and the administration of justice above a mere mechanical trade; only so shall our lawyers and judges know ‘the reason of the rule’ and hence be able to determine its proper limits in relation to new sets of fact.”
Sebagai contoh, sekitar tiga dekade lalu berkembang cabang teori hukum yang disebut psychological jurisprudence. Dalam buku yang disunting oleh Bruce A. Arrigo, “Psychological Jurisprudence: Critical Explorations in Law, Crime, and Society” (2004) dibahas tentang topik-topik psikologi dan hukum menyangkut kesehatan mental, penghukuman pidana, pengaruh media terhadap perilaku, tanggung jawab peradilan, dan sebagainya.
Kemudian ada lagi cabang lain berupa legislative jurisprudence atau constructive jurisprudence, yang lazim dikenal sebagai teori perundang-undangan. Hohfled mengritik banyak perguruan tinggi hukum di Amerika Serikat yang mengabaikan cabang ini karena sistem common law di sana memang lebih menekankan sumber hukum yurisprudensi (case law).
Terakhir adalah functional jurisprudence, yaitu kajian sistematis dan empiris tentang hukum, yang membahas hukum dalam keadaan bergerak (the law in motion). Mungkin ada pandangan bahwa pembelajaran tentang dimensi empiris terhadap hukum cukup diserahkan ke ilmu-ilmu lain saja, misalnya ilmu politik, sehingga ilmuwan hukum cukup berkonsentrasi pada dogmatika hukum melalui kajian sumber-sumber hukum otoritatif yang sudah tersaji (given). Mengenai hal ini Hohfeld membantahnya.
“This work cannot be safely entrusted to departments of political science or government; for the work of the latter is apt to be to general in character, dealing only with the larger phases of government, not with such concrete problems as the organization of courts, the neccisity for judicial efficiency and independence, the appointment of tenure of judges, and oher fundamentals of justice according to law. Furthermore, most university teachers of political science or government are not lawyers by training, experience, observation, or sympathy, and therefore the safeguarding and improvement of our legal institutions should not be entrusted exclusively to their jurisdiction. Through lack of technical legal training such teachers are, in large part, unable to understand the concrete problems and needs of the administration of law and justice; and hence their views are not infrequently extreme and misleading in tendency.”
Dengan tulisan ini menjadi jelas sekarang bahwa jurisprudence (teori ilmu hukum) ini memang kandungannya bisa sangat kaya dan beragam. John Austin dalam bukunya “The Province of Jurisprudence Determined” (1995: 18) juga sudah mengingatkan:
“The matter of jurisprudence is positive law, simply and striclty so called; or law set by political superiors to political inferiors. But positive law (or law, simply and stricly so called) is often confounded with objects to which it is related by resemblance, and with objects to which it is related in the way of analogy; with objects which are also signified, properly and improperly, by the large and vouge expression law.”
Alhasil, kita perlu meyakinkan diri kita bahwa belajar hukum dengan baik di perguruan tinggi tidak pernah cukup dengan membatasi diri pada belajar di dalam koridor hukum positif belaka. Belajar hukum dengan model seperti ini hanya akan mengerdilkan cara berpikir para “ahli” hukum kita. Belajar hukum tidak boleh mengarahkan diri kita pada cara melihat hukum secara monolitik. Oleh karena itu, pembelajaran di perguruan tinggi hukum sudah selayaknya memperkenalkan studi tentang esensi hukum yang luas dan multifaset. Pembelajaran ilmu hukum tersebut harus dikemas dengan baik, yakni harus sampai menyentuh pada dimensi yang lebih abstrak dan hakikat daripada sekadar makna tekstual sebagaimana tertera dalam norma hukum positif.
Jurisprudence membuka diri kepada pendekatan-pendekatan non-dogmatis dalam belajar hukum. Artinya, penstudi hukum yang baik juga seharusnya bersikap terbuka dalam mempelajari hukum, sehingga keilmiahan hukum tidak harus terpasung oleh dogma-dogma kekuasaan. Itulah yang menjadi pesan terdalam dari para eksponen cabang disiplin hukum yang disebut jurisprudence atau teori [ilmu] hukum ini. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Oliver W. Holmes Jr. (yang juga dikutip oleh Hohfeld dalam tulisannya), “One of the marks of a great lawyer is the capacity for broad generalization.”
Pandangan lain yang dapat melengkapi uraian kita di atas berasal dari Myres S. McDougal dan Harold D. Lasswell. Sebagaimana Hohfeld, mereka berdua juga adalah dosen-dosen dari Yale Law School. Mereka membedakan dua jenis teori hukum, yaitu teori hukum untuk keperluan para akademisi (scholars) dan teori hukum untuk keperluan para pengambil keputusan (decision makers). Teori hukum untuk kepentingan para akdemisi disebutnya sebagai theory about law, sementara untuk para pengambil keputusan adalah theory of law. Dalam satu artikel mereka berdua yang berjudul “Criteria for A Theory about Law” yang pertama kali dimuat dalam Southern California Law Review (1971, Vol. 44: 362-394), jurisprudence dipahami mereka sebagai teori tentang hukum (theory about law). Kita dapat menyimpulkan di sini bahwa jurisprudence yang disebut oleh McDougal dan Lasswell ini adalah general jurisprudence seperti yang disampaikan oleh senior mereka: Wesley Newcomb Hohfeld. (***)
Untuk melihat tulisan sebelumnya, klik tautan di bawah ini:



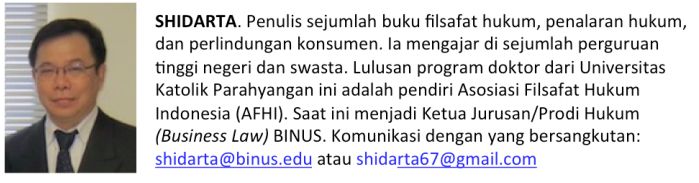
Comments :