HUKUM DAN TEKNOLOGI: Bagian 2 (Hukum Siber)
Oleh SITI YUNIARTI (Februari 2026)
Pertanyaan penutup pada bagian 1 seri Hukum dan Teknologi yang lalu adalah bagaimana bentuk respons hukum dalam dinamika perkembangan teknologi, pada dasarnya adalah pertanyaan tentang bagaimana hukum perlu menyesuaikan cara bekerjanya. Dalam masyarakat digital yang berbasis informasi, perilaku manusia tidak lagi berlangsung secara “murni”, melainkan dimediasi oleh perangkat, algoritma, platform, dan infrastruktur jaringan. Digitalisasi mengonversi sesuatu yang berada dalam dunia fisik menjadi representasi digital. Konsekuensinya, hukum dituntut bukan hanya mengatur perilaku, melainkan juga menata relasi, risiko, dan tata kelola sistem.
Perkembangan internet digunakan sebagai titik awal pembahasan untuk menunjukkan bagaimana hukum menjalankan fungsinya ketika masyarakat bergerak dari pola analog menuju masyarakat informasi. Internet kerap dipahami sebagai sarana komunikasi. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Namin, konvergensi TIK yang menjadi struktur internet membuat internet berbeda dari sarana komunikasi sebelumnya. Hal mana diilustrasikan oleh Lawrence Lessig sebagai freedom without anarchy, control without government, consensus without power.²
Secara teknis, internet merupakan jaringan yang menghubungkan komputer sebagai sistem elektronik. Interaksi antarpengguna dalam jaringan tersebut menciptakan ruang virtual yang berdampingan dengan ruang analog. Ruang virtual inilah yang selanjutnya disebut ruang siber (cyberspace). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2008, ruang (dunia) siber dimaknai sebagai “sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer yang di dalamnya berisi data-data abstrak ..”³ Definisi ini memperlihatkan bahwa ruang siber bukan sekadar metafora, melainkan suatu ruang aktivitas yang memiliki “wujud” dalam bentuk data, sistem, dan proses pemrosesan informasi.
Walaupun interaksi pengguna berlangsung dalam jaringan yang tidak kasatmata, subjek yang berinteraksi dan akibat dari interaksi tersebut bersifat nyata. Sebagaimana interaksi manusia dalam ruang analog membutuhkan norma sebagai pedoman perilaku, interaksi manusia dalam ruang siber sebagai representasi digital juga membutuhkan norma. Hal ini sejalan dengan adagium ubi societas ibi ius – di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Norma hukum, sebagai kaidah perilaku yang disertai sanksi dan dapat dipaksakan, merupakan kaidah utama pengatur perilaku manusia di ruang analog. Namun, pertanyaan berikutnya adalah: apakah norma hukum juga dapat menjadi kaidah utama pengatur perilaku manusia di ruang siber? Jika ya, maka perdebatan lainnya adalah siapa yang berperan sebagai pembentuk aturan, bagaimana penegakan aturan tersebut dalam ruang siber yang berbentuk virtual tersebut ?
Pertanyaan tentang pengaturan interaksi pengguna di ruang siber mengemuka karena perubahan tata kelola internet itu sendiri. Perubahan utilisasi internet untuk komunikasi pada ARPA Net Project ke penggunaan oleh masyarakat, mengubah sifat tata kelola sentralisasi menjadi desentralisasi yang melibatkan beragam aktor. Perubahan ini memunculkan perdebatan mengenai apakah negara perlu hadir dan sejauh mana negara berwenang mengatur ruang siber. Cyber libertarian menyatakan bahwa negara tidak perlu hadir, karena pengguna dianggap mampu mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme komunitas dan norma internal jaringan. Dalam praktik, pandangan tersebut menghadapi keterbatasan terutama ketika muncul penyalahgunaan teknologi, dominasi platform, serta ketimpangan kuasa antara pengguna dan penyelenggara sistem. Perdebatan panjang ini pada akhirnya bermuara pada pengakuan bahwa ruang siber memerlukan pengaturan. Namun pengakuan tersebut melahirkan pertanyaan lanjutan: bentuk pengaturan seperti apa yang paling tepat?
Perdebatan bentuk pengaturan kemudian berkembang dalam konsep-konsep tata kelola seperti state-centric versus multistakeholder, serta co-regulation versus self-regulation. Perdebatan tersebut pada dasarnya menyasar komposisi peran negara, peran sektor privat, dan peran masyarakat sipil dalam pengaturan ruang siber. Tarik-menarik ini tidak hanya menjadi konsumsi pada tingkat negara sebagai representasi kedaulatan, melainkan juga terjadi dalam konteks politik global. Oleh karena itu, pengaturan ruang siber sebagai suatu “teritori fungsional” yang bersinggungan dengan yurisdiksi negara turut dipengaruhi oleh norma, standar, dan dinamika global. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari salah satu karakteristik ruang siber, yakni lintas batas (cross-border/borderless). Bahkan, dalam perkembangan mutakhir, tata kelola ruang siber semakin dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, termasuk model bisnis berbasis data, komersialisasi layanan digital, dan konsolidasi kekuatan pasar platform.
Konvergensi TIK sebagai karakteristik pembentuk ruang siber menjadi tantangan bagi norma hukum yang telah ada (ius constitutum). Benturan antara konvergensi TIK dan norma hukum yang telah ada menghasilkan dua kemungkinan: pertama, peristiwa hukum yang muncul di dalam atau dari ruang siber masih dapat diakomodasi oleh norma hukum yang tersedia; kedua, peristiwa hukum yang muncul di dalam atau dari ruang siber belum dapat diakomodasi, sehingga menimbulkan kekosongan atau ketidakcukupan pengaturan. Oleh karena itu, konvergensi TIK mendorong kebutuhan akan pengembangan disiplin hukum baru atau setidaknya penyesuaian kerangka hukum yang lebih adaptif. Dalam diskursus internasional, International Telecommunication Union(ITU) telah menekankan kebutuhan penyesuaian tersebut sejak dekade 1990-an.⁴ Seiring itu, lahir berbagai terminologi seperti computer law, virtual law, telematics law, dan cyber law sebagai upaya menamai bidang hukum yang berfokus pada problem hukum dalam ruang siber.
Salah satu rujukan awal yang sering dikaitkan dengan penggunaan istilah cyber law adalah Jonathan Rosenoer (1997), yang menggambarkan cyber law sebagai domain hukum baru yang muncul untuk mengatur dan mengendalikan penyebaran serta proses teknologi di ruang siber.⁵ Dalam konteks Indonesia, cyber law kerap dimaknai sebagai pengaturan mengenai pemanfaatan TIK, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Penjelasan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).
Dalam pandangan penulis, sebagai bidang hukum baru, karakteristik utama hukum siber adalah sifatnya yang multidisipliner. Multidisipliner merupakan konsekuensi logis dari keterlibatan TIK yang merupakan domain ilmu komputer (dan bidang-bidang teknis lainnya). Di sisi lain, dimensi multidisipliner juga muncul dari interaksi hukum siber dengan cabang hukum lain, seperti namun tidak terbatas pada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum perlindungan konsumen. Mengikuti pandangan Shidarta mengenai disiplin ilmu, suatu bidang kajian memiliki objek material dan objek formal. Objek material menunjuk pada pokok bahasan, sedangkan objek formal berkaitan dengan sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis objek tersebut. Dalam konteks Indonesia, UU ITE sebagai salah satu regulasi kunci yang sering diposisikan sebagai pilar hukum siber memuat objek formal yang bersinggungan dengan bidang hukum lain. Perkembangan legislasi mutakhir, termasuk kecenderungan pemindahan atau pengaturan ulang sebagian norma yang sebelumnya dikenal dalam rezim informasi dan transaksi elektronik ke dalam rezim hukum pidana umum, memperlihatkan semakin kompleksnya posisi hukum siber di antara bidang hukum lain. Kondisi ini memunculkan pertanyaan konseptual: apakah objek yang diatur tersebut merupakan domain khas hukum siber, ataukah sebetulnya merupakan domain bidang hukum lain yang kebetulan beroperasi dalam ruang siber?
Referensi:
- Lawrence Lessig, Code Version 2.0, New York: Basic Books, 2006.
- Jonathan Rosenoer, Jonathan Rosenoer, Cyberlaw 25 years later: Innovation, transformation, and an emerging backlash, 4 April 2017



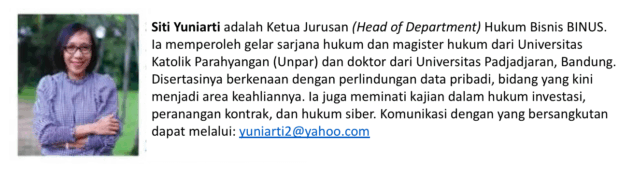
Comments :