SWAKRAMA KECERDASAN ARTIFISIAL (AI ETHICS)
Oleh SHIDARTA (Agustus 2025)
Kata “ethics” dapat dengan mudah dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, menjadi “etika”. Apabila “artificial intelligence” memiliki padanan dengan kosakata “kecerdasan artifisial” maka dengan sendirinya “AI ethics” adalah “etika kecerdasan artifisial”. Apakah ada opsi yang lain?
Kata “ethics” dalam Kamus bahasa Inggris Merriam-Webster mengandung makna sebagai “a set of moral principles : a theory or system of moral values; the principles of conduct governing an individual or a group”. Jadi, etika dapat dipandang sebagai filsafat moral atau sebagai sistem moral itu sendiri, berbentuk prinsip-prinsip moralitas dalam menuntun perilaku seseorang atau sekelompok orang. Pengertian yang kedua ini dekat dengan keperluan memformulasikan suatu “AI ethics”.
Kata “etika kecerdasan artifisial” digunakan secara eksplisit dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Di dalam surat edaran ini, etika kecerdasan artifisial didefinisikan sebagai landasan yang mengatur prinsip dan norma etis dalam penyelenggaraan pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang didasari dengan nilai inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan dalam penyelenggaraan sumber daya data yang tersedia. Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik memberi syarat khusus kepada setiap pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik untuk membuat dan menerapkan kebijakan internal perusahaan mengenai data dan etika internal kecerdasan artifisial.
Format dari etika kecerdasan artifisial itu biasanya berupa kode etik (code of ethics), yang di mana perlu juga diatur lebih lanjut dengan kode perilaku (code of conduct). Isi dari kode etik itu tentu bukan etiket (dari kata “etiquette”) yang lebih bermakna norma sopan santun dalam suatu komunitas atau situasi tertentu, seperti etiket bertamu, etiket bertelepon, dan etiket makan. Apabila etiket itu dijabarkan secara lebih teknis sehingga mengacu pada tata cara praktis yang sopan ketika seseorang bertamu, misalnya bagaimana cara mengetuk pintu, cara mengucapkan salam, cara memperkenalkan diri, dan seterusnya, di dalam bahasa Inggris lebih mengacu pada “manner”. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat menyebut keduanya, “etiquette” dan “manner” sebagai tata krama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata krama adalah sopan santun atau basa basi.
Kata “krama” di sini menarik untuk digunakan dalam kaitannya dengan “etika”. Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak memberi pemaknaan tentang apa yang dimaksud dengan “krama”, kecuali mengindikasikan bahwa kosakata ini kemungkinan berasal dari bahasa Jawa “kromo”. Tingkatan bahasa Jawa yang paling halus atau paling sopan disebut “kromo”.
Dalam bahasa Sansekerta kata “krama”[क्रम]mengacu pada makna “urutan yang tertib dan teratur”. Kata ini awalnya dipakai untuk tindakan mengambil langkah-langkah atau memesan sesuatu dengan pola yang tertib dan teratur, sesuai prosedur, dan tidak acak-acakan. Menarik, bahwa kata “krama” ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan “order” yang sebagai nomina berarti “pesanan; perintah; ketertiban”.
Dengan demikian “krama” dapat dimaknai sebagai “order” tadi. Dalam hukum, suatu krama dapat dibuat sendiri secara otonom. Krama demikian kerap disebut sebagai “autonomic legislation”. Aturan ini bukan peraturan perundang-undangan, melainkan aturan otonom yang dikeluarkan oleh entitas non-negara. Kata “otonom” di sini adalah lawan dari kata “heteronom”. Sebuah aturan otonom tidak dibuat oleh entitas di luar diri sendiri. Apabila sebuah komunitas atau asosiasi profesi membuat aturan untuk mengatur dirinya sendiri, khususnya berupa kode etik dan kode perilaku, maka semua aturan ini termasuk dalam kategori “autonomic legislation”. Apabila kata “otonom” itu dicarikan padanannya, maka kita dapat menemukan kata “swa”, sehingga aturan otonom ini layak juga jika disebut sebagai “swakrama”.
Terminologi “swakrama” bukan temuan baru karena dalam komunitas periklanan, kosakata ini pernah diperkenalkan. Sayangnya, komunitas tersebut kemudian meninggalkannya. Terbukti, etika periklanan tidak mereka namakan sebagai “swakrama pariwara” melainkan “etika pariwara”. Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tidak memakai kata “swakrama periklanan” melainkan “etika periklanan”.
Untuk keperluan mencari padanan bahasa Indonesia terhadap “AI ethics” dapat ditawarkan kosa kata “swakrama kecerdasan artifisial”. Dalam tulisan sebelumnya, kosakata “kecerdasan artifisial” ini pernah diusulkan agar disingkat menjadi “cerdal”, sehingga “AI ethics” dapat diberi padanan menjadi frasa “swakrama cerdal”. (***)



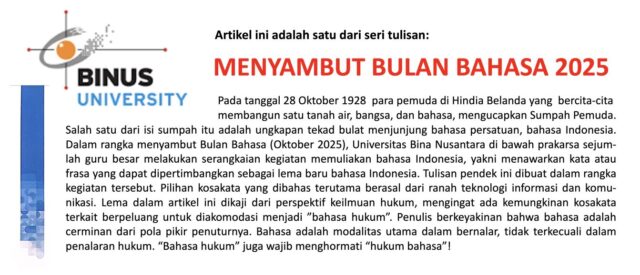
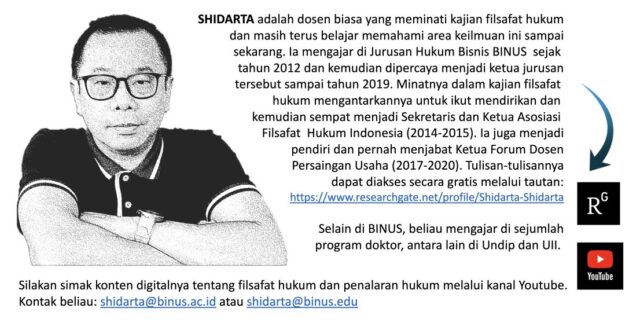
Comments :