KECERDASAN ARTIFISIAL (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
Oleh SHIDARTA (Agustus 2025)
Dalam terminologi peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ketika tulisan ini dibuat, “artificial intelligence” hanya disebutkan dalam satu peraturan, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik. Di dalam lampiran peraturan ini kegiatan usaha yang berbasis kecerdasan artifisial diberi Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 62015, yang sekaligus didefinisikan di dalam lampiran ini sebagai bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat. Definisi seperti ini tentu tidak memadai, tetapi pada bagian ruang lingkup dari lampiran tersebut diberikan tambahan keterangan bahwa aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial termasuk subset dari machine learning, natural language processing, expert system, deep learning, robotics, neural networks, dan subset lainnya. Definisi ini kemudian diambil alih untuk digunakan lagi di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Perlu dicatat bahwa surat edaran dalam konstelasi hukum positif di Indonesia tidak dimasukkan ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, melainkan peraturan kebijakan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika ini kemudian berganti nama menjadi Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut pemberitaan terakhir, Komdigi telah merampungkan penyusunan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dengan melibatkan 443 orang yang terdiri dari praktisi di pemerintahan, akademisi, industri, komunitas masyarakat, dan media.1
Dapat dipastikan bahwa padanan bahasa Indonesia untuk “artificial intelligence” telah diperbincangkan pada saat mereka merancang peraturan-peraturan tersebut. Sekalipun demikian, di masyarakat masih beredar berbagai terminologi yang mengarah ke padananan “artificial intelligence” tersebut. Tulisan ini ingin meninjau beberapa di antaranya. Selain ditranslasi menjadi kecerdasan artifisial, masih sering ditemukan penggunaan frasa “kecerdasan buatan”. Ada pula yang tidak ingin jauh dari singkatan awal dalam bahasa Inggris, sehingga “artificial intelligence” tetap ingin diberi label “AI” dengan cara disiasati terjemahannya menjadi “akal imitasi”.
Dalam Black’s Law Dictionary, kata “artificial” dimaknai sebagai lawan dari alami (natural), yakni segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Sebagai contoh, apabila seorang perempuan tidak dapat hamil secara alami, maka kehamilannya dapat direkayasa melalui campur tangan manusia. Campur tangan manusia dalam proses ini membuatnya menjadi artifisial. Dalam terminologi hukum, tindakan itu digolongkan sebagai “artificial insemination”. Kata “artifisial” juga sudah menjadi lema Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata “artifisial” dimaknai sebagai tidak alami; buatan.
Secara etimologis kata “artificial” konon berasal dari bahasa Latin “artificialis” yang berarti: dibuat dengan keterampilan manusia. Kata dasarnya adalah “artificium” yang terbentuk dari penggalan kata “ars/artis” (seni atau keterampilan) dan “facere” (membuat, melakukan).
Kata “buatan” sekilas terkesan tepat untuk digunakan dalam konteks ini, kendati kata ini sebenarnya berisiko menghadap-hadapkan manusia versus bukan manusia (Tuhan). Padahal, apa yang diklaim sebagai “buatan” manusia itu boleh jadi bukan karya manusia sepenuhnya. Dalam “artificial insemination” campur tangan manusia ditandai terutama pada tahap ketika sperma diinjeksi ke serviks atau rahim seorang perempuan dengan metode tertentu. Metode ini disebut artifisial karena berbeda dengan metode alami melalui hubungan seksual. Apabila metode ini berhasil membuat seorang perempuan hamil, maka kata “artifisial” sudah dapat dilekatkan pada proses itu, terlepas bahwa pembuahan selanjutnya akan berlangsung alami di dalam rahim ibu biologis dari janin tersebut. Dengan demikian, terminologi “buatan” (untuk menggantikan kata “artifisial”) berpotensi untuk diperdebatkan berkenaan dengan seberapa besar suatu intervensi manusia dapat disebut “buatan” (bukan lagi alami). Apabila sebelumnya dua subjek yang dihadapkan adalah manusia dan bukan manusia (Tuhan), maka dalam konteks “artificial intelligence” posisinya adalah manusia versus mesin.
Bagaimana dengan kata “intelligence”? Kata ini lazim diterjemahkan sebagai “kecerdasan”. Sebuah perangkat yang memiliki program kecerdasan tidak boleh sekadar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebuah kalkulator, misalnya, bukan termasuk kategori perangkat “AI” kendati ia mampu menjalankan operasi aritmetika berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan fungsi matematis lain mengikuti instruksi yang sudah diprogram secara tetap. Kalkulator bekerja secara deterministik mengikuti pola masukan (input), proses, dan keluaran (output). Kalkulator tidak dapat belajar beradaptasi menghadapi data baru dan tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Sebuah perangkat dapat disebut cerdas apabila ia belajar dari data, dapat mengambil keputusan atau memprediksi situasi baru, dan mampu beradaptasi dengan pola yang sebelumnya tidak diprogram secara eksplisit. Hal ini sejalan dengan kesepakatan dalam Konferensi Dartmouth tahun 1956, ketika para ilmuwan di sana mengklaim komputer bisa disimulasi agar dapat berpikir seperti layaknya manusia apabila komputer itu diperkuat dengan algoritma.
Di masyarakat sendiri, pelafalan “AI” /eɪ aɪ/ mengikuti fonetik bahasa Inggris akan tetap banyak digunakan daripada dieja mengikuti fonetik bahasa Indonesia. Situasinya berbeda dengan pelafalan “ATM” yang sudah sangat lazim diucapkan mengikuti fonetik bahasa Indonesia daripada mengikuti fonetik bahasa Inggris /ˈeɪ tiː ˈɛm/. Dengan demikian, opsi untuk mencari padanan kosakata “artificial intelligence” menjadi “akal imitasi” agar singkatan AI tidak mengalami perubahan, menjadi kurang tepat sasaran.
Memaknai “intelligence” sebagai “akal” dan bukan “kecerdasan” tidaklah terlalu keliru, namun tetap memiliki nuansa makna yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “akal” bermakna daya pikir (untuk memahami sesuatu dan sebagainya); pikiran; ingatan; jalan atau cara melakukan sesuatu; daya upaya; ikhtiar, sedangkan “kecerdasan” berarti perihal cerdas atau perbuatan mencerdaskan; kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman pikiran). Akal biasanya berkonotasi pada domain kognisi, sedangkan kecerdasan melebihi domain itu. Penyelesaian masalah dengan cara yang masuk akal dan cara yang cerdas, tentu berbeda.
Apabila “artificial intelligence” disepakati berpadanan dengan “kecerdasan artifisial”, maka singkatan “AI” kini harus diubah menjadi “KA”, sedangkan singkatan itu terlanjur populer sebagai kependekan dari “kereta api”. Oleh sebab itu dapat dipikirkan untuk membuat akronim dari “kecerdasan artifisial” itu, misalnya dengan menyebutnya “cerdal”. Dengan akronim tersebut kita dapat memadankan berbagai kosakata yang menggunakan “AI” dengan “cerdal”, bukan “KA”. Sebagai contoh, “AI ethics” dipadankan menjadi “tata krama cerdal” (etika cerdal) dan bukan “etika KA”.
Sebagai kesimpulan, tulisan ini mengusulkan agar “artificial intelligence” dipadankan dengan “kecerdasan artifisial” atau —jika ingin lebih singkat— dapat dipersingkat lagi dengan “cerdal”. (***)
REFERENSI:
1 https://www.tempo.co/ekonomi/komdigi-rampungkan-buku-putih-peta-jalan-ai-nasional-2057300



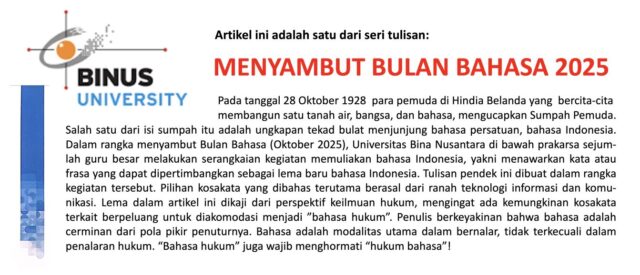
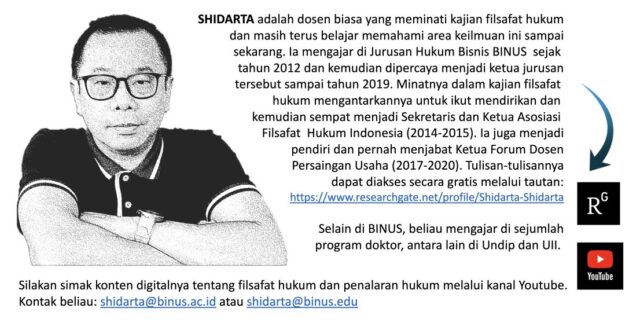
Comments :