DARI GAGAL BAYAR KE FRAUD: RISIKO DALAM FINTECH P2P LENDING
Oleh: ABDUL RASYID (Januari 2026)
Pendahuluan
Perkembangan layanan financial technology (fintech), khususnya fintech peer-to-peer lending (p2p lending) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), telah menghadirkan alternatif pembiayaan di luar lembaga perbankan. Menurut World Bank, fintech p2p lending merupakan model layanan keuangan yang memungkinkan individu atau entitas untuk meminjam dan meminjamkan dana secara langsung satu sama lain melalui platform online. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech p2p lending/LPBBTI merupakan sektor jasa keuangan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk meminjam uang atau menginvestasikan dana mereka melalui platform online, di mana platform berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman, dan mengenakan biaya atas layanan ini [1]. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa p2p lending melalui mekanisme digital hanya merupakan pihak perantara (pihak ketiga) yang mempertemukan pihak yang memiliki dana (lender) dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan (borrower) secara lebih cepat dan efisien.
Sumber: Roadmap LPBBTTI OJK 2023-2028
Saat ini fintech p2p lending berkembang dengan pesat. Menurut data statistik OJK bulan Agustus 2025, terdapat 96 penyelenggara fintech p2p lending yang berizin OJK, terdiri dari 89 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah[2]. Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai kasus gagal bayar (default) yang melibatkan penyelenggara fintech p2p lending. Kondisi ini terjadi di tengah pertumbuhan industri pinjaman daring yang cukup signifikan, di mana berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, outstanding pembiayaan fintech p2p lending mencapai sekitar Rp94,85 triliun per November 2025, dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) secara agregat meningkat hingga sekitar 4,33 persen pada periode yang sama [3]. Data ini menunjukkan bahwa seiring dengan ekspansi pembiayaan fintech p2p lending, risiko kredit bermasalah juga turut meningkat dan menjadi perhatian serius dalam pengawasan. Fenomena ini kemudian memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat serta perdebatan di ruang publik mengenai tingkat risiko dan keamanan pendanaan melalui fintech. Tidak jarang, setiap kasus gagal bayar langsung dipahami sebagai bukti kegagalan model bisnis fintech lending atau kelemahan pengawasan regulator.
Penting untuk dipahami bahwa tidak semua gagal bayar dalam fintech p2p lending memiliki karakter hukum yang sama. Terdapat perbedaan mendasar antara gagal bayar yang merupakan konsekuensi risiko pembiayaan dengan gagal bayar yang bersumber dari perbuatan fraud. Kesalahan dalam memahami perbedaan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penanganan hukum, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Gagal Bayar sebagai Risiko Pembiayaan dalam Fintech Lending
Dalam kegiatan pembiayaan, baik yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank, gagal bayar merupakan salah satu risiko inheren yang tidak dapat dihindari. Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari kegiatan intermediasi keuangan, di mana dana masyarakat disalurkan kepada pihak lain dengan harapan memperoleh pengembalian di kemudian hari.
Dalam konteks fintech p2p lending, gagal bayar pada dasarnya dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain kegagalan usaha penerima dana, perubahan kondisi ekonomi, kesalahan proyeksi arus kas, atau keadaan memaksa (force majeure). Pada kondisi demikian, pihak penerima dana pada prinsipnya memiliki iktikad baik, namun tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Secara hukum, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam hubungan perdata sebagaimana dikenal dalam hukum perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan wanprestasi sebagai kegagalan memenuhi prestasi yang diperjanjikan, yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perdata, seperti pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, maka gagal bayar tidak serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun merupakan bagian dari risiko usaha yang harus diperhitungkan sejak awal oleh para pihak.
Ketika Gagal Bayar Berubah Menjadi Fraud
Berbeda halnya apabila gagal bayar disebabkan adanya perbuatan penerima dana yang sejak awal mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan. Pada titik inilah gagal bayar mengalami pergeseran karakter hukum, dari sekadar risiko pembiayaan menjadi indikasi fraud. Indikasi tersebut dapat terlihat dari adanya rekayasa atau manipulasi proyek pembiayaan, penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada pemberi dana, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan, serta praktik penggunaan dana baru untuk menutup kewajiban lama. Perbuatan semacam ini secara substansial telah melanggar prinsip kejujuran dan transparansi yang menjadi dasar hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana.
Dalam perspektif hukum positif, tindakan yang memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi dapat diselesaikan semata-mata melalui mekanisme perdata. Apabila gagal bayar disertai dengan rangkaian kebohongan, penyampaian informasi yang menyesatkan, atau penyalahgunaan dana, maka perbuatan tersebut tidak lagi dapat dipahami sebagai wanprestasi semata. Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan bahwa perolehan keuntungan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan merupakan tindak pidana penipuan. Dalam konteks ini, gagal bayar merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar. Gagal bayar dalam konteks ini merupakan akibat dari perbuatan yang secara sadar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang melawan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap peristiwa semacam ini harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan pengawasan yang lebih tegas.
Kesalahan dalam mengklasifikasikan gagal bayar memiliki implikasi hukum yang serius. Apabila gagal bayar yang bersumber dari fraud diperlakukan sebagai risiko pembiayaan biasa, maka penanganan yang dilakukan cenderung terbatas pada langkah-langkah administratif dan restrukturisasi. Akibatnya, perbuatan yang seharusnya dihentikan sejak dini justru dibiarkan berlarut-larut sehingga potensi kerugian masyarakat semakin besar. Sebaliknya, apabila seluruh gagal bayar secara serampangan dipandang sebagai fraud, maka akan terjadi kriminalisasi risiko usaha yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, distingsi antara gagal bayar sebagai risiko pembiayaan dan gagal bayar sebagai akibat fraud menjadi sangat penting, baik bagi aparat penegak hukum, regulator, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan fintech p2p lending.
Peran Regulator dan Pentingnya Deteksi Dini
Dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan, regulator memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha penyelenggara fintech lending berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.
Pengawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada kepatuhan administratif dan pelaporan formal, tetapi juga harus mampu menilai substansi kegiatan usaha dan perilaku pelaku usaha terhadap konsumennya. Dalam konteks ini, rezim perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keunagan menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Deteksi dini terhadap pola-pola penyimpangan menjadi kunci untuk membedakan antara risiko pembiayaan yang wajar dan indikasi fraud, sehingga intervensi dapat dilakukan secara proporsional dan tepat waktu sebelum kerugian masyarakat semakin meluas.
Data Kasus dan Praktik di Lapangan
Dalam praktik, perbedaan antara gagal bayar sebagai risiko pembiayaan dan gagal bayar yang mengandung unsur fraud tercermin dari sejumlah kasus fintech p2p lending dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan fintech p2p lending (LPBBTI) mencapai sekitar Rp94,85 triliun per November 2025 dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) sekitar 4,33 persen. Peningkatan skala pembiayaan digital tersebut diikuti oleh meningkatnya eksposur risiko gagal bayar, yang pada tingkat tertentu dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih kompleks [3].
Pada satu sisi, terdapat gagal bayar yang disebabkan oleh penurunan kinerja usaha penerima dana secara masif, sehingga lebih tepat dipahami sebagai risiko pembiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme perdata. Namun pada sisi lain, ditemukan pula kasus gagal bayar yang disertai penyampaian informasi menyesatkan, penyalahgunaan dana, serta pola pembayaran kewajiban lama dengan dana baru, yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip transparansi dan itikad baik.
Kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) merupakan contoh konkret, di mana Otoritas Jasa Keuangan menemukan sejumlah indikasi kuat praktik fraud dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum, dengan nilai kerugian yang dilaporkan melebihi Rp2.4 triliun. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha terhadap beberapa penyelenggara fintech p2p lending yang tidak memenuhi ketentuan permodalan dan tata kelola. Data dan praktik tersebut menegaskan bahwa sebagian gagal bayar dalam fintech p2p lending berkorelasi dengan persoalan hukum yang serius dan memerlukan respons pengawasan yang tegas dan terukur [4].
Penutup
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa gagal bayar dalam fintech p2p lending tidak dapat dipandang secara tunggal. Terdapat perbedaan mendasar antara gagal bayar sebagai risiko pembiayaan dan gagal bayar yang bersumber dari perbuatan fraud. Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam menentukan pendekatan penyelesaian, baik melalui mekanisme perdata, pengawasan administratif, maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap karakter gagal bayar menjadi prasyarat penting dalam membangun tata kelola fintech p2p lendingyang sehat dan berkeadilan. Kesalahan dalam memahami dan mengklasifikasikan gagal bayar tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
Sumber:
[1] https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Documents/ROADMAP%20LPBBTI%20OJK%20Indonesia%20(1).pdf
[2] https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Agustus-2025.aspx
[3] https://keuangan.kontan.co.id/news/bertambah-24-fintech-lending-punya-twp90-di-atas-5-per-november-2025?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
[4] https://money.kompas.com/read/2025/12/28/102800226/gagal-bayar-fintech-lending-pada-2025–akseleran-dsi-hingga-crowde?page=all#page3




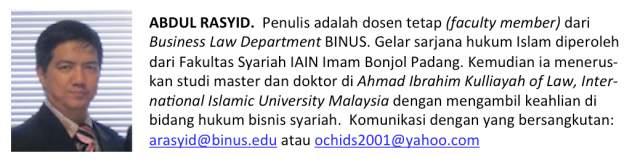
Comments :