KONSTITUSIONALITAS KEWARGANEGARAAN GANDA
Oleh SHIDARTA (November 2025)
Bagi kebanyakan diaspora Indonesia, baik yang masih memegang status kewarganegaraan Indonesia maupun yang sudah tidak lagi berstatus WNI, citarasa kuliner Indonesia pasti sesuatu yang selalu dirindukan. Oleh sebab itu, restoran Indonesia selalu menjadi daya tarik untuk mereka datangi, termasuk sebagai tempat mereka bertemu secara rutin. Demikianlah, di tengah gerimis yang membasahi kota Den Haag, pada awal November 2025, di sebuah kedai Indonesia bernama “Kopi-Kopi”, saya menghadiri pertemuan dengan lima orang diaspora Indonesia. Diskusi sambil santap malam ini terselenggara berkat bantuan Bu Monique Patricia, pendiri dan CEO BINA bv yang berkantor pusat di Groothandelsgebouw, Stationsplein, Rotterdam. Ikut hadir dalam santap malam ini rekan-rekan dari Center of Excellence in Governance & Policy Studies BINUS, yaitu Prof. Dr. Lindrianasari, Prof. Dr. Lim Sanny, dan Prof. Dr. Engkos Achmad Kuncoro. Diskusi menyasar ke banyak isu, seperti kebutuhan BINUS untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswanya untuk magang di perusahaan-perusahaan milik diaspora Indonesia di Belanda. Isu lain, yang ingin saya angkat dalam tulisan ini, adalah soal perjuangan diaspora mendapatkan status kewarganegaraan ganda.
Salah seorang tokoh diaspora Indonesia di Belanda, Pak Herman Syah, memulai dengan satu pertanyaan yang sangat reflektif. Ahli aerospace engineering yang kini beralih ke area software engineering dari perusahaan CNOC dan sudah tinggal di Belanda lebih dari tiga puluh tahun ini bertanya secara retoris: “Apakah status kewarganegaraan ganda itu melanggar konstitusi kita?”
Jika kita mengacu ke konstitusi, maka Pasal 26 ayat (2) UUD hanya menyatakan bahwa setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ayat ini mengubah redaksi ayat sebelum amandemen, yang menyatakan: “Syarat-syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang-undang.” Secara normatif, redaksi ayat yang lama sebenarnya lebih jelas, kendati secara substansial keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pasal 28D ayat (4) kemudian menegaskan bahwa perolehan status kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Hak ini terkait juga hak yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) untuk memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, meninggalkan Indonesia, dan kembali lagi ke Indonesia. Tidak ada terminologi “kewarganegaraan ganda” atau “dwikewarganegaraan” dalam UUD. Tampaknya hanya itu saja ketentuan yang relevan bersinggungan dengan persoalan yang dipertanyakan. Pesan yang termaktub dalam UUD memposisikan urusan kewarganegaraan sebagai open legal policy, yang dilimpahkan kewenangan pengaturannya ke format peraturan setingkat undang-undang. Jadi, kewarganegaraan ganda sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelanggaran konstitusi. Materi ini murni urusan politik hukum kewarganegaraan Pemerintah dan DPR sebagai otoritas pembentuk undang-undang.
Jawaban ini tentu sudah Pak Herman Syah ketahui sejak semula, mengingat lebih dari sepuluh tahun sudah terdapat kelompok kerja (working group) tentang imigrasi dan kewarganegaraan yang diberi label “Indonesian Diaspora Network-Global”, disingkat WGIK-IDN-Global (sebelumnya disingkat TFIK). Menurut situs resmi WGIK, berbagai upaya sudah dilakukan oleh para diaspora Indonesia untuk memperjuangkan kewarganegaraan ganda, antara lain dengan menerbitkan Buku Putih Perjuangan Diaspora Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda. Pak Herman Syah sendiri adalah Ketua WGIK untuk Negeri Belanda. Dengan status kewarganegaraan ganda itu mereka ingin agar diapora Indonesia tetap diakui secara resmi sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan dapat berperan serta dalam pembangunan Indonesia di segala bidang secara aktif dan leluasa.
Secara teori, ada sejumlah alasan negara-negara tertentu untuk menolak pemberian status kewarganegaraan ganda. Alasan ideologis merupakan dalih yang paling sering dikemukakan, bahwa negara-negara tersebut menghendaki loyalitas tunggal dari setiap warga negaranya. Dalih ini tentu terkesan naif, khususnya bagi kaum diaspora yang berpikir visioner. Terbukti negara-negara yang membuka diri terhadap politik hukum “kewarganegaran ganda” mampu menimba manfaat dari keberadaan para pemegang paspor ganda. Dari sisi keamanan nasional, juga tidak ada isu signifikan yang sangat mengganggu, sebagaimana telah dipraktikkan berbagai negara, termasuk oleh negara-negara berkembang seperti Filipina, Meksiko, dan India.
Sama seperti Indonesia, umumnya konstitusi negara-negara tersebut tidak menyinggung perihal kewarganegaraan ganda di dalam undang-undang dasar. Pengaturan urusan ini dilimpahkan ke level peraturan yang lebih rendah. Dalam undang-undang itupun sebenarnya cukup dinyatakan dengan satu ketentuan bahwa warga negara yang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain, tidak serta merta kehilangan status kewarganegaraannya. Nuansa yang lebih aktif dan moderat dapat dirumuskan sebagai berikut: “Warga negara yang telah melepaskan status kewarganegaraannya dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya itu tanpa harus melepaskan kewarganegaraan dari negara lain.”
Bagaimana dengan anak-anak hasil perkawinan campuran (pasangan berbeda kewarganegaraan)? Selama ini anak hasil perkawinan campuran memang diberi status kewarganegaraan ganda sampai ia dewasa, yaitu berusia 18 tahun atau menikah sebelum berusia 18 tahun. Dalam hal tidak ada pemilihan terkait kewarganegaraan (setelah berusia 18 tahun), maka hukum positif di Indonesia akan mengkualfikasikan orang tersebut sebagai bukan lagi warga negara Indonesia. Sikap terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran demikian juga perlu ditinjau ulang apabila Indonesia ingin sepenuhnya mengadopsi kepemilikan kewarganegaraan ganda. Hal yang sama juga berlaku bagi status anak-anak pasangan warga negara Indonesia yang lahir di negara-negara yang menerapkan sistem ius soli.
Di luar gaya penyikapan yang tegas, beberapa negara memakai strategi “malu-malu kuncing”. Artinya, secara umum mereka menolak pemberian kewarganegaraan ganda, tetapi dalam praktiknya tersedia celah untuk masuk. Isu dari celah seperti ini terkadang memang cukup sensitif, bahkan diskriminatif, misalnya negara akan melihat latar belakang etnisitas dan kemampuan finansial dari pemohon, sebagaimana yang diterapkan oleh India terhadap pemegang paspor dari Pakistan dan Bangladesh. Ada juga negara yang memberi status kewarganegaraan ganda tetapi kemudian melarang pemegang status ini untuk menduduki jabatan-jabatan publik tertentu.
Apa yang dapat disarankan di tengah situasi hukum positif di Indonesia saat ini? Apabila Indonesia ingin mengambil manfaat maksimal dari keberadaan diaspora Indonesia yang berkualifikasi tinggi, maka pemberian status kewarganegaraan ganda layak untuk dipertimbangkan. Perubahan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan memang harus tetap diperjuangkan, tetapi jalan lebih singkat dapat ditempuh dengan pengujian melalui Mahkamah Konstitusi (sepanjang dapat ditunjukkan adanya hak warganegara yang tercederai dari pengaturan kewarganegaraan dalam undang-undang itu). Hanya saja, pengajuan ke Mahkamah Konstitusi ini harus diberi catatan. Dengan mencermati apa yang sudah dilakukan beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, tampaknya agak sulit untuk meminta Mahkamah Konstitusi berubah pikiran dengan menyatakan bahwa larangan kewarganegaraan ganda (di luar yang berlaku bagi anak-anak pasangan perkawinan campuran) merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Paling jauh, Mahkamah akan mengatakan bahwa urusan ini adalah open legal policy. Sekalipun demikian, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sudah terkonfirmasi dan terklarifikasi bahwa urusan kewarganegaraan ganda pada hakikatnya tidak memiliki “hambatan konstitusionalitas” sama sekali.
Jadi, perjuangan para diaspora tetap perlu diarahkan kepada perubahan terhadap rumusan undang-undang. Alasan yang pragmatis harus ditekankan sebagai latar dari perlunya perubahan tersebut. Kekhawatiran yang selama ini disuarakan terhadap kewarganegaraan ganda dapat diminimalisasi, misalnya dengan memberlakukan seleksi ketat terhadap calon-calon penerima status kewarganegaraan ganda itu. Sebaiknya prioritas untuk menggunakan peluang ini diberikan kepada pemegang paspor Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama serta sudah berkarya dan berkontribusi nyata untuk kepentingan Indonesia. Tatkala mereka memperoleh kewarganegaraan dari negara domisili, maka mereka tidak serta-merta kehilangan status semula sebagai warga negara Indonesia. Pernyataan untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia harus dimohonkannya terlebih dulu, dalam arti tidak otomatis dikabulkan. Dalam hal ini harus ada proses pengkajian komprehensif dengan menggunakan tolok ukur yang konkret terkait kontribusinya selama ini. Tolok ukur itu dibuat transparan, bahkan wajib mendengar masukan dari Kedutaan Indonesia dan komunitas diaspora setempat. Agar isu keamanan nasional tidak muncul, mereka yang telah memperoleh kewarganegaraan ganda dibatasi untuk tidak menduduki jabatan-jabatan publik tertentu. Kebijakan demikian, paling tidak menjadi oasis kecil yang menandai langkah maju menyikapi isu kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. (***)
Di antara mereka terdapat …




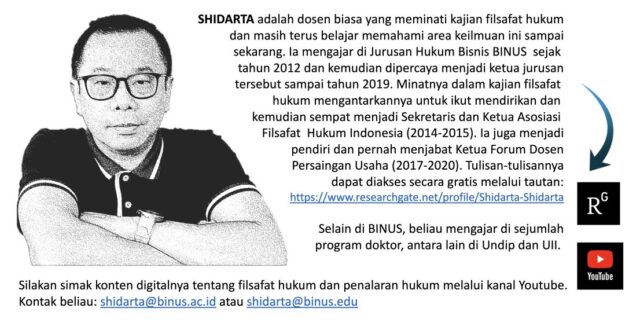
Comments :