STRATEGI SEMI-MONOLISTIK KUHP BARU TERHADAP UU TIPIKOR
Oleh SHIDARTA (Juni 2025)
Ada satu pertanyaan penting dari pemosisian KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya pasal-pasal yang ada di dalam Bagian Ketiga (Tindak PIdana Korupsi) dari Bab XXXV (Tindak PIdana Khusus). Pengaturan tentang tindak pidana korupsi dimuat dari Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Pertanyaan yang dimaksud adalah: apakah dengan adanya pasal-pasal di KUHP tersebut, berarti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU perubahannya, selanjutnya disebut UU Tipikor) telah kehilangan hakikatnya sebagai lex specialis?
Kendati secara maknawi, ketentuan di dalam KUHP itu sekilas terkesan mengambil alih redaksi dari UU Tipikor, ternyata ada perbedaan tekstual di dalam rumusan pasal-pasal tersebut. Misalnya, kata “dapat” yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah dihilangkan di dalam Pasal 603 KUHP. Juga ketentuan sanksi yang menyertai pasal itu, dari semula “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” menjadi “pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun”. Demikian juga dengan kata-kata untuk sanksi dendanya. Tulisan ini tidak akan secara khusus membahas soal perubahan redaksional ini. Fokus tulisan ini lebih ke pemosisian dari dua undang-undang di atas.
Pertama-tama, saya setuju untuk melabelkan UU Tipikor sebagai lex specialis. Penjelasannya dapat dicermati dari tiga aspek sekaligus. Pertama, kekhususannya terindikasi karena dinyatakan secara eksplisit di dalam UU Tipikor itu sendiri (wettelijke specialiteit). Dalam Penjelasan umum UU Tipikor, terdapat sejumlah kalimat yang menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan pelaksanaan ketentuan KUHP [yang lama] dan merupakan lex specialis terhadap ketentuan dalam KUHP itu. Kedua, kekhususannya terindikasi secara logis, yakni adanya tambahan unsur pada rumusan tindak pidana di dalam UU Tipikor itu dibandingkan dengan rumusan yang lebih umum di dalam KUHP (logische specialiteit). Dalam KUHP yang lama unsur-unsur seperti “melawan hukum”, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memang tidak ditemukan, tetapi muncul dalam UU Tipikor (lihat sebaran pengaturan dalam KUHP yang lama, antara lain dalam Pasal 209, 210, 415, 418, 419, 420, 423, 425). Ketiga, kekhususannya terindikasi secara sistematis, yakni apabila dilihat dari kaca mata sistem hukum secara keseluruhan (systematische specialiteit). Misalnya, UU Tipikor dipandang perlu diadakan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa karena sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Penegasan ini dapat ditemukan dalam konsiderans UU Tipikor dan Penjelasan Umum (lihat juga dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Perlu juga dicatat, bahwa pernyataan demikian juga tetap muncul di dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP yang baru. Artinya, seandainya tidak ada penegasan yang eksplisit tentang kekhususannya, kita dapat memaknai tindak pidana korupsi ini secara sistem pengaturan memang sudah mengandung kekhususan, antara lain terlihat dari keberadaan komisi tersendiri yang menanganinya berikut dengan hukum acaranya yang di sana-sini memiliki kekhususan.
Dengan berlakunya KUHP yang baru, maka kini muncul dua asas yang saling berhadapan dan perlu kita pertanyakan mana yang harus diprioritaskan, yaitu asas lex specialis derogat legi generali atau asas lex posterior derogat legi priori? Asas yang pertama mengacu pada ruang lingkup pengaturannya (yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum), sedangkan asas yang kedua merujuk pada waktu keberlakuan (yang terakhir mengalahkan yang lebih awal). Pertanyaan ini menjadi relevan, misalnya, ketika ada permohonan uji material terhadap eksistensi pasal-pasal di dalam UU Tipikor, lalu apakah berarti ketentuan dalam Bab XXXV Bagian Ketiga dari KUHP juga akan ikut terpengaruh, mengingat pasal-pasal terkait dalam KUHP yang baru tidak ikut dimohonkan pengujiannya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pertama-tama harus dilihat bagaimana strategi meletakkan KUHP kita yang baru berhadapan dengan UU Tipikor. Dilihat dari historisnya, kita menggunakan strategi dualistik, yaitu KUHP sebagai lex generalis, sedangan UU Tipikor sebagai lex specialis. Keduanya sengaja dipisahkan secara tegas. Ada strategi lain yang sedikit dimodifikasi seperti yang digunakan oleh Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini menggunakan cara fragmentaris, yaitu dengan sengaja menyebar pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam sejumlah undang-undang, sehingga tiap jenis korupsi memiliki undang-undang, dan boleh jadi juga, yurisdikasi berbeda-beda. Hanya saja, kendati semula terfragmentasi, pada akhirnya tetap ada integrasi di tingkat federal (fragmented but integrated). Barangkali ada pandangan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia punya kecenderungan serupa, mengingat terkadang tindak pidana korupsi ditangani oleh Kejaksaan, tetapi pada kasus lain lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kira perlu analisis lebih jauh untuk tidak buru-buru menilainya sebagai suatu kecenderungan ke arah fragmentaris ala Amerika.
Situasi yang menarik adalah justru dengan mencermati adanya fenomena baru yaitu arah pendekatan kebalikan dari strategi dualistik itu. Saya menyebutnya sebagai monolistik, dalam arti rumusan pasal-pasal yang semula ada di dalam UU Tipikor (lex specialis) digiring masuk ke dalam KUHP yang baru (lex generalis). Strategi seperti ini sangat mungkin terjadi apabila pembentuk undang-undang menginginkan agar kodifikasi (dalam hal ini KUHP) dipakai sebagai pusat penormaan hukum pidana kita (lex generalis-oriented system). Hal ini sejalan juga dengan cukup nyaringnya suara-suara yang mengatakan KUHP kita yang baru telah memberi angin segar bagi reformasi hukum pidana kita (lex generalis reformentis), sehingga semua tafsir terhadap peraturan hukum pidana harus juga berpatokan pada semangat yang baru ini.
Oleh karena pembentuk KUHP yang baru tidak cukup tegas mendudukkan UU Tipikor ini (mungkin juga karena kekhawatiran politis, sosiologis, dan psikologis setiap kali kita menyinggung perubahan UU Tipikor), akhirnya penyikapannya pun menjadi ambigu. KUHP yang baru sebagai lex posterior (dari sisi waktu berlaku) tidak memuat klausula pencabutan untuk memenangkan posisinya (derogasi ekspres) terhadap UU Tipikor. Jadi, saya menyimpulkan situasi ini sebagai sebuah penyikapan yang semi-monolistik. Artinya, di satu sisi ada keiginan membawa masuk pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP yang baru, tetapi di sisi lain tetap membiarkan UU Tipikor sebagai lex specialis. Dalam suasana semi-monolistik seperti itu, KUHP selayaknya memiliki peran dominan dalam memaknai unsur-unsur tindak pidana korupsi, dengan catatan bahwa beberapa ketentuan dari UU Tipikor itu masih tetap efektif berlaku.
Untuk memastikan kapan dominasi KUHP vis-a-vis UU Tipikor itu di dalam penanganan kasus per kasus, sungguh tidak mudah dicarikan suatu jawaban tunggal. Kita membutuhkan metode penemuan hukum atau asas hukum untuk membantu menjawabnya. Tentu saja, di luar asas lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori yang jelas-jelas membawa kita ke persilangan jalan.
Pertama, kita dapat memakai metode penemuan hukum berupa penafsiran sistematis. Latar belakanganya adalah karena KUHP yang baru dibentuk dalam rangka membangun suatu sistem hukum pidana yang lebih reformis. Semangat ini adalah kehendak dari pembentuk KUHP yang baru dan wajar apabila semangat reformatif itu diletakkan dalam kodifikasi hukum pidana nasional kita (lex generalis reformentis). Apabila kita mencoba meminjam istilah yang diperkenalkan oleh ahli hukum Romawi, antara lain ketika mereka menyebut adanya kehendak untuk memiliki suatu benda (animus domini) atau kehendak untuk menguasai (animus possidendi), maka untuk situasi ini kita boleh juga menyebutnya sebagai adanya kehendak untuk mengkodifikasi (animus codificandi), Strategi semi-monolistik dalam mendudukkan KUHP yang baru terhadap UU Tipikor membawa konsekuensi bahwa norma-norma di dalam lex specialis sudah terintegrasi ke dalam kodifikasi yang baru ini, sehingga yang diprioritaskan adalah kehendak dari pembentuk kodifikasi. Alhasil, penafsiran sistematis akan mendahulukan tafsir yang dibuat oleh pembentuk KUHP daripada tafsir dari pembentuk UU Tipikor.
Kedua, kita dapat meminjam dari asas lex mitior. Dalam hal ini, perlu dicermati dulu mana formulasi dari dua undang-undang yang kita persoalkan, yang merumuskan akibat hukum lebih meringankan. Para ahli hukum pidana dapat dengan mudah membandingkan, misalnya, dengan menyandingkan ketentuan pidana penjara paling singkat empat tahun pada suatu undang-undang dan paling singkat dua tahun pada undang-undang lainnya. Demikian juga dengan kategori-kategori dendanya. Perlu dicatat bahwa asas lex mitior memiliki perbedaan dengan asas in dubio pro reo. Asas in dubio pro reo muncul ketika hakim ragu-ragu dalam memutuskan, sehingga hakim diarahkan untuk memilih opsi yang lebih menguntungkan bagi si terdakwa. Penerapan asas ini lebih kasuistik, karena basisnya adalah fakta yang terjadi di persidangan, bukan sekadar membandingkan rumusan sanksi yang tercantum di dalam undang-undang. Sebagai contoh, apabila hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah si terdakwa benar-benar telah melakukan korupsi atau tidak, maka hakim seyogianya memilih untuk membebaskan terdakwa. Dengan demikian, asas lex mitior merujuk pada situasi tatkala terjadi kekaburan normatif, sedangkan asas in dubio pro reo lebih mengacu pada keraguan subjektif [dari hakim] terhadap fakta yang terungkap di persidangan.
Saya membutuhkan pandangan para ahli hukum pidana untuk mengeleborasi lebih jauh isi tulisan ini. Namun, secara hipotetis, saya melihat sementara ini ada tendensi untuk mengatakan bahwa dalam strategi semi-monolistik KUHP yang baru terhadap UU Tipikor, akan membawa kita kepada pilihan pemaknaan yang mengarah ke rumusan menurut kodifikasi. Wallahualam. (***)

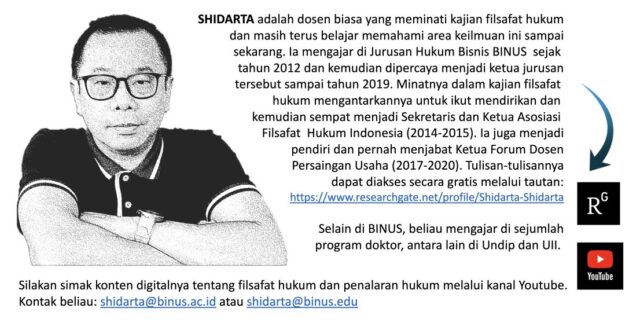
Comments :