PENDIDIKAN TERSIER VERSUS KEBUTUHAN TERSIER DAN TITIK TEMU MORALITAS FULLER
Oleh SHIDARTA (Juni 2024)
Sebagai pelanggan dan pembaca Majalah Tempo, saya terbilang cukup rajin menyimak media ini, termasuk aktivitasnya di jejaring online. Tempo dapat saya anggap sebagai salah satu barometer kebebasan pers di Indonesia. Majalah yang mengusung jurnalisme berkualitas ini saya pikir harus tetap kritis.
Pada akhir Mei lalu, media ini menayangkan podcast Apa Kata Tempo dengan episode nomor S2E143 yang berjudul “Biaya UKT Melejit, Ada Upaya Komersialisasi Pendidikan?” Di situ ada dialog dengan Pemred Tempo, mengangkat isu tentang kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri. Isi podcast tersebut sebagian besar memuat kritik terhadap kebijakan Kementerian Dikbudristek berkenaan dengan peningkatan biaya kuliah, sehingga terkesan kuat telah terjadi komersialisasi pendidikan. PTN seakan menjadi BUMN yang didorong mencari cuan saja. Begitu cuplikan yang dapat ditangkap dari dialog itu. Tidak ada yang salah sebenarnya atas kritik-kritik semacam itu. Namun, ketika Pemred Tempo sampai pada komentarnya berkenaan dengan ucapan Dirjen Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan tersier, saya lalu menjadi bertanya-tanya. Apa yang salah dengan ucapan tersebut?
Apakah pendidikan tinggi itu adalah pendidikan primer, sekunder, atau tersier? Jika mengacu kepada pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pendidikan tinggi jelas adalah pendidikan tersier. Namun, tidak berarti PBB ingin menjadikan pendidikan tingkat tersier ini menjadi kebutuhan tersier. Dalam laman resmi PBB secara eksplisit dituliskan bahwa Sustainable Development Goals (SDG) poin keempat tentang pendidikan berkualitas sudah memberi penekanan agar ada akses yang makin terbuka bagi semua orang untuk mencapai pendidikan tinggi. “SDG4 includes access to higher education in its 3rd target: “By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university,” tulisnya.
Bank Dunia dalam laman resminya menulis dengan nada yang kurang lebih sama, sebagai berikut:
Tertiary education refers to all formal post-secondary education, including public and private universities, colleges, technical training institutes, and vocational schools. Tertiary education is instrumental in fostering growth, reducing poverty, and boosting shared prosperity. A highly skilled workforce, with lifelong access to a solid post-secondary education, is a prerequisite for innovation and growth: well-educated people are more employable and productive, earn higher wages, and cope with economic shocks better.
Setelah saya membaca transkrip dari dialog di Podcast Tempo itu, saya dapat memaham, bahwa memangi telah terjadi kerancuan dalam membedakan makna antara pendidikan [tingkat] tersier dengan kebutuhan tersier. Hal ini tercermin dari komentar Tempo bahwa pendidikan tinggi itu sebagai barang mewah. Transkrip dari potongan dialog itu tertulis seperti di bawah ini:
Klarifikasi bahwa yang dimaksud oleh Dirjen Pendidikan Tinggi tentang pendidikan tersier di sini adalah bahwa pendidikan tersebut berada pada tingkatan ketiga setelah pendidikan dasar dan menengah, tampaknya sudah pernah juga disampaikan berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji di Program Metro Siang, tanggal 25 Mei 2024. Pernyataannya lalu dimuat kembali oleh medcom.id dengan judul “Jangan Salah Paham, Pendidikan Tersier dan Kebutuhan Tersier Beda Makna.” Saya tidak bermaksud untuk mengulangi penjelasan tersebut. Saya hanya ingin memberi catatan kecil bahwa seharusnya kerancuan seperti ini tidak diteruskan.
Kepedulian kita semua agar pendidikan tinggi tidak menjadi “barang” mewah, tentu kita sepakati. Demikian juga dengan kewajiban negara untuk menyiapkan sarana dan prasarananya. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertemukan antara kewajiban negara dan hak warga atas pendidikan tinggi tersebut? Untuk menelusuri jawabannya, kita bisa meminjam landasan berpikir yang disampaikan oleh Lon L. Fuller. Ia pernah menyebut tentang moralitas aspirasi (morality of aspiration) dan moralitas kewajiban (morality of duty). Mari kita pinjam analisis Fuller!
Menurut Fuller, moralitas aspirasi itu adalah cita-cita moral yang ingin dicapai oleh individu per individu. Jadi ini seharusnya suatu standar etika yang sangat tinggi, yang bertujuan mencapai kebajikan atau kebaikan tertentu. Katakan, misalnya, keinginan bersekolah setinggi mungkin (sampai tingkat perguruan tinggi) adalah sebuah kebaikan yang menjadi aspirasi individu-individu di Indonesia saat ini. Persoalannya adalah bahwa ketika kita ingin menetapkan standar ini menjadi sebuah kebijakan publik, misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kita harus hati-hati untuk tidak langsung menggunakannya begitu saja. Di sini Fuller lalu memperkenalkan konsep kedua yang disebutnya moralitas kewajiban.
Moralitas kewajiban bersinggungan dengan kewajiban dasar yang harus dipatuhi untuk menjaga ketertiban sosial dan pada hakikatnya ia akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap orang. Moralitas inilah yang biasanya dipakai sebagai tolok ukur dalam merancang hukum positif. Alasannya jelas, yaitu ia lebih menjamin ketercapaian karena relatif disepakati semua orang. Dalam konteks berhukum, moralitas kewajiban ini dapat dipilah lagi menjadi moralitas dalam (inner morality) dan moralitas luar (outer morality). Pemilahan ini tidak akan kita bahas lebih jauh dalam tulisan ini.
Kendati sudah terdapat moralitas kewajiban dan itu ditetapkan sebagai standar yang ingin dipenuhi, negara sebagai pembentuk hukum positif juga perlu mengukur diri apakah sanggup memenuhi aspirasi tersebut dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Jika ternyata tidak sanggup, maka negara harus membuat kompromi-kompromi. Misalnya, apabila moralitas kewajiban yang terkait tingkat pendidikan bagi warganya sudah ditetapkan sampai jenjang pendidikan tinggi, maka harus dicari tahu: seberapa kesanggupan negara memenuhi tingkat wajib belajar sampai pada level setinggi itu. Apabila tidak mampu, maka moralitas kewajiban itupun mungkin saja terpaksa tidak diakomodasi dulu dan negara memutuskan untuk menurunkan penerimaan standarnya ke tingkat pendidikan yang lebih rendah.
Sekarang kita perlu bertanya: apakah keinginan kita di Indonesia untuk memberi akses seluas-luasnya bagi warga kita mencapai pendidikan tinggi itu sudah menjadi moralitas kewajiban atau masih moralitas aspirasi dari individu-individu kelompok tertentu? Senyampang sudah menjadi aspirasi seluruh warga masyarakat, atau paling tidak sebagian besar masyarakat, maka berarti standar itulah yang seyogianya dipegang oleh negara tatkala ia menetapkan suatu kebijakan, termasuk di dalam membuat peraturan. Alasannya adalah karena standari itu sudah menjadi moralitas kewajiban. Negara yang sudah sanggup menunaikan suatu moralitas kewajiban, tidak boleh mengelak untuk mengemban tanggung jawab dalam mewujudkannya.
Di sejumlah negara yang memiliki kemampuan [finansial] untuk menyediakan fasilitas pendidikan tinggi bagi seluruh warganegaranya, pada umumnya akan membebaskan biaya pendidikan sampai pada level itu. Negara tersebut akan komit untuk membiayai pendidikan warganya sampai pada tingkatan setinggi mungkin yang diinginkan dan mampu ditempuh warga tersebut. Pada titik ini terlihat pertemuan antara moralitas aspirasi dan moraitas kewajiban. Negara seperti ini dapat didaulat sebagai negara yang membahagiakan waganya.
Nah, kita di Indonesia sepertinya belum sampai pada wacana “negara yang membahagiakan.” Kita bahkan belum terpikir untuk mencari tahu di mana titik temu antara dua moralitas yang dimaksud oleh Fuller. Kita seakan masih pada level meributkan urusan-urusan semantik. seperti pendidikan tersier versus kebutuhan tersier. (***)



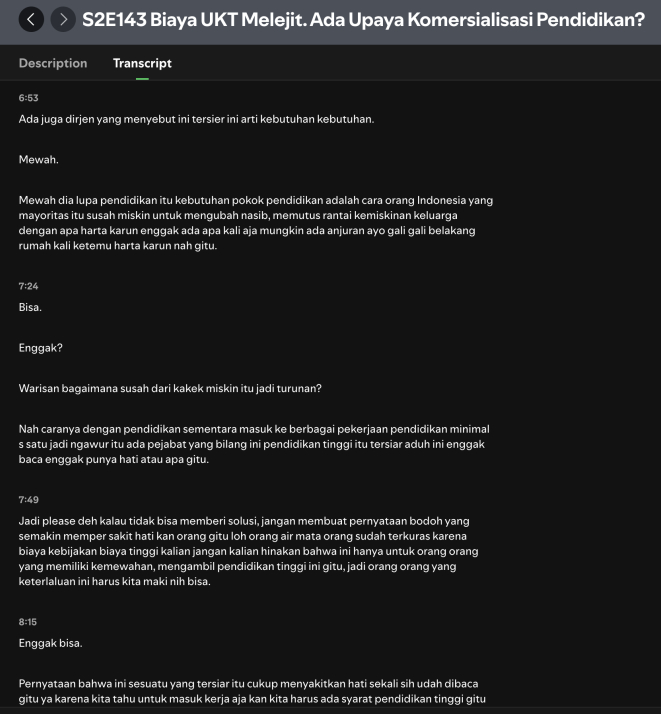
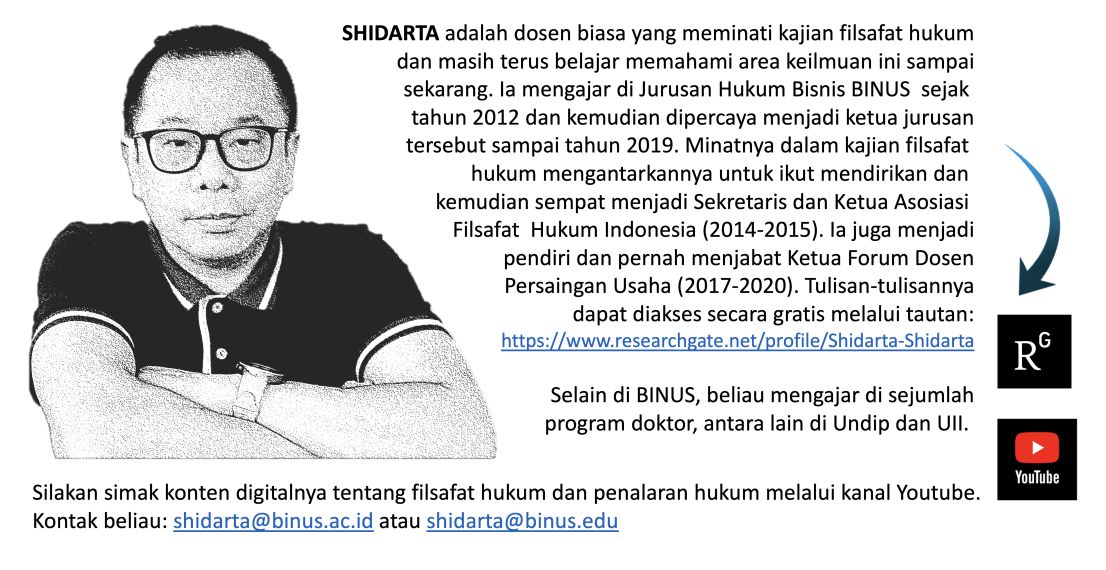
Comments :