KEPATUHAN YANG DISERTIFIKASI
Oleh SHIDARTA (April 2024)
PT Timah Tbk akhir-akhir ini sedang disorot banyak orang karena disinyalir telah melakukan kejahatan korupsi yang fantastis, dengan merugikan negara dan merusak lingkungan dengan taksiran uang senilai Rp271 trilyun rupiah. Menurut laporan Majalah Tempo (edisi 31 Maret 2024), sementara ini memang baru ditetapkan sebanyak 14 orang tersangka, termasuk petinggi PT Timah. BUMN ini ditengarai berkomplot dengan beberapa perusahaan memanipulasi hasil pengolahan timah ilegal. Kerja sama itu sudah berlangsung selama 2015-2022. Di dalam laporan majalah itu diilustrasikan bahwa PT Timah bermain mata dengan memberi keistimewaan kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi menampung hasil penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka-Belitung. Inti skenarionya adalah berupa tindakan “melegalkan” yang ilegal. Lebih ironis lagi, praktik ini dilakukan secara diskriminatif, sehingga pelaku usaha ilegal yang tidak ikut diajak dalam permainan kongkalikong ini akhirnya tersingkirkan dan berhenti beroperasi.
Saya tidak ingin mengulik lebih jauh keruwetan skenario korupsi di atas. Sebagai seorang yang meminati kajian hukum persaingan usaha, saya mencoba mencari tahu apakah PT Timah Tbk pernah membuat komitmen bahwa perusahaan itu sadar terhadap perilaku berusaha yang sehat, termasuk tentu saja komitmennya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelusuran saya menemukan satu sekuens dari dokumen yang dirilis oleh PT Timah Tbk mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil, tepatnya pada halaman 663-665. Di dalam halaman awal ada “janji-janji surga” PT Timah Tbk untuk tidak akan terlibat korupsi. Saya tidak ingin mengajak pembaca untuk menelaah isi halaman tersebut, melainkan lebih berminat mencermati deskripsi pada halaman terakhir, yang isinya lebih dekat dengan topik persaingan usaha. Saya dapat tunjukkan tampilannya sebagai berikut:
Di situ dinyatakan bahwa dalam operasionalnya sehar-hari PT Timah tunduk dan taat terhadap pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Sebagai buktinya, PT Timah menunjuk pada tidak terdapatnya laporan pelanggaran persaingan usaha yang diterima Perseroan. Lalu pada poin berikutnya, PT Timah berkesimpulan bahwa penerapan operasi yang adil di perseroan (terkait CSR, yang di dalamnya terkandung aspek persaingan usaha), dapat dilihat dari kepatuhan pelaku usaha itu terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakannya sanksi dalam perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan. Saya nanti akan memberi komentar tentang pernyataan tersebut pada bagian akhir tulisan ini.
Sekarang saya coba membayangkan: apa yang terjadi jika PT Timah Tbk ini termasuk dalam daftar perusahaan yang telah mendaftarkan diri untuk ikut dalam Program Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022? Saya tidak dapat memastikan apakah PT Timah ada dalam daftar perusahaan yang sudah mendaftarkan diri karena nama-nama perusahaan pendaftar tidak dimuat dalam situs KPPU. Saya cuma sedikit bernapas lega, bahwa setidaknya saya belum menemukan (di dalam tautan penetapan KPPU) berkenaan dengan perusahaan yang telah menerima penetapan program kepatuhan dari KPPU. Artinya, asumsi kita adalah bahwa PT Timah memang belum mendaftar dan karena itu belum pernah menerima penetapan. Atas asumsi seperti itu, justru ada baiknya kejadian di PT Timah Tbk ini dapat dijadikan iktibar tentang bagaimana apabila ada pelaku usaha seperti PT Timah yang telah mendapat penetapan kepatuhan, tetapi kemudian melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999. Tulisan singkat ini akan mencoba sejenak merefleksikannya.
Untuk itu, kita tentu perlu menengok ke dasar hukum dari penetapan program kepatuhan yang diluncurkan oleh KPPU. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. KPPU menyampaikan dalam salah satu beritanya, bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, telah tercatat puluhan pelaku usaha yang mendaftarkan diri mengikuti program kepatuhan ke KPPU. Untuk itu KPPU terus mendorong agar pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas program kepatuhan tersebut, guna mengurangi risiko bisnis akibat pelanggaran maupun potensi pelanggaran persaingan usaha yang ada. Mekanisme yang ditempuh adalah dengan cara pelaku usaha melakukan penyusunan program kepatuhan secara mandiri dan mendaftarkannya ke KPPU untuk dievaluasi. Dokumen program kepatuhan yang disampaikan berupa (i) dokumen kode etik; (ii) dokumen panduan kepatuhan; dan (iii) pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan. Berdasarkan evaluasi, sidang Komisi dapat menyetujui program kepatuhan tersebut dan dituangkan dalam Penetapan Program Kepatuhan. Penetapan ini berlaku selama lima tahun. Apabila di kemudian hari terbukti pelaku usaha itu melanggar UU No. 5 Tahun 1999, ia dapat diberikan keringanan atas sanksi denda yang akan dijatuhkan.
Substansi dari dasar hukum ini menarik karena keringan sanksi itu ternyata tidak diberikan terhitung sejak penetapan KPPU diterbitkan, melainkan sudah terhitung berlaku sejak pelaku usaha mendaftarkan keikutsertaannya dalam program ini (lihat Pasal 5 ayat [4] Perkom No. 1 Tahun 2022). Jadi, seandainya PT Timah seperti dicontohkan di atas sudah pernah mendaftar, ia sudah layak mendapat keringanan apabila perilakunya berkenaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 diproses oleh KPPU. Kata “dapat” di sini memperlihatkan adanya hak atau diizinkan untuk diberi. Baru mendaftarkan saja sudah berhak, apalagi jika sudah menerima penetapan. Perlakuan demikian terbilang luar biasa dan sangat tidak lazim dalam penalaran hukum. Sebab, jika patokannya adalah pendaftaran, maka sampai kapanpun catatan pernah mengajukan pendaftaran itu tidak pernah dapat dihapus. Perkom No. 1 Tahun 2022 juga tidak pernah mengatakan bahwa hak atas keringanan “sejak pendaftaran” itu akan hapus apabila KPPU tidak menyetujui (jika memang ada pilihan untuk tidak menyetujui itu) atas program kepatuhan yang diajukan oleh pelaku usaha.
Hal lain yang menarik diperbincangkan adalah tentang keberadaan dokumen yang disebut sertifikat. Dalam praktiknya, KPPU mengeluarkan sertifikat sebagai kelanjutan dari diterbitkannya penetapan program kepatuhan. Hal ini dapat diketahui karena perusahaan-perusahaan yang menerina sertifkat secara demonstratif melakukan seremoni penyerahan sertifikat ini. Suasananya ceria mirip seperti ketika penyerahan sertifikat ISO. Padahal, kata “sertifikat” tidak pernah tercantum dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dasar penerbitan sertifikat ini juga layak dipertanyakan. Tindakan menerbitkan sertifikat ini, disadari atau tidak disadari, sesungguhnya berpeluang memelesetkan program kepatuhan ini menjadi program sertifikasi. Padahal, KPPU jelas-jelas tidak pernah didesain dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai lembaga sertifikasi. Kita mungkin dapat mengatakan ini bagian dari “kreativitas” atau kata sertifikat di situ sama dengan piagam saja. Apapun alasannya, ada implikasi yang perlu direnungkan dalam-dalam.
Selanjutnya, kitra dapat menelisik apa saja dokumen yang dipakai sebagai tolok ukur bagi KPPU untuk menyetujui [atau tidak menyetujui] pendaftaran pelaku usaha “lulus” dari program kepatuhan ini. Mari kita membaca salah satu contoh penetapan yang dikeluarkan oleh KPPU..! Misalnya, yang termutakhir adalah penetapan untuk PT Grab Teknologi Indonesia (Penetapan Nomor 14/KPPU-PKP/2023) Di situ dikatakan, bahwa KPPU menyetujui mengeluarkan penetapan setelah KPPU:
- membaca Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari perlaku usaha tersebut;
- membaca Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Validasi oleh Verifikator terhadap Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari pelaku usaha tersebut;
- mendengar Evaluasi Komisi terhadap Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan dari pelaku usaha tersebut;
- mendengar Evaluasi Komisi terhadap Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Validasi dari Verifikator;
- membaca Perbaikan atas Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Validasi dari Verifikator.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, andalan KPPU sebenarnya terletak pada laporan hasil verifikasi dan/atau (jadi bisa salah satunya saja?) validasi dari verfikator. Siapa verifikator ini dan bagaimana pola pengangkatannya? Perkom Nomor 1 Tahun 2022 sama sekali tidak menyebutkan, bahkan kata “verifikasi” dan/atau ” verifikator” juga tidak ditemukan di sana. Padanannya mungkin ada pada kata “evaluasi” dalam Pasal 11. Namun, apakah terminologi verifikasi dan evaluasi itu dapat dipersamakan, tentu perlu ada penjelasan. Hal ini perlu digarisbawahi karena KPPU terlihat sangat mengandalkan peran verifikator dalam memberikan keputusan.
Tentu saja masih ada sejumlah catatan lain, tetapi saya ingin kembali ke cerita awal tentang menjadikan PT Timah Tbk sebagai suatu kasus hipotetis. Senyampang PT Timah ini telah mengajukan pendaftraran atau bahkan telah mendapat penetapan (+sertifikat) program kepatuhan, bagaimana KPPU seyogianya mengambil sikap terhadap perusahaan ini?
Pertama-tama kita dapat membayangkan gambaran kualitas pemahaman sebuah perusahaan yang dapat kita serap dari isi rilis CSR tentang kepatuhan atas iklim persaingan usaha yang sehat dan wujud dari perilaku berusaha yang adil. Kendati kita dapat berkelit bahwa pernyataan sependek itu tidaklah menggambarkan realitas, tetapi saya menangkap memang ada “kebingungan” mereka untuk menarasikan dan menunjukkan apa bukti yang lebih meyakinkan lagi selain kata-kata seperti itu. Akibatnya, redaksi yang hadir adalah pernyataan yang sangat sederhana, normatif, dan sangat formalistis, yaitu bahwa PT Timah belum pernah dilaporkan ke KPPU dan belum pernah dijatuhi sanksi. Itulah ukuran kepatuhan dan perilaku adil.
Hal ini menyulut kekhawatiran kita apabila data dan informasi semacam itulah yang tersaji di dokumen dan kemudian diterima oleh evaluator (atau verifikator) yang ditunjuk oleh Komisi. Sementara itu, evaluator tidak punya waktu memadai untuk mengecek rekam jejak, juga menghubungi rekanan kerja dari pelakku usaha, atau bahkan ke masyarakat (dalam Perkom disebut “konsumen”). Padahal, evaluasi secara empiris mengenai rekam jejak dari sebuah perusahaan menentukan posisi berdiri (existing position) dari perusahaan itu pada saat akan dinilai. Jangan sampai terjadi program kepatuhan ini hanya memotret [di atas kertas] komitmen ke depan, tetapi mengabaikan perjalanan di masa lampau yang notabene masih sangat kasatmata terlihat. Dengan posisi berdiri yang berbeda, maka program kepatuhan yang dievaluasi oleh KPPU terhadap tiap-tiap pelaku usaha tidak boleh sama. Untuk pelaku usaha dengan rekam jejak dengan catatan negatif tertentu, misalnya, ia harus diberi perhatian khusus. KPPU bahkan harus berani menolak untuk memberikan penetapan (persetujuan) apabila ada keraguan terhadap kemampuan perusahaan itu menjalankan komitmennya, mengingat mungkin catatan historis perusahaan itu memang tidak cukup meyakinkan. Atau, kalaupun diberikan penetapan juga, ia tidak perlu diganjar dengan kurun waktu keberlakuan maksimal (lima tahun).
Hal lain yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai program kepatuhan berkembang menjadi semacam program “pemutihan” atau “pencucian” atas citra negatif yang terlanjur melekat pada pelaku usaha tertentu. Apabila KPPU di kemudian hari menerbitkan penetapan (+sertifikat) terhadap perusahaan-perusahaan berkaliber seperti itu, maka dikhawatirkan justru dapat menjadi bumerang terhadap kepercayaan publik terhadap KPPU. Komisi bakal dinilai tidak profesional dan tidak sensitif terhadap pandangan masyarakat. Serangan balik terhadap Komisi akan mudah terjadi karena dapat dipastikan perusahaan-perusahaan yang telah mendapat penetapan (+sertifikat) seperti itu biasanya akan sangat senang untuk memamerkan “anugerah” itu, sekaligus sebagai [re-]branding perusahaan. Indikator dari sikap seperti itu dapat dilihat dari seremoni dan pemberitaan yang menyertai penyerahan sertifikat KPPU selama ini.
Dalam hal ada pelaku usaha yang sudah mendaftarkan diri ikut program kepatuhan, tetapi di kemudian hari melakukan pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999 (apalagi perusahaan itu juga telah dikenai sanksi pelanggaran pidana atas kejahatan tertentu), maka KPPU sebaiknya tidak langsung memberi keistimewaan bagi yang bersangkutan, berupa kepastian pengurangan sanksi denda. Kepastian untuk memberi pengurangan sanksi seperti itu, berisiko memicu paradoks dalam sistem penegakan hukum karena di satu sisi ada lembaga yang menghukum (tergolong berat), sementara KPPU mengambil jalan berbeda. Oleh sebab itu, jalan terbaik adalah seyogianya “janji” untuk menggaransi atau mendiskon sanksi jangan ditonjol-tonjolkan oleh KPPU sendiri. Lagi pula Pasal 5 ayat (4) Perkom No. 1 Tahun 2022 tidak bermakna seperti itu. Tanpa harus dijanjikan pun, dengan kewenangan diskresioner yang dimiliknya, komisioner KPPU dapat menjadikan sesuatu hal yang logis dan relevan sebagai faktor peringan. Dengan perkataan lain, pertimbangan keringanan karena pernah mendaftarkan diri itu tidak harus mengikat KPPU untuk wajib memberikannya. “Janji” seperti itu tidak seharusnya pula dipakai sebagai magnet agar pelaku usaha berbondong-bondong mendaftarkan diri dalam program kepatuhan. Kecenderungan seperti itu justru layak dicurigai karena mungkin saja ada “udang di balik batu” dari antusiasme pelaku usaha untuk mendaftarkan diri.
Dengan demikian, tulisan ini sama sekali jauh dari pretensi untuk mengatakan bahwa program kepatuhan ini harus diakhiri atau tidak boleh dilanjutkan. Filosofi dari program kepatuhan ini tentu tetap ada pembenarannya, kendati harus diakui juga bahwa teknis operasionalnya berpeluang untuk melenceng apabila tidak dilengkapi dengan rambu-rambu (aturan main) yang jelas dan transparan. Namun, apabila KPPU memang belum benar-benar siap dengan rambu-rambu tadi, disarankan agar dilakukan moratorium sementara waktu. Diskusi dengan banyak pihak, sambil mengevaluasi perkembangan atas pelaku-pelaku usaha yang sudah diberikan penetapan, harus dilakukan segera. Di samping itu, pengalaman penerapan program serupa di negara-negara lain layak pula dijadikan rujukan dengan melihat kesesuaiannya dengan atmosfer persaingan usaha di Indonesia. Catatan-catatan kecil di atas, boleh jadi dapat menjadi perhatian dan perbaikan atas program ini dalam waktu dekat. (***)




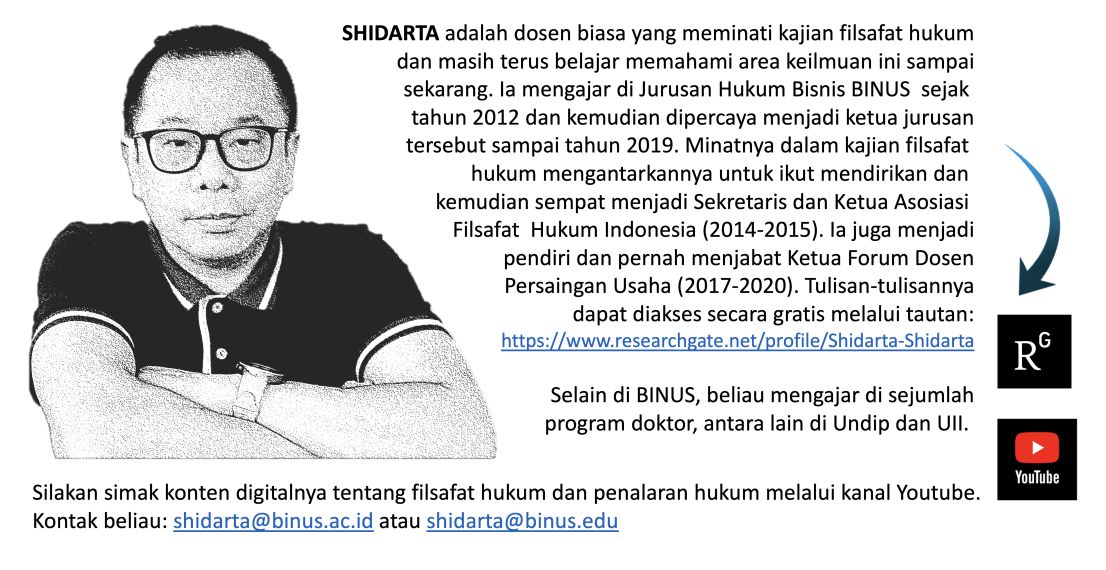
Comments :