MORALITAS BUDAK DI PANGGUNG DEMOKRASI
Oleh SHIDARTA (Desember 2023)
Moralitas budak adalah antonim dari moralitas tuan. Di mata filsuf besar yang mengakhiri era modern, yaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche, “moralitas budak” adalah moralitas orang kalah, yaitu manusia kerdil yang tidak mampu berpikir bebas untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. “Moralitas budak” hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap “neraka.” Ketakutan yang ironisnya, membuat mereka tidak berani menerima realitas dunia yang sebenarnya abu-abu. Alih-alih untuk realistis, mereka justru menawarkan cara berpikir sederhana, yakni cara melihat setiap persoalan sebagai hitam-putih; baik-buruk. “Moralitas budak” lalu mengklaim moralitas yang mereka anut sebagai ciri dari orang baik-baik, dan menganggap orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang jahat.
Nietzsche menduga bahwa banyak di antara kita pada akhirnya akan menyerah pada “moralitas budak” ini. Dan, sebagaimana kita ketahui, ia bahkan mengkritik agama Kristen (dan figur Kristus sebagai wujud keimanan) karena mempromosikan moralitas seperti itu. Padahal, ketika ajaran ini belum terinstitusionalisasi menjadi agama, menurut Nietzsche, ajaran ini (dan figur Yesus sebagai fakta historis) justru mengajak manusia untuk berpijak pada kehidupan duniawi yang nyata, dan bukan berada di alam transenden (Hinterwelt) tentang prioritas “hidup” sesudah mati. Atas dasar itulah Nietzsche waktu itu menolak Kristianitas dan kemudian menyatakan “Tuhan sudah mati!” Nietzsche memang seorang ateis, tetapi sangat mungkin bahwa dengan proklamasi itu, ia sesungguhnya hanya berniat untuk “menghidupkan” mentalitas sejati seorang manusia.
Tulisan ini tidak ingin mengulas lebih jauh tentang Nietzsche dengan segala kontroversi pemikirannya. Namun, cuplikan kecil pemikirannya di atas, yakni tentang kedangkalan “moralitas budak” menohok saya ketika mengikuti perjalanan hajatan demokrasi yang sedang melanda negeri ini, khususnya menyaksikan ujaran-ujaran yang dipakai para politisi atau model yang relatif seragam dalam poster-poster calon politisi yang beredar. Isu-isu yang diangkat di sana dan diklaim sebagai adu gagasan, ternyata memang sedemikian sederhananya, cenderung mengajak kita ke Hinterwelt. Jadi, barangkali ada baiknya kita meminjam terminologi “moralitas budak” versus “moralitas tuan” ini, lebih sebagai pengingat akan kebutuhan kita dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pucuk pemimpin pemerintahan kita saat ini.
Indikasi dari apa yang diungkapkan di atas terlihat dari bermunculan “gagasan” yang sekadar umbaran janji tanpa rasionalitas untuk mewujudkannya. Janji-janji menggratiskan berbagai hal, mulai dari sandang, pangan, papan, pajak kendaraan, adalah beberapa contoh di antaranya. Umbaran yang tidak pernah ditunjukkan perhitungan-perhitungannya secara rasional, sehingga tidak dapat dipastikan, misalnya, berapa banyak warga yang menikmati (termasuk area sebarannya), berapa lama fasilitas ini bakal diberikan secara berkelanjutan, berapa beban biaya yang harus ditanggung, dan dari mana sumber pembiayaannya. Demikian juga dengan biaya-biaya yang muncul sebagai eksternalitas negatif dari semua umbaran ini.
Uraian dan penjelasan demikian tentu tidak mungkin dipadatkan di dalam poster-poster wajah para calon yang bergantungan di hampir setiap sudut negeri. Tentu harus diciptakan panggung-panggung resmi (dalam arti disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang notabene sangat terbatas) dan juga panggung-panggung tidak resmi, antara lain dengan memanfaatkan forum-forum digital.
Kita sudah seharusnya meninggalkan gaya sosialisasi gagasan (baca: kampanye) yang tidak substansial. Apologia untuk mempertahankan model “berkampanye” demikian, tentu sudah dapat diduga, mudah diberikan. Misalnya, bakal dikatakan bahwa untuk berbicara dengan rakyat banyak, calon-calon itu memang tidak perlu berumit-rumit. Demokrasi itu konon menjadi terlalu luks apabila kita diajak berdiskursus sampai ke rasionalitas gagasan. Sebab, yang dikejar adalah suara, yakni satu kepala, satu suara. Isi kepala orang rasional dan tidak rasional sama nilainya! Tugas setiap kontestan adalah mendulang suara sebanyak-banyaknya. Untuk itu, cara paling sederhana adalah cukup dengan berteriak di atas panggung-panggung hiburan tentang janji-janji tadi. Bahkan, cukup memajang poster diri dengan sosok-sosok pesohor tertentu di belakang dirinya. Gaya snobis seperti ini diperagakan tanpa malu-malu. Lalu, muncul pula deklarasi-deklarasi dukungan yang dulu pernah sangat marak kita saksikan di era Orde Baru. Ironisnya, deklarasi-deklarasi seperti ini justru datang dari komunitas yang mengaku sebagai pusat-pusat pembelajar.
Di sisi lain, arena-arena debat gagasan yang seyogianya hadir untuk mendalami gagasan-gagasan tadi juga tidak kunjung muncul ke permukaan. Fenomena ini bahkan sampai di level debat capres-cawapres. Format debat yang didesain secara resmi, juga terkesan asal ada. Debat formalitas, bukan substansial!
Lalu apa yang salah dari sikap pragmatisme seperti itu? Apa yang salah dalam pilihan moralitas yang menyederhanakan persoalan dan tidak realistis seperti itu?Apabila entitas agama dan pendidikan pun sudah terkooptasi dengan sikap moralitas seperti disinyalir oleh Nietzsche (“moralitas budak”), lalu apakah kita kemudian harus berpasrah diri menghadapi kondisi seperti ini?
Tatkala para pendiri negeri kita merumuskan aspek epistemologi tentang bagaimana negara persatuan ini harus dibangun menuju ke visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, mereka dengan sangat cermat merumuskan satu fondasi yang kini kita kenal sebagai sila keempat Pancasila. Kata-kata dalam sila ini merepresentasikan misi berbangsa yang penting, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” (lihat uraian tentang hal ini dengan mengklik tautan berikut: https://business-law.binus.ac.id/2018/08/05/).
Misi ini memperlihatkan keseriusan yang selayaknya dilakukan untuk menghadirkan kontestan-kontestan berkualitas yang akan duduk sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Mereka inilah yang akan duduk di lembaga-lembaga negara terhormat kita. Mereka pula yang akan bertanggung jawab memutuskan apa yang terbaik bagi rakyat dalam perjalanan beberapa tahun ke depan. Mereka adalah primus inter pares. Namun, sebelum mereka mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka pertama-tama harus “berani” menunjukkan sebagai wakil rakyat yang sudah mencerdaskan kehidupan diri mereka sendiri.
Untuk itu, banyaknya gelar akademik, budaya, dan reliji, bukan ukuran bagi kontestan yang diharapkan. Masyarakat perlu pembuktian lebih daripada itu. Masyarakat–paling tidak para penghuni kelas menengah di negeri ini–perlu difasilitasi dengan ketersediaan forum-forum yang secara bernas mampu mengungkapkan gagasan-gagasan brilyan dari calon wakil-wakil mereka. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak mengherankan apabila rakyat terperdaya memilih “kucing dalam karung.” Rakyat memilih orang-orang yang tidak benar-benar mereka kenal reputasi dan pemikirannya. Alhasil, hembusan angin “kematian demokrasi” bakal makin menguat, ditambah lagi dengan distorsi teknologi informasi dan komunikasi yang lepas kontrol. Rakyat mungkin saja masih antusias untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara, tetapi sesungguhnya mereka tidak benar-benar yakin lahir-batin, kepada siapa suara mereka itu akan dititipkan. “Moralitas budak,” juga akan benar-benar dipertontonkan apabila benar terjadi tekanan-tekanan dalam hajatan demokrasi itu, misalnya dengan pengerahan aparatur negara dalam ikut memobilisasi massa pendukung konstestan tertentu,
Kita memang menyadari bahwa di arena politik selalu ada panggung depan dan panggung belakang. Artinya, kita cukup mafhum tentang sisi kosmetika yang menghiasi panggung depan yang lazim menggunakan tipe moralitas yang dikritik Nietzsche. Namun, moralitas seperti itu tidak boleh dibiarkan sampai mendominasi panggung belakang. Artinya, panggung belakang jangan sampai sama mengecohnya dengan panggung depan. Sebagian [besar] masyarakat merindukan dan membutuhkan panggung demokrasi yang sungguh-sungguh menunjukkan adanya pertukaran ide yang benar-benar bernas, didukung oleh data dan perhitungan yang memadai. Mereka harus berani masuk ke jantung-jantung konstituten mereka dan membiarkan masyarakat menangkap ide-ide mereka dengan nalar yang jernih. Demokrasi, dengan demikian, adalah hajatan pendidikan politik. Hilangnya anggaran negara sebesar Rp 71,3 trilyun tanpa peningkatan literasi politik yang berarti, sungguh-sungguh sebuah ritual yang sangat mahal.
Walaupun tulisan ini dimulai dengan meminjam terminologi dari pemikiran Nietzsche, tidak berarti kita ingin mengkopi seratus persen tabiat “moralitas tuan” di panggung demokrasi kita itu. Ada konteks demokrasi keindonesiaan yang ingin kita diskursuskan dengan meminjam istilah “moralitas tuan” versus “moralitas budak” itu. Hal yang ingin dipinjam dari “moralitas tuan” adalah keberanian para calon wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen atau di pucuk pemerintahan, untuk menyuarakan gagasan yang diyakininya sendiri sebagai kebenaran dan kebaikan. Bukan gagasan yang sekadar mengekor atau tunduk (tegak lurus) di bawah bayang-bayang partai atau sosok tertentu. Bukan gagasan yang membawa kita ke dunia awang-awang (Hinterwelt). Jika para calon itu sekadar mengekor, maka rakyat para pemilih, sama sekali tidak punya alasan pembeda apapun untuk memilih si A atau si B. “Moralitas tuan” yang dimaksud Nietzsche pun tidak boleh disalahpahami seakan sekadar menjadi manusia ambisius, tetapi hanya berupa ambisi meraih status sosial sebagai warga elit di parlemen atau pemerintahan. Ambisi seperti itu justru menunjukkan moralitas yang belum berevolusi ke tingkat lebih tinggi.
Dalam konteks berdemokrasi, “moralitas tuan” sewajarnya melekat pada “tuan-tuan” dengan standar moral yang berkelas. Mereka yang yakin bahwa setiap janji yang diucapkan, walaupun sebatas umbaran yang menempel di poster-poster pinggiran jalan, tetaplah membutuhkan pertanggungjawaban moral sekaligus rasional. Janji adalah hutang, dan setiap hutang membutuhkan pertanggungjawaban, paling tidak tanggung jawab untuk mampu memahami detail janjinya sendiri dan kemudian mampu menjelaskannya kepada warga yang telah membaca janji itu. Atau, jika dipersempit lagi, setidaknya ditujukan kepada penghuni kelas menengah negeri ini yang diasumsikan punya minat dan waktu untuk mendengarkan. “Moralitas budak” sebaliknya, adalah moralitas yang hanya berani melempar batu tetapi bersembunyi tangan; berani mengumbar gagasan tapi gagal paham tentang apa yang dikatakan.
Konkretnya, hajatan demokrasi adalah sebuah panggung pendidikan politik. Partai-partai politik adalah institusi pendidikan politik yang harus membekali secara memadai semua calon pemimpin yang direkrutnya dengan semua kemampuan yang telah dinyatakan di atas. Masyarakat, khususnya kelompok yang peduli pada kualitas demokrasi kita, perlu menuntut hal ini. Demokrasi berbiaya sangat mahal ini sangat disayangkan apabila diyakni sebagai rutinitas formal-prosedural belaka. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal dapat membuka diri untuk menyediakan forum-forum diskusi gagasan, tetapi harus mulai menjauhkan diri dari perangkap kooptasi sempit yang berujung pada deklarasi dukung-mendukung.
Demikianlah, pilihan demokrasi telah ditetapkan sebagai basis epistemologi berbangsa dan bernegara bagi negeri ini. Para pendiri negeri kita telah memasang rambu-rambu untuk mencegah kecenderungan hadirnya wakil-wakil rakyat dan pucuk pemimpin kita di pemerintahan dengan kualitas mediocre, sebagaimana terbaca dari kata-kata “hikmat kebijaksanaan” dalam misi bernegara kita. Untuk itu, kita perlu me-tuan-kan demokrasi kita, bukan mem-budak-kannya. (***)

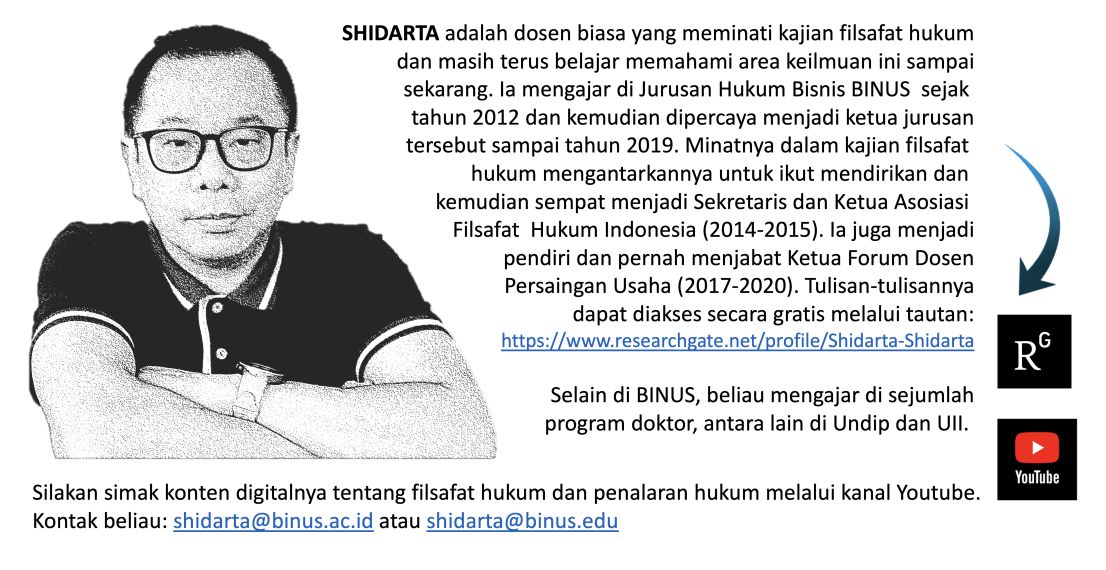
Comments :