PASAL 50 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
Oleh SHIDARTA (April 2023)
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut: UU Persaingan Usaha) memuat tentang pengecualian pemberlakuan atas undang-undang ini. Pasal 50 UU Persaingan ini menggunakan judul Bab IX KETENTUAN LAIN. Secara material, pasal ini memang memuat pengecualian (teridentifikasi dari kata “dikecualikan”), yang dalam bahasa Inggris sering disebut “exceptions” atau “exclusion”. Ada juga terminologi lain yang kerap dipakai, yaitu exemptions, yang dapat diartikan sebagai pembebasan (lihat terjemahan istilah ini di dalam lampiran Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009; tinjauan terhadap Peraturan KPPU ini akan dimuat pada bagian akhir tulisan ini).
R. Shyam Khemani (2002) dalam dokumen UNCTAD/DITC/CLP/Misc.25 merujuk sejumlah referensi untuk kemudian memberikan pembedaan atas istilah-istilah di atas. Ia menulis sebagai berikut:
A distinction is made in the use of the terms “exemption” and “exception” as they are generally applicable in the context of competition law policy. The term exemption refers to being “excused or free from some obligation to which others are subject”. An exception is to be “excluded from or not conforming to a general class, principle, rule, etc.” However, it may be noted that while the terms “exemption” and “exception” (also “exclusion”) have specific meanings within the context of particular national legal systems, they are often used interchangeably.
Sekalipun diakui bahwa semua istilah itu dalam praktiknya dapat digunakan secara bergantian (interchangeably), sekilas dapat dipahami bahwa terdapat dua sebab utama suatu pelaku usaha untuk dikecualikan dari kewajiban menjalankan UU Persaingan Usaha. Pertama, faktor subjek normanya. Kedua, faktor kondisi normanya. Yang pertama inilah yang kerap disebut exemption, sedangkan yang kedua adalah exception atau exclusion.
Sebagai contoh, sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu berdasarkan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1992, dikatakan bahwa perkeretaapian diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya diserahkan kepada badan penyelenggara yang dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan penyelenggara yang dimaksud, dapat diduga, tidak lain adalah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Pelaku usaha ini adalah penyelenggara satu-satunya yang diberi hak mengelola jasa perkeretaapian di Indonesia. Dilihat dari ketentuan normatif, PT KAI adalah subjek norma yang diberi keistimewaan oleh undang-undang untuk memonopoli (statutory monopoly) layanan jasa perkeretaapian pada pasar bersangkutan di seluruh Indonesia. Namun, setelah UU No. 23 Tahun 2007 berlaku, investor di luar PT KAI dapat juga berbisnis di sektor jasa ini untuk ikut menjadi pengelola.
Jasa perkeretaapian membutuhkan investasi yang sangat besar. Hal ini menciptakan kondisi yang secara alamiah tidak memungkinkan apabila monopoli tidak diberikan untuk suatu pasar bersangkutan di sektor usaha tersebut. Kondisi ini mengharuskan satu pasar bersangkutan (yaitu jalur-jalur layanan tertentu) hanya dikelola oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Hanya dengan kondisi demikian, pelaku usaha mendapat jaminan untuk tetap untung dalam bisnis ini. Monopoli demikian biasanya dikenal sebagai monopoli alami (natural monopoly). Seharusnya, untuk pelaku usaha yang berbisnis dalam kondisi monopoli alami juga perlu dikukuhkan eksistensinya dengan peraturan perundang-undangan, atau setidaknya dengan peraturan kebijakan.
Sesuai dengan judul, tulisan berikut ini akan memfokuskan pada uraian tentang Pasal 50 huruf a, yang lengkapnya tertulis sebagai berikut:
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau …
Pasal 50 huruf a UU Persaingan Usaha berbicara tentang monopoli karena undang-undang. Siapa pelaku usaha yang layak mendapatkan monopoli karena undang-undang? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit banyak membawa kita kepada rumusan Pasal 51 UU Persaingan Usaha. Pasal 51 UU Persaingan Usaha menyatakan:
Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.
Dengan membaca ketentuan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU Persaingan Usaha, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
- UU Persaingan Usaha tidak berlaku bagi pelaku usaha, yakni berupa badan usaha milik negara; atau badan; atau lembaga, yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah;
- pelaku usaha tersebut melakukan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ia memperoleh pengecualian untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan menurut UU Persaingan Usaha;
- area perbuatan dan atau perjanjian itu harus berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara;
- area usaha yang dimaksud sebagai “menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” itu harus sudah ada pengaturannya di dalam undang-undang.
Poin nomor tiga di atas, diperluas dalam ayat-ayat berikutnya dari Pasal 50 UU Persaingan Usaha, sehingga menjangkau juga area perbuatan dan atau perjanjian di lapangan hak kekayaan intelektual (seperti perjanjian lisensi paten/merek/desain, waralaba), penetapan standar teknis produk, keagenan, kerja sama penelitian (R&D), perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian/perbuatan untuk mengekspor produk, pelaku usaha kecil dan koperasi yang bertujuan melayani anggotanya. Cara perumusan yang secara otomatis memberikan pengecualian seperti ini lazim disebut block exemption.
Dengan demikian, pengecualian dalam Pasal 50 UU Persaingan Usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. Kiteria pertama berlaku bagi pelaku usaha yang mendapat hak monopoli karena undang-undang (statutory monopoly). Kriteria kedua berlaku bagi pemegang hak monopoli privat (private monopoly). Kriteria ketiga adalah pelaku usaha yang justru tidak dalam posisi memonopoli, antara lain karena berada di pasar bersangkutan yang ternyata berbeda, atau penguasaan pangsa pasarnya jauh dari posisi dominan.
Ketentuan Pasal 50 huruf a jelas mengarah ke pengecualian kriteria yang pertama. Oleh karena dasarnya adalah adanya undang-undang, maka kita menemukan setidaknya harus ada dua undang-undang yang saling berhadapan. Pertama, tentu UU Persaingan Usaha yang menjadi basis di sisi persaingan usahanya. Kedua, UU yang dipersepsikan sebagai peraturan yang memuat pengecualian.
Asas lex specialis derogat legi generali
Mengingat UU No. 5 Tahun 1999 adalah undang-undang dalam arti formal, maka jika ada undang-undang lain yang memuat pengecualian, harus juga dalam hieraki yang minimal sama tingkatannya. Artinya, undang-undang yang mengecualikan wajib juga paling rendah adalah undang-undang dalam arti formal. Rumusan Pasal 50 huruf a yang menyebut kata-kata “peraturan perundang-undangan” menimbulkan problematika tersendiri karena secara hierarkis ada banyak peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang.
Asas lex speicalis derogat legi generali seharusnya dibaca sebagai asas yang mengatasi pertentangan substansial dari dua undang-undang. Dalam hal ini tidak boleh ada isu terkait hierarki. Apabila peraturan yang ingin menyimpang dari UU Persaingan Usaha (memuat pengecualian) itu tingkatannya ternyata bukan undang-undang (dalam arti formal), melainkan peraturan pemerintah atau lebih rendah lagi, maka akan tampil asas lex superior derogat legi inferiori.
Apabila ada satu pelaku usaha yang berdalih bahwa ia tidak tunduk pada UU Persaingan Usaha, maka ia tidak boleh hanya menunjuk dasarnya suatu peraturan kebijakan (beleidsregel) atau keputusan administratif (beschikkings). Jelas-jelas yang disebutkan oleh Pasal 50 huruf a adalah peraturan perundang-undangan (regerlng), bukan peraturan kebijakan atau keputusan administratif. Atas dasar pemikiran demikian, seharusnya pelaku usaha yang memenuhi pengecualian Pasal 50 huruf a tidak akan banyak jumlahnya. Bahkan, pelaku usaha seperti PT KAI pun tidak lagi dapat terbebas dari ketentuan ini karena UU No. 23 Tahun 2007 tidak lagi memberi landasan bagi PT KAI untuk melakukan monopoli.
Potensi untuk menjadikan perturan kebijakan atau keputusan administratif, dan bukan undang-undang, sebagai dasar mengecualikan diri dari UU Persaingan Usaha, sangatlah mungkin terjadi. Hal ini, misalnya, dapat dicermati dari berbagai bentuk penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pelaku usaha tertentu. Salah satunya dapat dicermati dari Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2O03 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang dikukuhkan dengan UU No. 6 Tahun 2023). Pasal 66 UU BUMN itu berbunyi:
Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.
Pertimbangan untuk memberikan izin demikian kepada BUMN ternyata sangat sederhana, yaitu cukup dengan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan menteri terkait. Layak dipertanyakan, bagaimana dengan KPPU, apakah komisi independen ini dilewatkan begitu saja? Ternyata memang demikian yang terjadi.
Rumusan pasal yang memberi preferensi kepada pelaku usaha tertentu akan sangat mungkin juga terjadi melalui kata-kata “memberdayakan” (lihat contohnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023). Bahkan, pemberi izin pun tidak lagi harus Pemerintah Pusat.
Asas lex consumens derogat legi consumptae
Perdebatan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia akan bertambah kompleks apabila dua undang-undang mengklaim sebagai lex specialis. Klaim-klaim demikian dapat saja terjadi karena pengkategorian mana undang-undang yang lebih khusus daripada undang-undang yang lebih umum, sangat bergantung pada pandangan subjektif si penafsir. Terkadang tiap kasus menggunakan perspektif berbeda. Idealnya, memang setiap undang-undang yang dibuat sebagai lex specialis, harus menyatakan hal itu di dalam teks undang-undang tersebut, atau paling tidak mencantumkannya dalam ketentuan mengingat sebagai landasan yuridisnya. Namun, lagi-lagi aturan main seperti ini tidak sepenuhnya ditaati.
Mari kita ambil contoh antara UU Perdagangan dan UU Persaingan Usaha serta UU BUMN. Mana di antara tiga undang-undang ini yang lebih luas cakupan materi pengaturannya? Apabila kita berpendapat bahwa cakupan keluasan tidak relevan dipersoalkan terhadap ketiga undang-undang ini, maka tentu kita harus menghindar dari pengidentifikasian mengenai mana yang lex specialis dan mana yang lex generalis. Seandainya ada konflik norma di antara ketiganya, maka cukuplah digunakan asas lex posterior derogat legi priori. Namun, penggunaan asas lex posterior derogat legi priori ini sangat menyederhanakan persoalan.
Untuk itu, harus ada asas yang lebih fundamental sebagai landasan berpikir kita. Asas tersebut dicari melalui cara bernalar hukum yang disebut argumentum a fortiori (argument from the stronger reason). Pada akhirnya cara benalar ini akan mengantarkan kita pada penggunaan asas lex consumens derogat legi consumptae. Dalam hal terdapat klaim antara dua atau lebih undang-undang untuk diberikan preferensi berlaku, maka yang harus diberi prioritas adalah undang-undang yang lebih kuat alasan keberlakuannya. Alasan itu dapat dilihat dari akibat (keburukan) yang lebih serius yang ingin dicegah atau diatasi oleh suatu undang-undang.
UU Persaingan Usaha dibentuk dengan landasan filosofis “demokrasi ekonomi” yang ada di dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi mengamanatkan agar kita semua memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
UU BUMN menyatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah menjadi perintis kegiatan–kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Jadi, kita dapat memastikan di sini bahwa BUMN harus tunduk pada UU Persaingan Usaha. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bahwa UU BUMN menjadi lex specialis daripada UU Persaingan Usaha.
UU Perdagangan di sisi lain menyatakan bahwa ia lahir karena pembangunan di bidang ekonomi memang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dalam rangka itu, persaingan usaha yang sehat harus dijadikan ciri dalam berusaha. Kata-kata “persaingan usaha” secara eksplisit disebutkan dalam UU Perdagangan ini. Demikian juga dengan BUMN juga disebutkan, antara lain dalam Pasal 27, dengan kata-kata:
Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.
Dengan menggunakan penalaran argumentum a fortiori, kita dapat menemukan bahwa UU Persaingan Usaha memiliki justifikasi yang lebih kuat untuk menyimpangi dua undang-undang lainnya (dalam hal ada konflik normatif). Oleh sebab itu, Pasal 50 huruf a UU Persaingan Usaha harus dibaca secara sangat spesifik, yaitu “sepanjang tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” Pelaku usaha, termasuk BUMN atau badan atau lembaga tertentu, dimungkinkan untuk diberikan hak monopoli melalui undang-undang, tetapi ia tetap tidak boleh melakukan praktik monopoli, yang pada gilirannya akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Pemberian tempat yang lebih prioritas kepada UU Persaingan Usaha karena ia punya alasan lebih kuat (a stronger reason) dapat juga dilacak pada berbagai undang-undang lain. Dalam UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dapat ditemukan dalil-dalilnya dari redaksi sejumlah pasal, seperti Pasal 57 ayat (4) huruf b UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: … daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat“); atau juga dalam Pasal 29 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha); atau di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: …menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi”); serta contoh lain lagi dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/ atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat“). Dengan contoh-contoh di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa iklim persaingan usaha yang sehat itu adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dikorbankan dengan alasan apapun. Pasal 50 huruf a UU Persaingan Usaha yang memuat pengecualian, tidak boleh sampai mengorbankan keniscayaan ini karena pada hakikatnya undang-undang yang memberikan hak monopoli itu tidak boleh sampai menyentuh kondisi yang dihindari oleh filosofi demokrasi ekonomi menurut konstitusi negara, yaitu jika sampai memasuki kondisi praktik monopoli.
Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2009
Sejak tanggal 7 Desember 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesungguhnya sudah memiliki pemahaman tersendiri tentang bagaimana harus membaca Pasal 50 huruf a. Jika diringkas, sikap dari KPPU berkaitan dengan unsur-unsur Pasal 50 huruf a itu adalah sebagai berikut:
|
No. |
Unsur |
Keterangan |
| 1 | perbuatan |
|
| 2 | perjanjian |
|
| 3 | bertujuan melaksanakan |
|
| 4 | peraturan perundang-undangan yang berlaku |
|
UU No. 10 Tahun 2004 saat ini sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022. Dalam peraturan yang baru, nomenklatur “keputusan” sudah tidak lagi digunakan untuk menyebutkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan. KPPU harus juga tidak membuka diri terhadap penafsiran yang terlalu luas atas jenis-jenis peraturan perundang-undangan ini, apalagi jika pendelegasian itu menyalahi teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena pendelegasian itu wajib bersumber dari undang-undang (dalam arti formal), maka dengan sendirinya keruntutannya akan dipertanyakan apabila ada pelaku usaha yang mengklaim mendapatkan pendelegasian itu dari jenis-jenis peraturan yang lebih rendah. Misalnya, di daerah-daerah terdapat BUMD yang ingin menggunakan pengecualian menurut Pasal 50 juncto Pasal 51 huruf a UU Persaingan Usaha dengan menggunakan dasar peraturan daerah. BUMD bukanlah BUMN, sehingga Pasal 51 jelas tidak dapat diterapkan untuk konteks BUMD.
Perlu dicatat bahwa BUMD di daerah-daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, wajib mengambil alternatif di antara dua bentuk, yaitu perum[da] dan persero[da]. Bentuk perseroda biasanya lebih disukai karena lebih fleksibel dan dapat menampung aneka jenis usaha. Dalam pembentukan BUMD itu, aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, memang menjadi persyaratan pendirian, sehingga terkesan mendekati filosofi Pasal 33 UUD. Namun lagi-lagi, indikator dari terpenuhi pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat tersebut terbukti sangat longgar dan multitafsir. KPPU, dengan demikian, harus membuat patokan yang tegas untuk tidak membuka pintu terlalu lebar bagi klaim-klaim pengecualian dari pelaku usaha yang mendapatkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terlebih-lebih peraturan di tingkat daerah.
Dapat terjadi misalnya, suatu daerah menolak kehadiran pelaku usaha besar untuk bergerak dalam lini bisnis tertentu. Dalih yang kerap diajukan adalah agar kehadiran pelaku usaha besar itu tidak sampai mematikan pelaku usaha kecil yang asli berasal dari daerah setempat. Sepanjang motif dari peraturan itu memang ingin menghasilkan titik keseimbangan dalam lingkup demokrasi ekonomi di daerah tersebut, dan ada peta kebijakan yang jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang (sampai kapan kebijakan seperti itu akan dipertahankan), maka sekilas aksi afirmatif seperti itu layak untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun KPPU juga memiliki peran untuk menggalakkan program kemitraan. Namun, motif seperti ini harus juga diwaspadai agar tidak digunakan untuk menghadirkan kebijakan yang diskriminati di lapangan, yang pada gilirannya hanya dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha tertentu saja. Untuk itu, pengecualian harus diatur tersendiri oleh KPPU dengan menggunakan model single exemption. Pengecualian tersebut dapat diberikan atau tidak diberikan berbasis penilaian secara kasus per kasus. Pengecualian tak dapat diberikan apabila secara substansial aktivitas pelaku usaha itu diyakini dapat mencederai persaingan usaha yang sehat dan tidak memberi kemanfaatan yang nyata bagi publik (konsumen).
Satu hal yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa Pasal 50 UU Persaingan Usaha pada hakikatnya diformulasikan tidak sebagai norma primer. Formatnya adalah norma sekunder. Agar jelas pemaknaannya, norma sekunder seperti ini harus dicarikan kaitannya dengan norma primernya. Pertanyaan penting dalam perumusan norma primer adalah tentang subjek normanya: kepada siapa Pasal 50 huruf a ini akan ditujukan? Jawaban pertama, subjek normanya adalah pelaku usaha. Dengan demikian rumusan norma primernya dapat kita bayangkan kurang lebih sebagai berikut:
Setiap pelaku usaha dapat melakukan perbuatan dan atau perjanjian dengan pihak lain dengan mengenyampingkan keberlakuan undang-undang ini sepanjang perbuatan dan atau perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pendelegasian undang-undang.
Kata “dapat” dari rumusan di atas jika diposisikan sebagai operator norma, bermakna sebagai “diizinkan”. Izin adalah kebolehan untuk melakukan perilaku yang secara umum dilarang.
Jawaban kedua, subjek normanya adalah KPPU. Rumusannya akan menjadi kurang lebih sebagai berikut:
KPPU tidak dapat menerapkan ketentuan undang-undang ini terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan dan atau perjanjian dengan pihak lain apabila perbuatan dan atau perjanjian itu bertujuan untuk melaksanakan pendelegasian undang-undang.
Hal yang paling krusial dilakukan adalah memahami apa kriteria dari undang-undang yang memberikan pendelegasian itu. Isu yang muncul di sini lebih menjurus kepada tugas dan wewenang KPPU, yakni yang digarisbawahi oleh Pasal 35 dan 36 UU Persaingan Usaha. KPPU diamanatkan oleh UU Persaingan Usaha untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap semua perjanjian, kegiatan usaha/tindakan pelaku usaha, dan potensi penyalahgunaan posisi dominan, lalu mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Juga menjadi tugas KPPU untuk memberi saran dan pertimbangan, menyusun pedoman/publikasi, dan memberi laporan berkala ke Presiden dan DPR.
Dalam rangka mempertegas frasa “melaksanakan pendelegasian undang-undang” maka perlu ditambahkan rumusan:
Dalam melaksanakan pendelegasian undang-undang tersebut, pelaku usaha tidak boleh melakukan perbuatan dan atau perjanjian dengan pihak lain yang menyebabkan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Artinya, terkait suatu undang-undang yang jelas-jelas mengarah ke praktik monopoli dan menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat, KPPU tidak selayaknya mendiamkan kondisi seperti ini. Jika ini dilakukan, berarti KPPU tidak menjalankan amanat konstitusi untuk menegakkan demokrasi ekonomi. Semua produk hukum di bawah konstitusi yang melanggar landasan yang diamanatkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, harus menjadi perhatian dan layak dianggap “inkonstitusional” di mata KPPU, terlepas kemudian diperlukan proses formal untuk mengajukan pengujiannya ke lembaga yudikatif terkait. Dan, khusus untuk pelaku usaha yang berstatus BUMN, rumusannya harus juga dibaca satu napas dengan Pasal 51 UU Persaingan Usaha. Cara pembacaan demikian dalam banyak sisi, sebenarnya sudah menjadi sikap KPPU yang sudah terakomodasi dengan baik dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2009.
Penutup
KPPU perlu lebih mengaktifkan perannya dalam pengawasan terhadap produk-produk hukum seperti ini. Dengan perkataan lain, jangan hanya area hilirnya yang diurusi (terkait kasus-kasus konkret dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha), melainkan juga harus menyentuh area hulunya, sehingga “mata pedang” KPPU bakal lebih tajam karena argumentasinya dibangun secara fundamental.
Sayangnya, perhatian terhadap topik-topik persaingan usaha di wilayah hulu ini, sangat jarang menarik perhatian. Padahal, inti persoalan kerap bersumber di sini. Misalnya, makna dari “kemanfaatan umum” yang diperkenalkan dalam Pasal 66 UU BUMN, apakah sama dan sebangun dengan “hajat hidup orang banyak”? Jika ya, di mana garis demarkasi untuk mengatakan area itu wajib diselenggarakan hanya oleh BUMN dan tidak boleh diserahkan ke pelaku usaha lain? Jika boleh diserahkan ke pelaku usaha lain, seperti apa batas-batas peran yang bisa diserahkan? Diskursus yang bernas seperti ini akan memudahkan KPPU bekerja dalam menjalankan visi dan misinya sebagai lembaga independen yang “konon” menurut Pasal 30 ayat (2) UU Persaingan Usaha, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. (***)



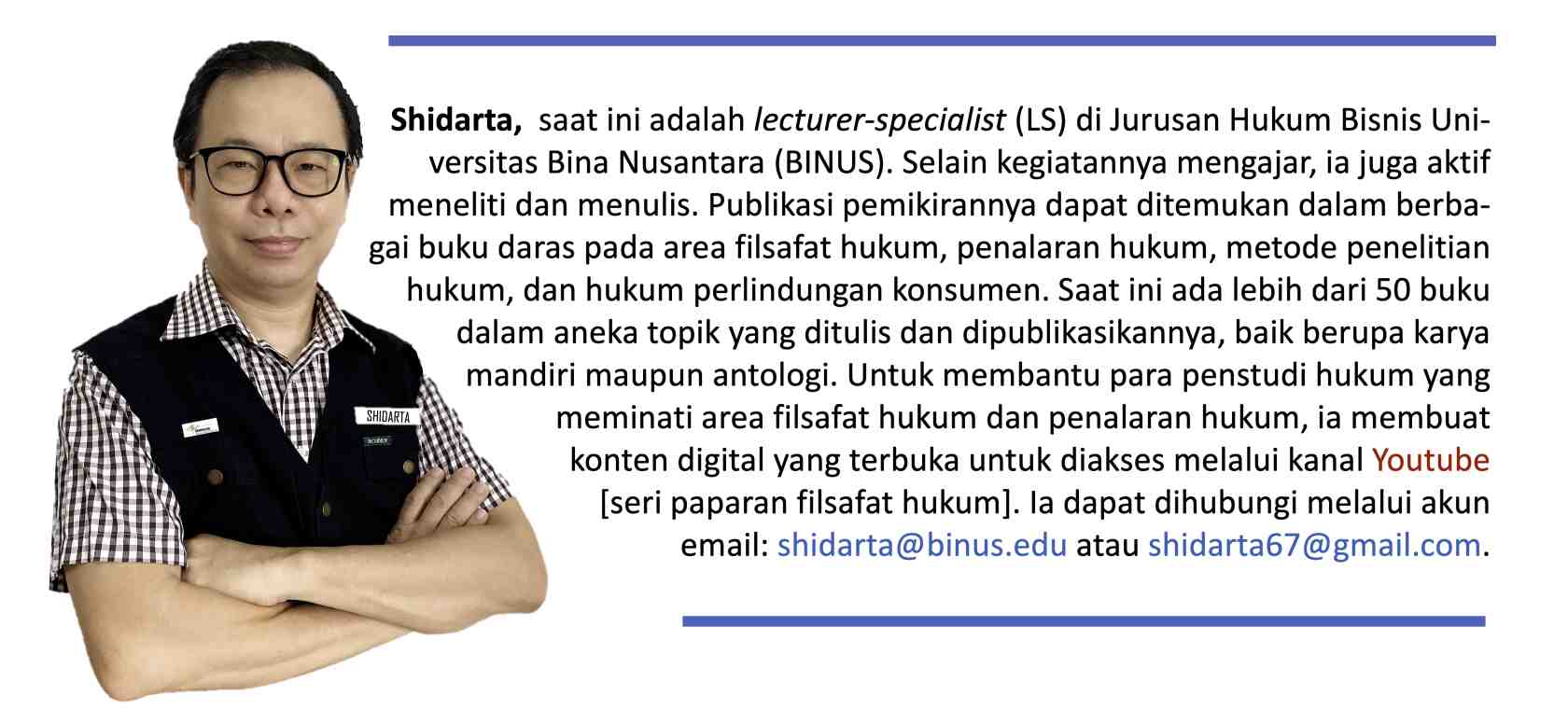
Comments :