BPSK SEBAGAI BADAN ALTERNATIF PENYELESIAN SENGKETA
Oleh: SHIDARTA (September 2020)
Setelah 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diberlakukan, eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tetap belum dirasakan greget-nya. Lembaga ini memang diposisikan sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa (di luar pengadilan).
Kehadiran suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dalam rangka mengatasi keberlikuan proses peradilan. Pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.” Ini berarti, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.[1]
Dalam desain awal UUPK, keberadaan BPSK ini diamanatkan ada di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya (daerah tingkat dua). Ternyata dalam praktik hal ini tidak berjalan sesuai desain awal itu. Tidak semua kabupaten dan kota (dulu kotamadya) memiliki BPSK. Wilayah kerja satu BPSK, dengan demikian, dapat saja mencakup lebih dari satu kabupaten dan/atau kota. Setelah muncul pengaturan baru tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah [pusat], pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tampaknya desain awal dari UUPK tentang wilayah kerja BPSK ini perlu disesuaikan.
Personalia BPSK, menurut ketentuan UUPK, ditetatapkan oleh Menteri Perdagangan. Dalam Pasal 49 UUPK, syarat-syarat menjadi anggota BPSK adalah: (1) waraga negara Republk Indonesia, (2) berbadan sehat, (3) berkelakuan baik, (4) tidak pernah dihukum karena kejahatan, (5) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan (6) berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun. Keanggotaan BPSK terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha, sehingga jumlahnya antara sembilan sampai dengan lima belas orang.
Setiap kasus sengketa konsumen diselesaikan dengan membentuk majelis yang berjumlah ganjil, terdiri dari minimal tiga orang yang mewakili semua unsur. Mereka yang dipilih sebagai majelis kemudian menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen ini melalui jalur yang dipilih, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hal penjatuhan sanksi, hanya jalur arbitrase yang boleh melakukannya. Jalur arbitrase dilakukan mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sebagian dari hukum acara di dalam BPSK ternyata sudah diatur dalam Kepmenperindag Nomor 350/2001, sehingga menjadi pertanyaan juga apakah UU Nomor 30 Tahun 1999 juga sepenuhnya dapat berlaku. Dengan perkataan lain, seberapa mungkin UUPK dan peraturan pelaksanaannya (Kepmenperindag Nomor 350/2001) itu dapat mengenyampingkan UU Nomor 30 Tahun 1999. Di sini ada dua pendapat. Pandangan pertama mengatakan bahwa sebuah lembaga arbitrase yang permanen, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak lagi tunduk pada UU Nomor 30 Tahun 1999. Artinya BPSK, juga termasuk sebagai lembaga yang permanen. Pandangan kedua menyatakan bahwa UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah lex arbitri, yang artinya ia menaungi semua ketentuan hukum tentang arbitrase di seluruh wilayah Indonesia.[2]
Dalam konteks penjatuhan sanksi administratif, jelas bahwa lembaga arbitrase adhoc tidak memiliki wewenang ini. UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberi pelimpahan maupun pendelegasian wewenang penjatuhan sanksi administratif ini kepada lembaga-lembaga arbitrase adhoc itu. Pelimpahan atau pendelegasian itu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga arbitrase tersebut. Artinya, BPSK sebagai badan yang dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, berwenang menyelenggaraan mekanisme arbitrase yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Di sini tidak berlaku asas lex arbitri, melainkan asas lex specialis derogat legi generali.
Oleh karena UUPK dapat dipandang sebagai lex specialis untuk ketentuan hukum acaranya, maka sangat menarik apabila BPSK sendiri dapat mengoptimalkan kemampuannya ini. Dalam UUPK memang ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang lebih difungsikan sebagai badan riset dan pemberi rekomendasi bagi pemerintah. Artinya, BPKN sangat mungkin bukan pilihan yang tepat untuk dimintakan bantuannya dalam mengoptimalkan peran ini. Optimalisasi ini seharusnya dilakukan oleh BPSK-BPSK itu sendiri, antara lain dengan cara membentuk jaringan kerja sama di antara mereka. Sementara ini Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan dapat memfasilitasi munculnya jaringan ini.
Tujuan dari koordinasi tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari BPSK. Mereka dapat saling belajar dengan berbagi pengalaman menghadapi kasus-kasus sengketa konsumen. Bukan rahasia umum bahwa anggaran dari masing-masing BPSK ini sangat kecil, yang mengandalkan sepenuhnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah masing-masing. Apabila BPSK-BPSK ini dapat berkoordinasi, maka kendala anggaran sangat mungkin bakal teratasi dan frekuensi “saling belajar” di antara mereka dapat makin ditingkatkan. Termasuk dalam hal ini tentu saja, jejaring kerja sama ini dapat diperluas dengan melibatkan perguruan-perguruan tinggi di berbagai tempat.
Dengan modal kedekatan kasus-kasus konsumen ini pada masyarakat luas, maka isu-isu yang ditangani BPSK pasti menarik perhatian. Putusan-putusan BPSK yang argumentatif dan mencerahkan dipastikan akan mengisi ruang-ruang diskusi di kelas-kelas pembelajaran hukum perlindungan konsumen. Pada gilirannya kemudian, BPSK akan makin dikenal luas dan dicintai oleh masyarakat konsumen. (***)
CATATAN: Tulisan di atas dicuplik dari tulisan penulis (term of reference) untuk memandu penelitian “payung” bagi sejumlah mahasiswa yang dibimbing penulis mengenai fungsi dan kewenangan BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
REFERENSI:
[1] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 175.
[2] Lihat perdebatan ini dalam artikel yang diumuat oleh hukumonline: “Hikmahanto: UU Arbitrase Tak Berlaku bagi BANI,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5476df516e404/hikmahanto–uu-arbitrase-tak-berlaku-bagi-bani>, akses tanggal 1 November 2016.



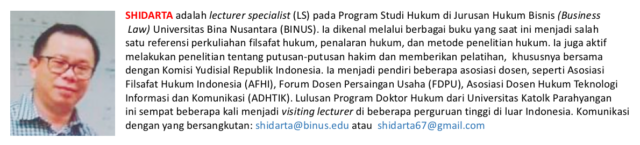
Comments :