“FORCE MAJEURE” DAN “CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS”
Oleh SHIDARTA (April 2020)
Dalam situasi krisis covid-19 yang tengah melanda dunia seaat ini, kalangan hukum ramai membicarakan tentang dapat tidaknya alasan pandemi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengubah atau membatalkan perjanjian, yang lazim di Indonesia dasar hukum ini diberi label sebagai force majeure. Dalam bahasa Indonesia, istilah force majeure ini cukup banyak diterjemahkan dengan istilah “keadaan kahar” namun dalam tulisan ini, terminologi aslinya sengaja dipertahankan karena rupanya masih lebih luas dikenal oleh komunitas hukum. Tulisan ini akan berbicara tentang ketentuan force majeure dan kaitannya dengan satu doktrin yang mirip, yakni clausula rebus sic stantibus. Tulisan ini akan memberi paparan tentang asas dan doktrin tersebut. Jadi, tidak sampai kepada analisis untuk menjawab apakah pandemi covid-19 merupakan dalih untuk dapat mengajukan alasan force majeure (atau jika ada, dengan clausula rebus sic stantibus).
Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini merupakan pembatasan terhadap keberlakuan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata, menurut terjemahan dari Prof. Subekti, berbunyi sebagai berikut:
Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungawabkan padanya, kesemua itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.
Aslinya, pasal ini di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:
De schuldenaar moet, indien daartoe gronden bestaan, veroordeeld worden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, zoo dikwijls hij niet bewijzen kan dat het niet uitvoeren of het niet tijdig uitvoeren der verbintenis voortkomt uit eene vreemde oorzaak, die van zijne zijde plaats gehad.
Jika kita strukturkan pasal tersebut ke dalam unsur-unsur norma, maka kita akan lebih mudah memahami maksud dari ketentuan norma tersebut. Agar struktur normanya lebih jelas dipahami, maka digunakan diksi yang sedikit berbeda, dengan catatan tidak sampai mengubah makna. Hasil penstrukturannya adalah sebagai berikut:
| Subjek norma | Debitur (si berutang; obligor) |
| Operator norma | diperintahkan (harus/wajib) |
| Objek norma | mengganti biaya, kerugian, dan bunga |
| Kondisi norma | dalam hal ia:
1. tidak melaksanakan suatu perikatan; atau 2. tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu |
| 3. jika ia TIDAK DAPAT membuktikan tentang penyebab-penyebabnya:
(a) karena sesuatu hal yang tidak terduga; (b) ia tak bertanggung jawab atas hal itu; dan (c) ia tak punya iktikad buruk [untuk tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu]. |
Pengertian biaya, kerugian, dan bunga, mengacu pada pasal sebelumnya, yakni Pasal 1243 KUH Perdata. Menurut R. Subekti (1982: 148-149), kata “biaya-biaya” (kosten) dan “kerugian” (schaden) di sini berarti semua biaya dan kerugian yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan oleh si kreditur dan telah menimpa harta benda si kreditur, yang muncul karena kontrak tidak dilaksanakan oleh debitur. Sementara kata “bunga” (interessen) di sini tidak identik dengan nilai uang dari bunga pinjaman, melainkan nilai akibat kehilangan keuntungan yang bisa didapat seandainya kontrak dijalankan oleh si debitur. Ia memberi contoh pengertian kehilangan keuntungan (bunga) ini seperti kehilangan pendapatan dari karcis penonton akibat pertunjukan batal karena pemain yang telah dikontrak tidak bisa tampil di dalam pertunjukan tersebut. Contoh lain adalah kehilangan pendapatan karena ada penjual yang lalai menyerahkan barangnya tepat waktu, padahal pembelinya bermaksud akan segera menjualkan barang itu kepada orang ketiga dengan harga lebih mahal. Orang ketiga ini batal membeli karena barang yang hendak dibelinya itu belum tersedia. Selisih harga antara barang yang dibeli dari penjual pertama dengan nilai barang yang akan dijual ke orang ketiga itu (tetapi tidak jadi) adalah kehilangan pendapatan.
Namun, fokus pembahasan kita dalam tulisan ini, bukanlah pada objek norma tersebut. Fokus perhatian kita terletak pada kata kunci dari norma ini, yakni pada kondisi norma yang ketiga. Sebab, secara kumulatif kondisi norma ketiga inilah yang akan mengubah operator norma. Artinya, jika dipahami kebalikannya, maka debitur justru tidak lagi diperintahkan (tidak harus/tidak wajib) untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga itu, apabila kondisi norma yang ketiga ini menjadi “dapat membuktikan tentang penyebab-penyebab” tersebut.
Persoalannya adalah operator norma apa yang menjadi konsekuensi dari pembalikan kondisi norma tadi? Dalam diagram norma, posisi “tidak lagi diperintahkan (tidak harus/tidak wajib)” punya tiga kemungkinan. Pertama, operatornya menjadi dilarang. Pilihan ini tampaknya tidak masuk akal karena dalam hukum perdata, ketentuan Pasal 1244 ini lebih bersifat mengatur daripada memaksa. Pilihan kedua adalah diizinkan. Pilihan ini adalah implikasi dari diperintahkan. Pilihan menggunakan operator “izin” ini menjadi relevan apabila objek normanya tetap dipertahankan dalam konotasi positif (mengganti biaya, kerugian, dan bunga). Pilihan ini bukanlah opsi yang tepat. Pilihan berikutnya adalah “dispensasi”. Tampaknya pilihan ketiga inilah yang paling tepat, tetapi objek normanya harus diubah menjadi berkonotasi negatif (tidak mengganti biaya, kerugian, dan bunga).
Dengan demikian, kita dapat menyusun ulang pemaknaan Pasal 1244 KUH Perdata tersebut sebagai berikut:
| Subjek norma | Debitur |
| Operator norma | diberi dispensasi [untuk] |
| Objek norma | TIDAK mengganti biaya, kerugian, dan bunga |
| Kondisi norma | dalam hal ia:
1. tidak melaksanakan suatu perikatan; atau 2. tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu |
| 3. jika ia DAPAT membuktikan tentang penyebab-penyebabnya:
(a) karena sesuatu hal yang tidak terduga; (b) ia tak bertanggung jawab atas hal itu; dan (c) ia tak punya iktikad buruk [untuk tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu]. |
Persoalannya adalah apakah kondisi norma (1), (2), dan (3) di atas merupakan kondisi yang dipersyaratkan untuk dapat disebut sebagai force majeure? Untuk itu, kita dapat melanjutkan analisis pada Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal tersebut, menurut terjemahan R. Subekti, berbunyi:
Tidaklah biaya, rugi, dan bunga, harus digantikan, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang (Geene vergoeding van kosten, schaden en interessen heeft plaats, indien de schuldenaar door overmagt of door toeval verhinderd iets gedaan heeft hetwelk hem veroden was).
Pada pasal tersebut kata “overmagt” (sekarang: “overmacht”) diterjemahkan oleh R. Subekti dengan kata “keadaan memaksa”. Istilah inilah yang sekarang makin banyak diterjemahkan sebagai “keadaan kahar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 489), kata sifat “kahar” diartikan sebagai “mahakuasa” (sifat Allah) atau “sewenang-wenang”. Dengan mengacu pada definsi leksikal tersebut, kita dapat mengatakan bahwa keadaan kahar adalah keadaan yang sewenang-wenang yang terjadi di luar kewenangan manusia untuk menduganya terjadi. Karena tidak dapat diduga, maka dengan sendirinya manusia tidak dapat mencegah atau mengantisipasi kejadian tersebut.
JIka Pasal 1245 KUH Perdata distrukturkan, maka akan tampak gambarannya sebagai berikut:
| Subjek norma | Debitur |
| Operator norma | diberi dispensasi [untuk] |
| Objek norma | TIDAK mengganti biaya, kerugian, dan bunga |
| Kondisi norma | dalam hal ia:
1. tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan; 2. tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan; atau 3. melakukan sesuatu yang terlarang; |
| karena:
1. keadaan memaksa (force majeure; keadaan kahar); atau 2. kejadian tak disengaja (= kejadian yang tak dapat dicegah). |
Sekilas tampak bahwa Pasal 1245 hanya mengulang atau mempertegas ketentuan Pasal 1244. Melalui analisis struktur norma, kita dapat dengan jelas melihat bahwa perbedaannya ada pada unsur kondisi norma itu saja. Namun, penambahan unsur “kejadian tak disengaja” pada kondisi norma Pasal 1245 itu tidaklah signifikan karena di dalam Pasal 1244 sudah tertampung oleh kondisi “sesuatu hal yang tidak terduga”. R. Subekti tampaknya juga agak keliru menerjemahkan kata “verhinderen” dalam Pasal 1245 KUH Perdata itu. Kata ini seharusnya dimaknai sebagai “mencegah atau menghalangi”.
Dengan demikian, apabila kedua pasal ini digabungkan pemaknaannya, maka force majeure adalah: “keadaan memaksa yang terjadi tanpa bisa diduga/dicegah [pada saat kontrak terjadi], yang akibat dari keadaan itu membuat debitur, tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu (bentuk-bentuknya berupa: tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan; tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan; atau melakukan sesuatu yang terlarang).” Konsekuensi hukum dari keadaan memaksa ini adalah bahwa debitur tidak wajib (dalam arti diberi dispensasi untuk tidak…) membayar biaya, kerugian, dan bunga, sepanjang ia memang tak dapat (tidak layak) dimintakan pertanggungjawaban atas keadaan memaksa tadi dan semua bentuk wanprestasi/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya itu dilandasi iktikad baik.
Asas iktikad baik (good faith; te goeder trouw; de bonne foi) pada dasarnya adalah asas umum yang langsung mengikuti asas pacta sunt servanda. Hal ini dapat ditelusuri dari penempatan asas ini pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang berdekatan dengan asas pacta sunt servanda.
Pengertian “terlarang” pada kalimat di atas, seharusnya dibaca, tidak hanya terlarang menurut kontrak, tetapi juga menurut kepatutan, kebiasaan, dan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1339 KUH Perdata). Itulah sebabnya, gugatan yang mungkin diajukan terhadap debitur tak hanya dengan landasan wanprestasi, namun bisa pula dengan perbuatan melawan hukum.
Satu pertanyaan yang menggoda adalah: apakah mungkin keadaan memaksa ini hanya dialami oleh debitur, tetapi tidak dialami oleh kreditur? Apakah keadaan memaksa yang secara subjektif dialami salah satu pihak masih dapat disebut force majeure?
Pertanyaan ini menjadi menarik karena di dalam doktrin yang berkembang di negara-negara bersistem civil law, dikenal juga ada clausula rebus sic stantibus. Apakah force majeure ini sama dengan clausula rebus sic stantibus?
Pertama-tama, mari kita cermati makna dari clausula rebus sic stantibus, atau lengkapnya disebut “omnis convention intellegitur rebus sic stantibus”. Secara harfiah, maknanya adalah bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah. Sekilas tidak ditemukan perbedaannya antara force majeure dan clausula rebus sic stantibus ini. Keduanya merupakan penerobosan terhadap asas pacta sunt servanda.
Namun, menurut Prof. Azis T. Saliba (2001), keduanya memiliki perbedaan. Pada force majeure, debitur diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya karena suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya, yang apabila ia dipaksa untuk tetap melaksanakan kewajibannya, maka ia akan menghadapi kondisi yang berat akibat terkendala secara fisik dan hukum. Jadi, pada force majeure kendalanya harus bukan karena alasan ekonomi. Kendala fisik di sini misalnya berupa bencana alam, sehingga jalur transportasi terganggu dan barang tidak dapat diantar tepat waktu. Sementara yang dimaksud dengan kendala hukum, misalnya terjadi karena perubahan mendadak suatu peraturan yang sangat berkaitan dan menjadi dasar terkait isi kontrak. Katakanlah, dulu objek perjanjian adalah legal untuk diperjualbelikan, tetapi kemudian dinyatakan terlarang. Force majeure, esensinya, tidak menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan, misalnya karena debitur mengalami terlilit hutang atau bahkan pailit.
Clausula rebus sic stantibus membolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindar dari kewajiban kontrak. Alasan ini bisa diterima, misalnya, karena debitur tidak dapat melaksanakan kontrak akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis dengan beban bunga yang sangat berat. Pengadilan pun dimungkinkan untuk membatalkan perjanjian yang bermotifkan riba. Lengkapnya Prof. Aziz T Saliba (2001) menulis:
Rebus sic stantibus should not be confused with force majeure. Force majeure excuses the obligor to perform only if there is an irresistible (and unforeseeable) obstacle. In force majeure, the performance must be physically or legally impossible and must not be merely more onerous to perform. Thus, in a nutshell, the fundamental difference is that, unlike rebus sic stantibus, force majeure does not include economic hardship nor even economic impossibility. Rebus sic stantibus was first applied by the ecclesiastical courts, especially when there was a suspicion of usury. It was subsequently adopted by other courts and jurists and this concept thus became widely accepted by the end of the XVIII century. Obviously, as in most historical changes to the law, the acceptation of a particular concept in law gradually faded over time. As Prof. Rosenn explains: “As early as the fifteenth century, the popularity of the theory of rebus sic stantibus had begun to wane, largely because of protests from burgeoning commercial interests against the climate of transactional insecurity produced by the theory’s widespread application. By the end of the eighteenth century, pacta sunt servanda reigned supreme, and the theory of rebus sic stantibus had been relegated to the doctrinal scrap heap. Contributing to its demise were the rise of scientific positivism, and the increasing emphasis on individual autonomy and liberty of contract.”
Seiring dengan menguatnya asas kebebasan berkontrak, maka clausula rebus sic stantibus ini makin tersingkirkan. Asas pacta sunt servanda tetap dijadikan pegangan utama, tetapi tetap dibuka kemungkinan asas ini untuk dikecualikan apabila ditemukan adanya iktikad tidak baik. Tidak mengherankan bahwa tatkala force majeure kemudian lebih dikedepankan, maka force majeure ini beririsan dengan asas iktikad baik tersebut.
Dalam konsep force majeure yang berlaku di Indonesia, dikenal ada force majeure mutlak (absolut) dan force majeure relatif. R. Subekti (1982: 150) kembali menjelaskan, bahwa force majeure yang bersifat mutlak adalah apabila debitur sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan kewajibannya, misalnya karena barang yang diperjanjikan sudah musnah. Force majeure yang relatif terjadi apabila debitur masih mungkin melaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar. Misalnya, terjadi kenaikan harga barang yang sangat tinggi secara tiba-tiba (hiperinflasi).
Pembedaan force majeure mutlak dan absolut ini, berdasarkan kriteria R. Subekti, terletak pada derajat ketidakmungkinan (imposibilitas). Jika ketidakmungkinannya sudah mutlak, tak lagi terbuka kemungkinan berubah, maka ia menjadi keadaan memaksa untuk lahirnya force majeure mutlak. Ketidakmungkinan ini tidak hanya berlaku untuk diri si debitur, melainkan ketidakmungkinan bagi siapapun di dalam kondisi demikian. Jika ketidakmungkinannya masih terbuka untuk jadi mungkin, kendati dengan pengorbanan yang besar, maka ini adalah force majeure relatif. Seandainya kendala ini suatu waktu menghilang atau mereda, masih dimungkinkan prestasi yang semula tidak dilaksanakan itu untuk dimintakan lagi agar dipenuhi oleh si debitur, namun kali ini kreditur tidak diperkenankan mengajukan pergantian biaya, kerugian, dan bunga.
Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa KUH Perdata kita. Pertama, bahwa hukum perjanjian di Indonesia tentu sangat menghormati asas pacta sunt servanda, namun asas ini segera diberi catatan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Oleh sebab itu, ketika kita membahas tentang force majeure sebagai penyimpangan dari asas pacta sunt servanda, maka force majeure ini sendiri mensyaratkan adanya iktikad baik. Kedua, bahwa dasar-dasar force majeure telah diatur di dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Terlihat bahwa sistem hukum perdata di Indonesia tidak membedakan secara tegas antara force majeure dan clausula rebus sic stantibus. Terbukti bahwa hambatan ekonomi pun dapat dijadikan sebagai dasar bagi force majeure yang relatif.
Karena sifatnya yang lebih subjektif sekaligus mempunyai dampak yang lebih eksesif terhadap nasib suatu kontrak dibandingkan dengan force majeure, maka cluasula rebus sic stantibus disikapi secara berbeda pada negara-negara bertradisi civil law. Aziz T Saliba (2001) membedakannya ke dalam tiga model, yaitu model Prancis, model Jerman, dan model Italia. Pada model Prancis, clausula rebus sic stantibus tidak mendapat tempat. Namun pada model Jerman, clausula rebus sic stantibus telah diterima dengan sedikit modifikasi. Tokoh utama yang melakukannya adalah Prof. Oertmann dari Gottingen University. Ia mendefinisikan clausula rebus sic stantibus ini sebagai doktrin dasar kontraktual (contract basis doctrine; Wegfall der Geschäftsgrundlage) bahwa jika perubahan-perubahan yang tak dapat diduga dan mendasar terjadi setelah kontrak dibuat, maka pangadilan dapat menyesuaikan isi kontrak tadi, atau bahkan dapat membatalkan kontrak itu apabila penyesuaian tak dapat dilakukan. Terakhir adalah model Italia yang telah menerima asas ini.
Perlu dicatat, bahwa di dalam video “Seri Paparan Filsafat Hukum” yang memuat diskusi dengan Prof. Stefan Koos dari Jerman, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2002, Jerman pun sudah mengadopsi clausula rebus sic stantibus ini ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman. Tautan video tersebut tercantum dalam bagian terakhir tulisan ini.
Dalam berbagai buku teks hukum perdata yang kerap dipakai sebagai rujukan, clausula rebus sic stantibus hampir tidak pernah disinggung apalagi didalami. Doktrin ini malahan lebih dikenal di dalam hukum [perjanjian] internasional dan sedikit di dalam hukum asuransi. Dengan mencermati perkembangan yang terjadi di Jerman, sangat mungkin secara diam-diam kita sebenarnya sudah mengadopsi doktrin tersebut dan menerapkannya di dalam berbagai kasus di pengadilan. Hanya saja, barangkali kita belum secara formal mengakuinya karena memang tidak pernah dimasukkan ke dalam KUH Perdata (mengingat sampai sekarang pun kita masih belum memiliki KUH Perdata produk Indonesia merdeka). Pandangan seperti ini tentu masih perlu pengkajian lebih jauh: apakah benar bahwa perkembangan hukum perjanjian kita ada dalam posisi sikap seperti itu. (***)
REFERENSI:
Aziz T Saliba (2001). Rebus sic stantibus: A Comparative Survey. Murdoch University Electronic Journal of Law [2001] MurUEJL 18 <http://www5.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/2001/18.html>
R. Subekti (1982). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Tautan video SERI PAPARAN FILSAFAT HUKUM #20:
https://www.youtube.com/watch?v=vm7hYL3YPno&t=476s



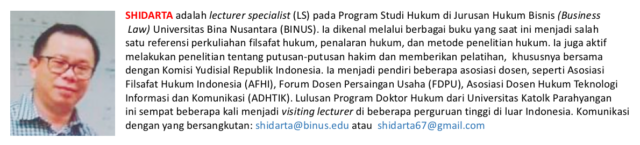
Comments :