COVID-19, MASIH HADIRKAH NEGARA?
Oleh SHIDARTA (April 2020)
Ketika tulisan ini dibuat, Pemerintah pusat sedang dalam keadaan galau untuk memutuskan apakah akan me-lockdown atau harus mengarantina Jakarta dan/atau daerah-daerah lain. Berjangkitnya covid-19 telah menjadi test-case tentang seberapa handal tata kelola pemerintahan kita, termasuk mekanisme konsentrasi dan sentralisasi versus dekonsentrasi dan desentralisasi unsur-unsur pemerintahan.
Satu hal yang pasti, di tengah kegalauan itu, masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama. Mereka biasanya akan segera mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Salah satu, misalnya, dengan cara menutup akses di perumahan masing-masing. Semacam me-lockdown atau mengarantina area perumahan mereka. Tidak jelas siapa yang mengomandoi ini semua. Boleh jadi, ini semacam “virus” juga. Satu perumahan melakukan, dan kemudian berjangkit, diikuti oleh perumahan-perumahan yang lain tanpa jelas apakah pertimbangannya sungguh-sungguh rasional atau emosional.
Bayangkan! Pintu akses warga ditutup dengan dipasang galah atau portal. Namun, warga tentu tidak bisa dihalangi untuk tetap berhilir mudik. Lalu, penutupan ini buat siapa? Apakah hanya buat warga di luar perumahan? Jika ya, apakah berarti ada jaminan pembawa (carrier) virus itu selalu berasal dari warga yang datang dari luar, bukan justru dari warga setempat yang sempat meninggalkan perumahan dan lalu kembali ke rumahnya?
Praktik tutup-menutup ini bisa dilihat contohnya di kota Tegal. Walikotanya menutup akses yang menghubungkan Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal, tapi [menurut laporan reporter televisi] justru bukan di jalan penghubung utama. Penutupan dilakukan di jalan-jalan alternatif dekat permukiman padat, dan ini membuat warga bukannya menjauh satu sama lain, melainkan justru dijadikan ajang kongkow-kongkow dan arena permainan bola oleh anak-anak karena memanfaatkan jalanan yang lengang.
Kejadian lebih lucu terjadi di kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Seorang pengendara mobil dilarang masuk ke satu area hanya karena nomor polisi kendaraannya adalah B (Metro Jaya). Intinya, jika mobilnya berplat nomor B berarti orang ini pasti datang dari Jakarta. Orang Jakarta adalah orang yang berpotensi menularkana virus.
Kita kembali ke cerita tutup-menutup akses ini. Jika sebuah jalan ditutup, maka dengan sendirinya jalan itu harus dijaga oleh warga. Penjaganya bisa jadi orang awam yang tidak tahu protokol untuk menyeleksi warga yang lewat. Di kota Pangkalpinang, penjaganya berbaju hitam dan sorban dengan tulisan di bagian punggungnya “Front Jaga Babel”. Penjaga seperti ini biasanya tidak berani sendirian. Ia “wajib” ditemani beberapa orang, yang posisi duduk/berdirinya pun belum tentu sejalan dengan anjuran jarak minimal (physical-distancing). Belum lagi soal peralatan yang digunakan. Paling-paling amunisi yang dipakai hanyalah masker dan pemindai suhu yang boleh jadi tidak standar. Mereka belum tentu tahu apa beda makna suhu manusia 37 derajat dengan 38 derajat celcius. Jika ada yang bersuhu di atas 38 derajat, mereka juga belum tentu tahu langkah apa yang harus diambil kemudian? Lebih repot lagi jika disinfektan yang disemprotkan adalah produk racikan sendiri, yang dibuat berdasarkan panduan dari Youtube.
Lebih menarik lagi jika ada warga atau tamu yang datang berkendaraan mobil dan meminta izin untuk masuk ke kompleks perumahan tersebut. Jika di dalam mobil itu ada lima orang, apakah kelima orang ini harus dimintakan turun dari kendaraannya, dan diperiksa satu per satu? Bagaimana jika ada yang merasa keberatan, apakah dibolehkan untuk dipaksa dan diusir pergi? Atau, apakah kita cukup menjalankannya sekadar sebagai formalitas. Mirip perilaku petugas di pintu masuk pusat-pusat perbelanjaaan yang membawa metal-detector memeriksa ruang bagasi setiap mobil yang masuk tanpa kejelasan apa yang mereka telisik sesungguhnya.
Ulah vigilante seperti ini sangat menyesakkan dada! Apabila di negara-negara lain (terlepas mereka sudah melakukan lockdown atau belum), petugas keamanan (bahkan sampai militer) berjaga-jaga agar jangan ada warga yang berkeliaran tanpa tujuan yang jelas. Di Jerman, warga akan didenda hingga 300 euro apabila keluar rumah tanpa alasan yang masuk akal. Sebaliknya kita di sini justru menyaksikan warga berinisiatif keluar rumah dengan alasan menjaga lingkungan dari notabene musuh yang tak kasatmata. Penjagaan pun dilakukan dengan protokol yang tidak jelas, sehingga yang terjadi malahan semacam sweeping oleh orang-orang sipil.
Warga sangat mungkin dihimbau oleh ketua RW/RT ikut meluangkan waktu berjaga di pintu-pintu akses tadi, mungkin dengan pertimbangan “mumpung ada di rumah”. Padahal, himbauan untuk tinggal di rumah sama sekali bukan dalam rangka berlibur. Ada sekian banyak warga yang bekerja dari rumah (work from home) yang belum tentu punya waktu duduk-duduk menurun-naikkan portal. Profesi tertentu, seperti guru dan dosen, justru makin terasa berat menjalankan tugas secara daring (online), di tengah kualitas koneksi Internet yang tidak stabil. Dan, demi solidaritas warga diajak untuk ikut menjalankan aktivitas seperti ini.
Dari kaca mata sosiologi, kemunculan inisiatif warga mengambil tindakan yang tidak seyogianya mereka lakukan, sebenarnya menandakan satu hal. Negara tidak lagi hadir! Dalam ranah kemasyarakatan, memang tidak selamanya negara harus hadir di setiap jengkal kehidupan. Namun, dalam situasi yang krusial seperti ini, kita mengharapkan negara benar-benar hadir. Kehadiran negara harus diwakili oleh aparatur resmi negara, bukan oleh para vigilante yang cenderung bertindak tanpa terukur.
Indonesia telah tunduk dengan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Salah satu hak yang dilindungi adalah hak setiap warga untuk bergerak (mobilitas) dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang ini menyatakan:
(1) Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
3.Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.
Jadi, tindakan menghalangi mobilitas orang adalah pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik (sebagai bagian dari hak asasi manusia). Menurut Pasal 4 undang-undang tersebut memang dimungkinkan dilakukan pembatasan pergerakan orang apabila terjadi keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya. Keadaan darurat ini harus telah diumumkan secara resmi oleh negara. Lagi-lagi, berarti yang boleh melakukan pembatasan ini haruslah negara. Itupun masih dikawal dengan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1984) yang tertera dalam Siracusa Principles (Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 [1984]).
Lalu, apakah warga tidak boleh berinisiatif menjaga lingkungannya sendiri? Sangat boleh! Namun, mereka harus tetap dalam kontrol negara. Mereka hanya mengambil peran pembantu. Bukan peran utama! Karena di bawah kontrol negara, maka area-area mana yang ditutup dan seperti apa rekayasa lalu-lalang orang harus dikoordinasikan bersama instansi pemerintah terkait. Akses jalan berhubungan dengan kepentingan publik yang harus dijamin ketersediaan, keamanan, dan kenyamanannya. Untuk itulah, hadirnya aparatur resmi negara mutlak diperlukan untuk memberi kepastian sekaligus pencerahan tentang mana tindakan yang selayaknya dan tidak selayaknya dilakukan oleh warga sipil biasa. Jangan biarkan perilaku arbiter terjadi dan berpeluang memunculkan konflik horisontal yang kontraproduktf. Negara wajib hadir, kapanpun dan dalam situasi seperti apapun, untuk memberi kejelasan dengan ketegasan bersikap, bukan dengan kegalauan! (***)



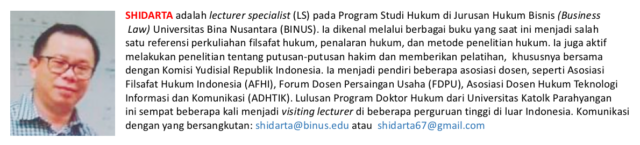
Comments :