CORONA, MASYARAKAT ABSTRAK, DAN PERAN KAUM INTELEKTUAL
Oleh SHIDARTA (Maret 2020)
Tulisan ini dibuat dalam suasana yang kurang menyenangkan, ketika kehidupan tidak berjalan normal. Sebagai seorang dosen yang terbiasa pergi-pulang ke kampus, sekarang kondisinya terpaksa harus mengajar dan mengerjakan tugas-tugas dari rumah. Inilah dampak kekhawatiran terpapar virus covid-19. Di tengah situasi seperti ini, berbagai isu seputar virus ini bertebaran di jagad maya. Seperti biasa, isu-isu itu berkembang mulai dari yang berdimensi realistis sampai ke transendental.
Ada yang mengulas perebakan virus ini sebagai bagian dari konspirasi politik kelas tinggi. Ada lagi yang mengatakan ini kecelakaan laboratorium. Namun, ada juga yang mengatakan ini bagian dari azab Tuhan, dan virus-virus itu adalah tentara-Nya. Sangat menarik, bahwa pencetus “teori-teorian” itu dengan sangat percaya diri menyampaikan gagasan mereka dan ketika buah dari gagasan itu sudah terlanjur menyebar ke mana-mana (beranak pinak melalui satu ponsel ke ponsel yang lain), dan kemudian terbukti ada fakta yang tidak lagi koheren dengan pandangannya semula, si penggagas tetap tampil tanpa rasa bersalah. Tidak ada inisiatif untuk meralat. Filosofinya, “lempar batu sembunyi tangan.”
Semua teori pasti punya derajat spekulasi, namun jelas yang paling mengganggu dari semuanya (karena paling spekulatif) adalah teori-teorian yang berdimensi transendental. Hal ini tidak lain karena kemampuan teori-teorian tadi untuk diverifikasi, terbilang paling rendah. Alih-alih untuk membangun kognisi para penerima pesan, yang justru ditonjol-tonjolkan mereka adalah sisi emosi. Sesuatu yang kontraproduktif dalam situasi seperti ini.
Koherensi yang lazim dibangun oleh si penggagas paham transendental adalah dengan mengandalkan penafsirannya berangkat dari teks. Proposisi tekstual yang paling mapan tentu teks kitab suci (apapun agamanya). Teks inilah yang kemudian dikaitkan dengan suatu fenomena untuk kemudian dicarikan logika pembenarannya.
Menurut ilmuwan Islam Indonesia terkemuka [Almarhum] Kuntowijoyo, teks kitab suci (dalam hal ini ia mengacu pada Al-Quran) adalah teks yang merujuk ke gejala-gejala sosial lima belas abad yang lalu di Jazirah Arab. Artinya, ada jarak sosio-historis yang jauh antara masyarakat Arab ketika itu dengan masyarakat kita sekarang ini. Pada masa itu, masyarakat Arab masih terbilang homogen sebagai masyarakat kesukuan (tribal society). Sekarang, apalagi untuk konteks Indonesia, masyarakatnya sudah masuk ke era industri (atau malahan sudah pasca-industri), masyarakat kenegaraan (civic society) dan heterogen.
Tulisan berikut ini akan banyak mengambil konteks diskursus Islam di Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa fenomena ini sangat khas terjadi pada Islam saja. Hal (baca: krisis) serupa jelas terjadi pada semua agama dan keyakinan. Alasan untuk mengambil konteks Islam, tidak lain karena sumber rujukan tulisan ini adalah karya Kuntowijoyo (terbit 2018) yang sangat menarik untuk dijadikan pisau analisis.
Kuntowijoyo memperkenalkan satu metode dalam rangka memahami semua fenomena ini, yang disebutnya sebagai metode strukturalisme transendental. Untuk sampai pada pemahaman tentang metode ini, Kuntowijoyo mengawali penjelasannya tentang apa itu struktur, strukturalisme, transendental, dan kemudian strukturalisme transedental. Karena keterbatasan tempat, tulisan kecil ini tidak akan merangkum alur pemikiran tersebut.
Metode strukturalisme transendenal diklaim oleh Kuntowijoyo mampu menyikapi jarak sosio-historis yang terjadi dalam pemahaman teks yang turun puluhan sampai belasan abad lalu dengan kekinian dan keterdisinian kita. Menurutnya, agama-agama bereaksi secara berbeda dalam melihat perubahan-perubahan sosial tadi, menyesuaikan dengan karakter mereka masing-masing. Sebagai contoh, agama Kristen bisa menerima sekularisme (menerima perbedaan antara hak raja untuk urusan duniawi dan hak Tuhan terkait urusan akhirat), sedangkan Islam tidak dapat menerimanya (karena tidak membedakan dunia dan akhirat). Sekularisme direspons positif di dalam Kristen [Protestan] dengan cara kultural (mengadopsinya ke dalam ranah moral, filsafat, teologi), sedangkan Islam menanggapinya secara struktural (ranah politik dan bisnis). Kata Kuntowijoyo:
Paul Tillich hanya memerlukan bahasa baru dalam menghadapi sekularisme (James Luther Adam, ‘Paul Tlllich’s Philosophy of Culture, Science and Religion,’ New York: Schocken Books, 1970), sementara umat Islam memerlukan institusi-institusi baru (pendidikan, politik, ekonomi) dan simbol-simbol baru (busana, budaya, bujana).
Sebagai seorang intelektual Islam, Kuntowijoyo ingin agar segi muamalah (pergaulan antar-manusia di dunia) tidak boleh sampai ketinggalan zaman dan haruslah efektif. Ia lalu memperkenalkan enam macam kesadaran untuk memperluas muamalah tadi. Dalam tulisan ini hanya akan disinggung beberapa di antaranya. Kita mulai dari keadaran tentang perubahan, yakni kesadaran bahwa apa yang terjadi pada puluhan dan belasan abad lalu tidak lagi sama dengan kondisi sekarang. Sebagai contoh peran pemimpin agama tradisional (kiai) sudah tergantikan dengan tokoh-tokoh dan media lain-lain. Sebuah tabel menarik ditampilkan oleh Kuntowijoyo dalam esainya berjudul “Dalam Masyarakat Industrial Ulama Bukan Lagi Ketegori Sosial”. Pada tabel ini terlihat bagaimana masyarakat pra-industrial, semi-industrial, dan industrial itu memandang siapa yang disebut sebagai “ulama”. Lalu, seperti apa mereka berkomunikasi, mengambil peran, dan pola rekrutmennya.
Sinyalemen Kuntowijoyo di atas mendapatkan pembenaran dalam penyebaran isu-isu Corona saat ini. Seseorang yang disebut “ulama” sekarang bukan lagi kiai dan guru, melainkan semua yang menjadi mitra mereka. Ulama kita sekarang adalah para buzzers dan influencers, yang dengan nyaman kita panggil atau memanggilkan diri mereka dengan istilah “guys” atau “bro”. Ulama tidak perlu lagi punya pondok pesantren atau sekolah/universitas. Orang mencari obat untuk menangkal virus corona tidak harus bertanya kepada dokter, melainkan bisa ke para pembuat konten di media elektronik seperti Youtube. Andaikan ada dokter yang mencoba membuat konten serupa, sangat mungkin jumlah viewer-nya [apalagi yang ‘like’ ] kalah jauh dengan anak SMA yang membuatnya secara asal-asalan, tanpa referensi teks book atau jurnal ilmiah.
Gelar kiai dan ustad/ustadza (guru) bisa dilekatkan kepada siapa saja sepanjang disukai komunitasnya. Mereka direkrut secara sporadis. Artis yang baru saja ber-hijrah (istilah yang makin populer saat ini) bisa tiba-tiba menambahkan gelar itu di depan nama mereka dan tenang-tenang saja seolah tanpa beban dengan predikat itu. Beberapa waktu lalu, misalnya, terkuak ada “ustad ” yang ternyata tidak menguasai ilmu nahwu karena tidak bisa membedakan antara kafir dan kuffar. Notabene, tidak lama berselang, kita dapat menyaksikan figur “ustad” tadi masih tetap percaya diri tampil di hadapan publik, tanpa harus mengklarifikasi dan menanggalkan label ustad yang disematkan padanya. Ceramahnya tetap diunggah di Youtube dan mendapat “like” dan “subscribe”. Pemilik modal juga tetap senang memasang iklan di sela-sela unggahan Youtube-nya. Apa yang terjadi dengan kita?
Kuntowijoyo menyebut ada satu lagi kesadaran yang penting disinggung di sini, yang disebutnya sebagai kesadaran tentang masyarakat abstrak. Tampaknya, kuncinya ada di sini. Ia menulis sebagai berikut:
Di dalam masyarakat peralatan pra-indstrial, orang hidup dalam masyarakat konkret, real, hubungan orang dengan orang, dan hubungan dari muka ke muka. Akan tetapi, hubungan dari muka-ke-muka ini hilang ketika masyarakat abstrak (Baca Anton C. Zijderveld, The Abstract Society: A Cultural Analysis of Our Time. New York: Anchor Books, 1971). Dalam masyarakat industri, yang mengatur bukan lagi orang, melainkan sistem. Setiap orang diharapkan berpartisipasi dalam sistem yang abstrak, impersonal. Karakteristik perorangan (akhlak, keimanan, emosi, kepentingan) harus dapat menyesuaikan diri (conform) dengan sistem. Sistem (birokrasi, pasar) sangat bergantung pada kualifikasi objektif, tidak lagi kualifikasi subjektif.
Masyarakat kita tampaknya bermasalah pada aspek ini. Di satu sisi, kita sudah berada dalam masyarakat abstrak, namun di sisi lain kesadaran kita akan perubahan membuat kita lalai menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berperan dalam masyarakat abstrak tadi. Pegiat keagamaan kita terlena dengan model pembelajaran era pra-industrial dan semi industrial. Kekosoongan inilah yang diisi oleh para ‘rohaniawan’ yang tidak cukup berakar secara intelektual. Oleh sebab itu, kita bisa mengkritisi kolom peran ulama pada tabel di atas. Kita belum mengaksentuasi peran “intelektual” tadi pada masyarakat industrial ini, tetapi masih berpegang kuat pada peran sosial dan politik. Kelalaian ini sesungguhnya juga menimpa dunia pendidikan kita (isu ini bisa kita bahas pada kesempatan lain).
Uniknya lagi, media yang semula terkooptasi oleh basis-basis kekuatan sosial-politik (termasuk pelaku bisnis) tertentu, terbukti tidak lagi kuasa mengontrol arus informasi dan komunikasi pada masyarakat abstrak tadi. Media arus utama (mainstream) telah kehilangan pengikut. Orang menonton TV tidak lagi melalui tayangan langsung oleh stasiun televisi, melainkan melalui hasil postingan potongan-potongan yang disukai penonton. Teknologi filter bubble telah mampu menyisir mana informasi yang disukai dan tidak disukai itu, sehingga penerima informasi akan “dimanjakan” dengan informasi-informasi satu sisi saja. Oleh sebab itu, tidak heran tatkala isu virus corona ini membanjiri mayantara tanpa terkendali arahnya, salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah berusaha membendungnya bekerja sama dengan para buzzers dan influencers.
Kondisi masyarakat industrial Indonesia dewasa ini belum siap dengan peran kaum intelektual seperti yang dipetakan oleh Kuntowijoyo. Kaum intelektual adalah orang yang cenderung berhati-hati dalam menyampaikan pandangannya. Filosofinya adalah: “tahu jika ia tidak tahu dan lebih baik diam jika tidak tahu”. Mereka tidak asal bicara atau asal nyaring bersuara; mereka yang bertolak dari iktikad baik tatkala menafsirkan setiap teks; mereka yang yakin bahwa ia mungkin salah dan orang lain mungkin saja benar, sehingga ia tidak selalu berkelit dalam kuasa tafsir transedental lalu mengklaimnya sebagai monopoli kebenaran. Mereka juga masih punya rasa malu dan khawatir jika berbuat salah dan segera meralatnya apabila ternyata keliru. Mereka inilah contoh-contoh kaum intelektual yang diharapkan mampu mengisi situasi-situasi genting pada masyarakat abstrak di era industrial [atau pasca-industrial] ini.
Isu corona masih di depan mata. Di mana mereka kaum ulama sejati kita? Kita sungguh-sungguh merindukan mereka! (***)
REFERENSI:
Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai al-Qur’an pada Masa Kini. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.




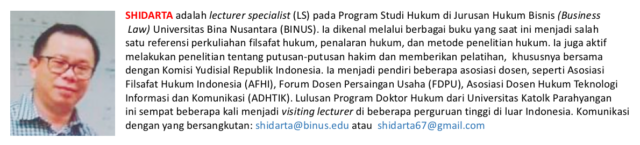
Comments :