RADIKALISME: TAK KENAL MAKA TAK SAYANG
Oleh SHIDARTA (Maret 2020)
Pembelajaran disiplin hukum sangat memerlukan bantuan ilmu-ilmu empiris tentang hukum. Berkat bantuan ilmu-ilmu empiris ini suatu fenomena hukum dapat dibawa ke dimensi yang lebih komprehensif, dengan sudut optik yang lebih tajam dan mendalam.
Salah satu ilmu empiris tentang hukum yang sangat berjasa adalah psikologi. Ada banyak cabang dari psikologi itu. Salah satu yang ingin diangkat di sini adalah psikologi sosial. Dan, di antara berbagai teori psikologi sosial, pada kesempatan ini kita pilihkan satu pemikiran yang disampaikan oleh psikolog asal Polandia bernama Robert Zojanc (1923-2008). Beliau menawarkan pendekatan familiaritas (familiarity) dalam teorinya. Intinya, beliau menyatakan: ““The more you see it, the more you like it.”
Budaya Indonesia tentu tidak asing dengan pandangan ini karena kita juga mengenal pepatah yang berbunyi: “Tak kenal maka tak sayang!” Pengenalan adalah suatu pendekatan familiaritas sebagaimana diteliti oleh Zojanc. Orang Jawa juga mengenal petitih yang kurang lebih sama arahnya: “Witing tresno jalaran soko kulino” bahwa cinta (baca: rasa sayang atau rasa suka) datang dari kebiasaan (familiaritas).
Para pengiklan produk-produk konsumen tentu sangat membenarkan teori ini, sehingga tidak heran jika mereka rajin menayangkan iklan suatu produk sesering mungkin di sebanyak mungkin media. Tujuan pengulangan itu adalah untuk membangun keterbiasaan, sehingga terbangunlah preferensi yang emosional. Zojanc memulai konsepnya dari “repetisi” (repeated exposure) yang melahirkan famliaritas atas perilaku pengulangan itu. Dari sini lalu muncul perubahan sikap (attitude change). Selanjutnya, timbul preferensi atau afeksi (preference or affection). Pada akhirnya, terbangun ikatan emosional yang mewujud di level alam bawah sadar (subconscious level) sebelum seseorang menyadarinya (lihat Collin et al, 2012: 230-235).
Pandangan Robert Zajonc ini dapat kita tunjukkan juga pada apa yang dikenal di dalam hukum sebagai Sindroma Stockholm. Kejadiannya bermula dari kasus perampokan bank di kota Stockholm (Swedia) tahun 1973. Dalam kasus itu, perampok telah menyandera sejumlah pegawai bank, namun setelah sekian lama berlangsung interaksi antara perampok dan pegawai tersebut muncullah rasa empati dari pegawai tersebut kepada penyanderanya. Psikologi hukum membantu menjelaskan fenomena ini yang juga dikenal dengan traumatic bonding atau victim brainwashing. Hal ini terjadi karena korban sangat terkesan dengan satu perilaku positif dari pelaku kejahatan, sehingga korban menyimpulkan pelaku ini tidaklah berbahaya. Dalam kasus di Sockholm itu, misalnya, pegawai yang disandera justru lebih mengkhawatirkan akibat tindakan polisi yang ingin membebaskan mereka.
Saat ini, di tengah membanjirnya informasi di media non-mainstream, kita sebenarnya telah terjajah oleh proses seleksi informasi yang dilakukan oleh mesin. Sekali kita membuka laman youtube yang menginformasikan aktivitas Presiden Joko Widodo, misalnya, maka info-info serupa akan berdatangan pada kali kedua, ketiga, dan seterusnya saat membuka laman youtube itu. Hal yang sama berlaku pada media sosial seperti face-book. Itulah sebabnya, preferensi pada saat ini menjadi lebih mudah terbentuk karena bantuan teknologi informasi. Bisa dibayangkan apabila informasi yang dicari adalah tawaran-tawaran ekstrem berpaham radikal. Sumber informasinya cukup dilacak sekali, dan selanjutnya giliran orang yang bersangkutan itulah yang bakal dikunjungi secara rutin oleh penyedia informasi demikian.
Apabila di era sebelumnya orang-orang dapat melakukan seleksi secara mandiri dan mudah mencari informasi berbeda (counter information), maka hal itu tidak lagi bisa dilakukan saat ini. Seorang aktivis Internet bernama Eli Pariser menyebut rekayasa algoritma seperti ini sebagai “filter bubble” bahwa di Internet kita hanya disuguhi apa yang cocok dan kita sukai. Dalam konteks ini, tindakan otoritas negara untuk menangkal “jualan” berupa repetisi atau replikasi informasi tentang radikalisme sesungguhnya sangat beralasan. Artinya kita butuh filter negara di atas filter bubble itu. Masalahnya memang, apakah filter negara itu tidak berujung pada penyalahgunaan kewenangan yang secara otoriter menggasak kebebasan berekspresi? Ini suatu pilihan dilematis!
Apabila kita kembali ke teori Zojanc, maka model preferensi yang emosional seperti itu sangat dahsyat karena ia bekerja di alam bawah sadar. Kekuatan alam bawah sadar ini ternyata juga sangat mencengangkan, karena ia tidak hanya mengubah pikiran orang, melainkan sampai ke tampilan fisik orang-orang itu. Suami dan isteri yang hidup bersama bertahun-tahun dalam kebahagiaan dan cinta, akan senang merepetisi perilaku masing-masing, dan akhirnya membentuk pola kebiasaan bersama. Itulah sebabnya, kata Zojanc, suami dan isteri itu dalam jangka waktu lama kerap memiliki kesamaan bentuk wajah seolah-olah seperti saudara kandung.
Jangan-jangan dalam jangka waktu lama, rekayasa teknologi dalam permainan algoritma berupa “filter bubble” ini akan membentuk kesamaan tampilan fisik kita sesuai preferensi kita mengkonsumsi informasi di media sosial. “Anda radikal, karena ciri-ciri Anda memang demikian!” Wallahua’lam. (***)
Referensi: Catherine Collin et al. The Psychology Book. London: Dorling Kindersley, 2012



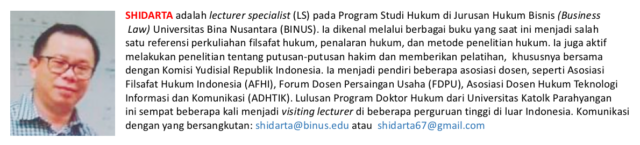
Comments :