KAWIN PAKSA LEGISLASI ALA “OMNIBUS LAW”
Oleh SHIDARTA (Februari 2020)
Omnibus law yang saat ini telah menjadi terminologi buah bibir, konon dimaknai sebagai model pembentukan undang-undang yang memangkas sejumlah undang-undang terkait yang sudah berlaku (existing legislation) untuk kemudian diformulasikan kembali sebuah undang-undang baru. Secara substansial, undang-undang ini akan beirisan dengan undang-undang lain dalam hierarki yang sederajat, sehingga perbenturan norma bakal menjadi problematika hukum yang harus dicermati.
Undang-undang omnibus tidak didesain untuk mencabut undang-undang yang sudah ada, melainkan justru akan mengawinkan beberapa undang-undang yang sudah ada tersebut. Artinya, akan banyak undang-undang terkait yang sudah ada sebelumnya, akan tetap berlaku. Hanya saja, terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam perkawinan itu bakal ada “duri-duri” yang mengganggu, sehingga onak-onak ini harus dipangkas. Dalam hal ini sejumlah pasal dari undang-undang terkait harus dinyatakan tidak berlaku lagi.
Gaya legislasi seperti ini tentu tidak sejalan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal. Undang-undang omnibus sejatinya memang hanya diperuntukkan sebagai obat jangka pendek dan sangat pragmatis guna mengatasi tumpang tindih dan belantara pengaturan. Namun, gaya legislasi seperti ini jelas mengandung dan mengundang bahaya. Bahaya yang dimaksud pertama-tama karena mengingat posisinya sangat tinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan jauh berbeda jika level omnibus law ada pada peraturan pelaksanaan, katakanlah setingkat peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Karena levelnya undang-undang, maka dengan sendirinya akan banyak asas-asas hukum yang bakal diterabas. Niat awalnya memang ingin menghilangkan “duri-duri” tadi, namun ternyata tindakan memangkas onak-onak itu sama artinya dengan mencabut nyawa undang-undang yang dimaksud. Sebagai contoh, konon pasal-pasal tentang persekutuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, dan 1623, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Apabila niatnya ingin meniadakan bentuk perusahaan yang bernama “pesekutuan perdata” maka mana mungkin hanya enam pasal itu saja yang dicabut? Mengapa tidak seluruh Bab Kedelapan kodifikasi itu saja yang dicabut? Dapat dibayangkan Pasal 1624 sampai dengan 1652 tetap eksis, padahal nyawa mereka ada pada keenam pasal yang kini sudah “berpulang” lebih dulu. Kalaupun pasal-pasal itu tetap eksis, mereka bakal seperti anak ayam kehilangan induk.
Isu yang sama terlontarkan dan sempat ditanyakan sejumlah kalangan pada penulis adalah tentang pencabutan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Benarkah pencabutan Pasal 4 itu akan mencabut nyawa keseluruhan Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu? Pasal 4 tersebut menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kata sambung yang dipakai dalam pasal ini adalah kata DAN, bukan kata ATAU. Dengan demikian, pasal ini berkenaan dengan semua produk yang diimpor dari luar negeri dan masuk ke Indonesia, lalu beredar di Indonesia, dan kemudian diperdagangkan di Indonesia. Ekstremnya, bisa saja suatu barang diimpor dan beredar di Indonesia, tetapi tidak untuk diperdagangkan; maka, terhadap produk itu tidak ada kewajiban untuk bersertifikat halal. Namun, kita harus cermati bahwa ada pasal lain di dalam undang-undang ini, yaitu Pasal 26, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal. Sebagai gantinya, ia wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut. Siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha di sini? Menurut undang-undang ini, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dengan demikian, kita dapat menafsirkan pencabutan Pasal 4 itu tidak otomatis mencabut roh dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan pencabutan pasal itu berarti, pelaku usaha tetap boleh mengimpor produk non-halal, mengedarkan, dan memperdagangkannya. Oleh karena sudah non-halal, maka dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha itu untuk mengajukan permohonan sertifikat halal.
Terlepas dari itu semua, naskah yang sampai di tangan penulis sampai saat ini dan juga beredar di banyak kalangan, belum tentu dapat dijamin otentisitasnya sebagai naskah dari rancangan undang-undang itu. Penyebutan pasal-pasal yang dinyatakan dicabut itu, hanyalah sekadar contoh dari kompoleksitas dan kompikasi persoalan yang bakal dihadapi dari ketidakhati-hatian dalam mengawinpaksakan berbagai produk hukum di dalam sebuah undang-undang untuk tujuan jangka pendek dan pragmatis.
Kita tentu masih ingat bahwa pada era-era pemerintahan sebelumnya, model pemangkasan legislasi secara parsial, jangka pendek, dan pragmatis seperti demikian, sudah dikenal dengan predikat paket-paket kebijakan. Contohnya adalah Pakto 88 (Paket Kebijakan Oktober 1988) yang mensimplifikasi perizinan dalam pendirian bank. Awalnya kebijakan ini disambut antusias karena berhasil mendorong para pengusaha swasta beramai-ramai mendirikan bank dengan cukup bermodalkan Rp10 milyar. Fokus perhatian yang hanya berjangka pendek dan pragmatis ini akhirnya harus dibayar mahal karena bertabrakan dengan prinsip-prinsip perbankan yang harus pruden dan berkelanjutan. Dalam waktu satu dekade kemudian, bank-bank karbitan ini jatuh kolaps dan justru menjadi beban yang terus menggerogoti keuangan negara. Pengalaman traumatis berbumbu skandal seputar kasus ini tentu bukan hanya jadi catatan sejarah, namun perlu benar-benar dihayati agar semangat pembentukan undang-undang omnibus ini tidak berujung pada tragedi serupa.
Pemerintah sebagai penggagas undang-undang omnibus kali ini harus benar-benar ekstra-hati-hati dalam mengeluarkan produk legislasi yang berspektrum luas tapi bertendensi pragmatis seperti ini. Niat baik saja tidak cukup! Pemerintah dan DPR harus membuat berbagai simulasi apabila undang-undang ini diasumsikan akan diberlakukan dan jika pasal-pasal tertentu dari undang-undang lain harus dicabut dan/atau tersentuh (sehingga membutuhkan reinterpretasi). Kehati-hatian ini sejalan dengan pesan yang kerap disampaikan oleh Presiden kita. “Semua harus dikalkulasi…!”
Lon F. Fuller pernah mengingatkan delapan pesan moral yang kemudian dikemasnya menjadi principles of legality. Salah satu di antaranya dan penting diingatkan di sini adalah tentang prinsip publisitas. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada saat undang-undang sudah jadi untuk diletakkan di lembaran negara atau berita negara, melainkan harus sudah diterapkan sejak awal pembahasannya. Pembahasan rancangan undang-undang harus dibuka seluas-luasnya, kendati risikonya bakal menuai kebisingan. Itulah sebuah proses yang sepatutnya dijalankan karena peraturan itu bakal berdampak pada mereka. Biarkan publik, khususnya dunia akademisi, aktivis, dan praktisi mewacanakan. Apalagi jika derajat peraturan itu sudah di level undang-undang. Benar bahwa pembahasan setiap rancangan undang-undang akan melibatkan wakil-wakil rakyat, tetapi pemegang kedaulatan sesungguhnya tidak di tangan mereka. Realitas politik kita masih menunjukkan anggota DPR kita saat ini lebih bertendensi sebagai wakil partai politik daripada wakil rakyat. Pemegang kedaulatan sesunggunya ada di tangan rakyat itu sendiri. Dengan demikian, rakyat perlu ikut didewasakan dan diedukasi guna mengontrol jalannya setiap undang-undang yang jelas-jelas berdampak pada kehidupan mereka.
Besar kemungkinan Pemerintah kita sedang ingin “kerja cepat”; sebuah sikap yang layak didukung dan diapresiasi. Jika kita terlambat, kesempatan kita mencuri hati investor bakal direbut oleh negeri tetangga. Tapi, prinsip-prinsip pembentukan peraturan setingkat undang-undang memang tidak bisa dikompromikan dengan alasan-alasan seperti itu. Di sisi lain, para investor pun sebenarnya tidak cukup hanya dijanjikan peluang menggiurkan, tetapi terlebih-lebih adalah juga stabilitas. Di alam demokrasi, stabilitas dapat dibangun, salah satunya secara deliberatif melalui keterbukaan informasi atas semua rancangan produk hukum.
Kecepatan Pemerintah dan DPR bekerja tidaklah sama artinya dengan operasi senyap; untuk kemudian rakyat harus dikejutkan dengan kehadiran undang-undang bak karya Bandung Bondowoso atau Sangkuriang. Apalah artinya kita punya undang-undang omnibus “hasil kawin paksa” tapi tidak berujung pada kebahagiaan kedua mempelai. Setiap perkawinan, juga perkawinan undang-undang, mendambakan hal yang sama, yaitu kedamaian, rasa cinta, dan kasih-sayang: sakinah mawaddah, warramah. (***)



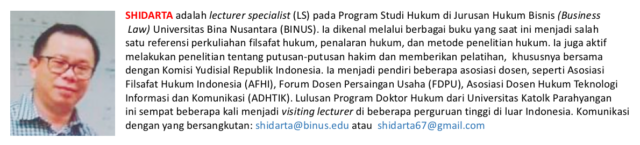
Comments :