TAHANAN DAN PRINSIP HABEAS CORPUS
Oleh SHIDARTA (Januari 2020)
Salah satu kajian menarik dalam kriminologi adalah tentang penahanan terhadap tersangka yang dilakukan di instalasi yang di Indonesia dinamakan sebagai “rumah tahanan” (rutan). Pada hakikatnya rutan dibedakan dengan penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Rutan disediakan bagi orang-orang yang belum divonis sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, para tahanan juga sering dititipkan di lapas, sedangkan untuk anak-anak pada lembaga pembinaan khusus. Total jumlah lapas, lembaga pembinaan khusus, dan rutan di Indonesia ada sebanyak 523, yang per Januari 2020 dihuni oleh lebih dari 260.000 orang tahanan.
Bukan cerita baru bahwa pengelolaan rutan di mana-mana menjadi persoalan tersendiri dalam sistem penegakan hukum. Gambaran yang kurang lebih sama tentu juga terjadi pada pengelolaan penjara. Robert J. Wright (The Jail and Misdemeanant Institution, 1951) menggambarkan sel tahanan itu sebagai pekerjaan, sumber pendapatan, sekaligus [pamer] kekuasaan. Artinya, rutan selalu dijadikan lahan basah untuk mencari uang oleh oknum-oknum di dalamnya. Padahal, jika kita konsisten dengan asas praduga tidak bersalah, penghuni rutan adalah orang-orang yang seharusnya belum pantas dihukum karena mereka memang belum berstatus terpidana. Mereka menjadi penghuni rutan berangkat dari penilaian subjektif penyidik bahwa mereka mungkin akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan/atau menghilangkan alat bukti.
Dalam sistem hukum di Amerika Serikat, penahanan dapat dihindari apabila tersangka dapat memberikan jaminan. Sistem ini kerap menimbulkan kecaman karena menjadikan penghuni rutan hanyalah orang-orang yang tidak mampu membayar jaminan. Hal ini diperparah lagi dengan persepsi bahwa orang-orang miskin penghuni rutan tadi sudah pasti bersalah sebagaimana telah dituduhkan kepada mereka. Penempatan mereka di rutan hanyalah tempat singgah sebelum akhirnya mereka menjadi penghuni penjara seusai kasusnya diputus di pengadilan.
Tentu tidak dapat disangkal bahwa penahanan pada hakikatnya adalah tindakan punitif juga, terlepas apapun alasannya. Penahanan adalah perampasan kemerdekaan seseorang, sehingga tindakan ini harus sangat selektif dilakukan. Untuk itu Sutherland et al (2018: 428-430) menyarankan tujuh tindakan alternatif untuk mengurangi peluang penyalahgunaan rutan guna memperbaiki kondisi punitif di sana.
Pertama, jumlah penangkapan harus dikurangi, dengan didahului pemberian surat peringatan atau surat panggilan polisi (citation). Mekanisme surat peringatan ini biasanya dipakai untuk tindak pidana ringan, seperti pelanggara lalu lintas. Kedua, dalam hal penangkapan dan penahanan diperlukan, maka mekanisme pembebasan dengan membayar jaminan harus diperluas. Kendati mekanisme ini menimbulkan “kecemburuan” dari kelompok masyarakat tidak mampu, dalam kenyataannya kebijakan ini tetap dipertahankan di banyak negara. Ketiga, mempercepat proses pengadilan agar beban instansi penyidikan dan penuntutan dapat dikurangi. Keempat, memperbaiki kondisi rutan agar lebih sehat bagi para penghuni. Tujuannya tentu agar mengurangi kondisi punitif yang terlanjur dilekatkan pada rutan. Kelima, pemisahan lokasi tahanan dengan lokasi terpidana (narapidana). Untuk kondisi di Indonesia, seharusnya memang penempatan tahanan tidak boleh dicampur dengan terpidana, bahkan untuk penyebutan institusinya pun harus dibedakan walaupun mungkin keduanya ada dalam satu bangunan yang sama. Misalnya, seorang tahanan tidak ditempatkan di Lapas Cipinang, melainkan Rutan Cipinang. Manajemen pengelolaannya juga wajib untuk dibedakan. Keenam, Sutherland menyarakan agar penanganan tahanan menjadi tugas dari negara bagian yang terkait. Untuk konteks Indonesia, saran ini tidak terlalu relevan. Tidak ada jaminan bahwa penanganan tahanan oleh pemerintah daerah akan menjamin kondisi dan perlakuan yang lebih baik terhadap para tahanan itu. Ketujuh, adanya penggantian (kompensasi) atas akibat penahanan apabila kemudian terbukti ia tidak bersalah di pengadilan. Perihal ketujuh ini bersinggungan erat dengan prinsip habeas corpus.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) memang sudah dianut prinsip habeas corpus, dengan memberi hak bagi tersangka mem-praperadilan-kan penyidik yang “cacat hukum” dalam menjalankan prosedur menurut hukum acara. Dalam praktik, memang ada kritik bahwa hakim-hakim di sidang praperadilan kerap tidak cukup jeli memeriksa alasan penyidik untuk menahan tersangka. Para hakim terjebak hanya pada pemeriksaan kelengkapan administratif saat akan dilakukan penahanan, bukan pada cukup tidaknya alasan dilakukan penahanan itu. Kata-kata “penilaian subjektif penyidik” di sini cenderung dimaknai sebagai “hak eksklusif milik penyidik”.
Pengejawantahan prinsip habeas corpus sebenarnya juga berlanjut pada pemberian kompensasi terhadap tindakan penyidik yang keliru dalam memproses seorang “pesakitan hukum”. Perihal kompensasi ini dapat dicermati dalam Pasal 95, 96, dan 97 KUHAP. Ketentuan Pasal 95 KUHAP memberi penegasan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Cikal bakal penerapan prinsip habeas corpus dalam konteks ini muncul dalam kasus Fay versus Nola (1963), ketika Mahkamah Agung di Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu bertanggung jawab secara hukum atas pemenjaraan seseorang; jika pemenjaraan itu tidak dapat dibuktikan sesuai dengan persyaratan fundamental dari undang-undang maka orang itu berhak untuk dibebaskan segera.
Dari optik kriminologi, tentu pencantuman prinsip ini di dalam KUHAP tidak serta merta menjamin semuanya bakal berjalan seperti bunyi teks undang-undang. Kriminologi sebagai ilmu yang dekat dengan sosiologi memiliki satu bagian yang disebut “sosiologi hukuman dan koreksi”. Bagian dari kriminologi ini akan menganalisis penerapannya di lapangan, sejauh mana para tahanan yang berjumlah lebih dari 260.000 tersebut memahami hak mereka untuk menuntut kompensasi apabila terjadi kekeliruan penahanan. Seandainya pun mereka paham, juga perlu dicermati seberapa banyak yang menganggap berharga untuk memperjuangkan prinsip habeas corpus ini. Apabila banyak yang pesimistis memperjuangkannya, maka ini tentu berkorelasi dengan asumsi kecilnya peluang negara akan memenuhinya. Jika demikian halnya, dengan mengutip penegasan hakim agung dalam kasus Fay versus Nola (1963) di atas, jangan-jangan sistem hukum pidana kita belum layak disebut sistem yang beradab. (***)
REFERENSI:
Sistem Database Pemasyarakatan. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current>. Akses 20 Januari 2020.
Sutherland, E.H., Cressey, D.R., & Luckenbill, D.F. (2018). Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi. Terjemahan Tri Wibowo. Jakarta: Prenadamedia Group.



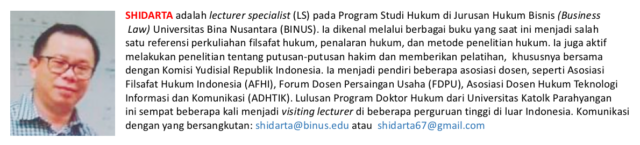
Comments :