MENJUAL JANJI SURGAWI
Oleh SHIDARTA (Januari 2020)
Baru-baru ini serangkaian kasus jual-beli berkedok syariah ramai diperbincangkan masyarakat karena konon tidak dapat dipertanggungjawabkan. Modus operandinya bisa berupa apa saja, mulai dari tawaran jasa pemberangkatan umorh/haji, investasi perkebunan, sampai jual-beli perumahan (real estate). Jumlah korbannya fastastis. Untuk kasus travel umroh yang paling menghebohkan, menurut berbagai pemberitaan, korbannya mencapai 63 ribu jemaah yang gagal diberangkatkan dengan akumulasi dana hilang sebesar Rp900 milyar. Untuk satu kasus lain, yaitu perumahan syariah yang mencuat pada akhir tahun 2019, korbannya sekitar 3.600 orang yang sudah menyetorkan dana. Bagaimana fenomena ini harus dijelaskan?
Pertama-tama, kita harus berangkat dari satu prinsip dasar bahwa keputusan untuk melakukan suatu hubungan hukum, misalnya berupa transaksi jual beli, pada hakikatnya merupakan hak keperdataan yang dijamin kebebasannya menurut hukum. Kita menyebutnya sebagai kebebasan berkontrak (partij autonomie). Tidak boleh ada paksaan pada setiap orang untuk terikat atau tidak terikat pada suatu perjanjian keperdataan. Tidak juga boleh ada paksaan dengan siapa seseorang akan membuat perjanjian. Demikian pula, tidak boleh ada paksaan untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian itu. Demikianlah ilmu hukum menuntunnya (kendati kebebasan ini tetap memiliki restriksi dalam konteks-konteks tertentu).
Menurut Sir Henry Maine (1822-1888), seorang sejarawan hukum asal Inggris, wujud hukum yang paling ideal adalah ketika hukum dibuat melalui kebebasan berkontrak ini. Ia menempatkan “kontrak” sebagai tahap kelima atau terakhir dari perjalanan “peradaban” hukum, yang bermula dari status sosial yang didominasi oleh sistem patriarkis, lalu berkembang ke sistem aristokratis, kemudian memasuki era kodifikasi atas hukum-hukum kebiasaan, dan tahap modifikasi atas hukum-hukum tertulis hasil kodifikasi tersebut, sebelum akhirnya ilmu hukum menuntun perjalanan hukum tadi guna menghasilkan format kontrak-kontrak perdata. Intinya, perjalanan hukum sangat sejalan dengan perjalanan peradaban manusia, mulai dari tahap irasionalitas menuju ke tahap rasionalitas.
Tokoh lain, Max Weber (1864-1920) juga pernah mempersoalkan hal yang serupa. Ia membedakan dua tingkatan rasionalitas (rendah-tinggi) yang dihadap-hadapkannya dengan derajat formalitas (rendah-tinggi). Rasionalitas yang rendah ini disebutnya irasionalitas. Pada tingkatan formalitas, bagian yang rendah ini disebutnya material atau substansial. Gambaran pemikiran sosiolog Jerman ini kurang lebih sebagai berikut: Weber merekomendasikan wajah hukum yang rasionalitas-formal. Ia menyatakan bahwa rasionalitas formal ini adalah kondisi yang mengacu pada kalkulasi rasional atas dasar aturan-aturan hukum. Sebagai seorang yang mendalami ilmu ekonomi, Weber memahami kalkulasi tadi sama dengan perhitungan-perhitungan ekonomis, yaitu maksimalisasi profit. Ia berpendapat, sistem hukum modern sudah dibentuk untuk menuntun setiap subjek hukum mampu berpikir rasionalitas-formal tersebut.
Weber merekomendasikan wajah hukum yang rasionalitas-formal. Ia menyatakan bahwa rasionalitas formal ini adalah kondisi yang mengacu pada kalkulasi rasional atas dasar aturan-aturan hukum. Sebagai seorang yang mendalami ilmu ekonomi, Weber memahami kalkulasi tadi sama dengan perhitungan-perhitungan ekonomis, yaitu maksimalisasi profit. Ia berpendapat, sistem hukum modern sudah dibentuk untuk menuntun setiap subjek hukum mampu berpikir rasionalitas-formal tersebut.
Namun,bayangan Weber tidak sepenuhnya tepat. Kadangkala hukum positif yang dibuat oleh penguasa negara tidak cukup merata dalam memberi akses pada kelompok yang termarjinalkan. Kelompok ini berpendapat hukum yang terlalu formalistis itu tidak bisa sepenuhnya bisa diandalkan karena tidak berpihak pada mereka. Hukum tidak bisa dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan yang benar-benar mampu memaksimalkan profit bagi kepentingan mereka. Untuk itulah, kelompok masyarakat seperti ini lalu berusaha mengisi ceruk yang kosog tadi dengan memberi nuansa “substantif” terhadap gaya berpikir yang [seharusnya] rasional itu. Dalam skema Weber di atas, kategori pengambilan keputusan seperti ini masuk pada tingkatan rasionalitas-material.
Jika kita perhatikan dengan saksama, apa yang disebut oleh Weber dengan rasionalitas-material ini tidak lepas dari pandangannya dalam buku “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus). Ia melihat bahwa nilai-nilai agama ternyata bisa sangat mendukung semangat kapitalisme yang rasional. Kesimpulan ini diperoleh setelah ia mengobservasi etos kerja penganut Protestan (Calvinis) di Eropa Utara, yang pada gilirannya mampu memakmurkan masyarakat di sana.
Teori Weber tentang rasionalitas-material ini ternyata tidak bisa kita terapkan pada kasus jual-beli yang disinggung di awal tulisan ini. Agama-agama yang berkembang di Indonesia, tidak semuanya mampu mendorong masyarakatnya untuk menggali sisi etis yang terkandung dalam ajarannya, sehingga dimensi “material” yang disebut oleh Weber tidak mengemuka sebagai semangat dalam memaksimalkan keuntungan bagi para pemeluknya.
Kita dapat melihat strategi marketing yang digunakan para penjual dalam kasus-kasus di atas. Mereka aktif menawarkan produk mereka dengan melibatkan penceramah di majelis-majelis keagamaan. Melalui insinuasi bahwa jual beli konvensional selama ini merugikan umat dan sudah saatnya beralih ke model-model transaksi yang lebih agamis, pemasaran tadi mampu menggaet banyak peminat. Perlu dicatat, gaya marketing seperti ini tentu tidak menjadi ciri khas pada kelompok agama tertentu, melainkan bisa terjadi pada agama mana saja. Persoalannya adalah, rasionalitas yang diklaim oleh Weber tidak terjadi di sini. Masyarakat konsumen tidak dididik untuk membuat perhitungan-perhitungan yang masuk akal bahwa model bisnis seperti itu memang bisa berjalan dan berbuah kenyataan. Tokoh agama yang ikut terlibat memasarkan, biasanya lebih senang mengutip ayat dari kitab suci dalam rangka menjustifikasi tawaran bisnis tersebut daripada ia harus ikut menerangkan alur pikir (rasionalitas) dari bisnis tersebut. Tidak heran ketika ada umat mempertanyakan hal ini, tokoh tadi hanya mampu berdalih bahwa dirinya pun ikut menjadi korban (tertipu).
Satu hal yang menyedihkan adalah bahwa otoritas negara yang berwenang tidak mampu mencegah skandal seperti ini agar tidak meluas dan memakan korban sedemikian banyaknya. Kasus “First Travel” merupakan bukti betapa pemegang otoritas resmi lalai membaca situasi seperti ini. Pelaku yang sekadar membonceng label agamis seperti “syariah” namun nyata-nyata menjalankan usahanya di luar kewajaran dan logika, pasti layak dipertanyakan kebenaran labelisasi tadi.
Dalam kondisi seperti itu, derajat rasionalitas yang dimaksud oleh Weber tidak lagi relevan untuk ditautkan. Patut diduga, tahap yang sebenarnya terindentifikasi dari kasus-kasus yang memuat “janji-janji surgawi” yang berujung pada jatuhnya para korban tadi, berada pada tingkatan irasionalitas-formal, atau bahkan mungkin lebih jauh daripada itu, yaitu irasionalitas-material. Pada tingkatan irasionalitas-formal, masyarakat percaya pada janji-janji yang ditawarkan perusahaan tadi karena yakin bahwa keputusan mereka untuk terikat dalam transaksi ini adalah bagian dari ibadah. Inilah bentuk transaksi yang agamis. Bagi mereka motif ini sudah cukup sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Hadirnya para tokoh agama dan [mungkin] selebritis menambah kepercayaan ini. Demikian juga dengan absennya negara untuk mengawasi, seolah memberi “legitimasi” terhadap semua fenomena tadi.
Kendati kasus-kasus di atas berada dalam ranah keperdataan, sebenarnya kita menyaksikan ada aspek formal hukum yang gagal berfungsi di sini. Beralihnya kasus-kasus ini menjadi perkara pidana bukan jalan keluar satu-satunya. Selama hukum positif kita belum mampu mewadahi kepentingan masyarakat dan menawarkan perlindungan pada transaksi-transaksi hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, selama itu pula masyarakat kita akan cenderung irasional dalam membuat keputusan. Alhasil, kasus-kasus seperti di atas bakal terus berulang. (***)

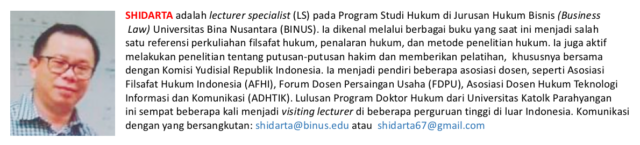
Comments :