BERPEGANG KEPADA ATURAN, HARUSKAH ITU ?
Oleh Agus Riyanto (September 2019)
Tragedi itulah kata untuk menggambarkan apa yang terjadi. Jenazah seorang bocah di Tangerang yang dibopong pamannya, Supriyadi, keluar dari Puskesmas viral di media sosial. Supriyadi mengaku terpaksa membopong jenazah keponakannya, Husein (8), dari Puskesmas agar dapat segera dibawa pulang ke rumahnya di Cikokol, Tangerang, untuk dimakamkan. Peristiwa miris ini terjadi lantaran pihak puskesmas menolak memberikan pelayanan ambulans untuk mengantarkan jenazah yang hanya berjarak kurang dari satu kilometer dari Puskesmas (https://news.detik.com/berita/4680048/viral-jenazah-bocah-di-tangerang-dibopong-paman-dari-puskesmas). Puskesmas yang menolak mengantarkan jenazah sesungguhnya karena aturannya memang melarang telah membunuh daya nalar manusia. Hilangkah nilai-nilai manusiawi dan mengedepankan aturan sebagai dasarnya pembenaran untuk menolak mengantarkanya. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa hal itu terjadi dengan bersikukuh kepada aturan yang dipegangnya ?
Petugas di lapangan seringkali bertindak sangat kaku dan baku di dalam menterjemahkan aturan adalah realitas yang terjadi. Dalam sudut pandang ini benar-benar sajalah, karena mereka berpegang teguh kepada berlakunya standar operasional prosedur (SOP) sebagai dasar pembenarnya. Ketidaktaatan kepada ketentuan yang berlaku dapat berakibat fatal dan bahkan mungkin berakhir dengan hilangnya identitas diri sebagai manusia pekerja dan termasuk sebagai pembangkangan terhadap perintah atasannya. Bias dari kerangka berpikir demikian adalah keseharian bekerja bagaikan robot yang akan selalu patuh pada garis-garis ketentuan yang telah diyakininya. Ketaatan itu seratus persen tanpa dikurangi sedikitpun dan selalu akan berjalan di dalam naungan rel atau koridor yang berlaku atau menjalaninya bagaikan kaca mata kuda. Tidak melihat dan memikirkan kiri dan kanan, tetapi lurus ke depan dengan menggunakan lampu kebenaran sebagai pedoman dasar di dalam melangkah menjalani pekerjaan dan kesehariannya. Tidak ada yang salah memang karena buku panduan dalam aturan yang berlaku ada pedoman dasar berpikir dan dalam bertindaknya. Warna warni kehidupannya hanya dua pilihan yaitu antara hitam atau putih untuk memberikan penilaian dan menjatuhkan putusannya. Tidak ada warna lain yang mungkin dapat dipilihnya. Hitam untuk kesalahan atau ketidakbenaran, sementara putih untuk ketidaksalahan dan kebenaran. Pilihannya menjadi terbatas.
Dengan konsep berpikir di atas jelas betapa normatifnya penegakan aturannya. Penegakan hukum yang berada dalam jebakan dengan tidak ada pilihan untuk merasionalisasi dalam pelaksanaannya. Lebih dari itu akibatnya rasa kemanusian dan toleransi lanjutan sebagai titik lain kelamahan sangat mungkin terjadi. Yang digunakan pelaksana lapangan adalah sebatas apa yang tertera dalam susunan uraian kalimat aturan yang mereka dapat pahami dengan tekstual. Mengharapkan dapat memahami dan kontekstual (makna dalam dibalik kata) membutuhkan energi tambahan untuk mendalaminya. Kendala realitas ini berakar dari tingkat pendidikan, pemahaman tentang penegakan hukum yang substansial dan keenganan untuk berpikir jauh dari keputusan yang telah mereka keluarkan adalah bagian kejadian yang terpotret di lapanagan. Kesemuanya bermula dari kombinasi aturan dan pelaksana lapangan (sebagai penegak hukumnya) yang telah berpikiran (tanpa disarinya) dengan menggunakan positivisme hukum. Hal ini, karena aliran ini berpendapat bahwa hukum itu harus tertulis, sehingga tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Artinya, semua persoalan kehidupan ini harus diatur dengan hukum yang tertulis. Dengan dasar berpikir demikian sesungguhnya pelaku lapangan telah mengakseptasi aliran positivisme hukum sebagai kunci utama darah pembenarannya. Aliran positivisme hukum telah memberikan penghargaan berlebihan-lebihan terhadap kekuasaan yang membentuknya dan menciptakan hukum tertulis dan dengan itu kekuasaan adalah sumber hukum dari kekuasaan adalah hukum itu sendiri. Pedoman inilah yang telah menjadi petunjuk dasar para petugas lapangan sebagaimana yang telah terjadi di Tangerang tersebut. Di desaknya dan ketika dimintakan pertanggung-jawaban mereka akan berputar-putar kepada SOP yang menjadi pegangan sebagai pembelaan dan pembenarannya.
Dengan berpegangan kepada aliran positivisme hukum di atas, maka hal itu menjadikan petugas lapangan di dalam menegakan hukum hanya terbatas menegakkan bunyi teks dari undang-undang saja dan tidak berkehendak menegakkan kebenaran, keadilan dan rasa karsa substansi hukum itu sendiri. Hal ini jika dijalankan sebagai dasar penegakan hukum itu bagaikan menggunakan kaca mata kuda dengan tegak lurus penegakannya. Hal ini berbahaya, karena tidak dapat membedakan kesalahan yang prosedural dan substansial dalam mennyelesaikan penegakan hukum yang dihadapinya. Penegakan hukum hanya berpegang penuh “rule and procedure”-nya saja. Penegakan hukum yang legaslistik akan membuahkan rasa ketidakadilan. Ketidakadilan yang menjauhkan idealisme dan cita-cita pembentuk aturan itu sendiri yang dibentuk demi dan untuk kemaslahatan warga negara masyarakat yang seharusnya dibentenginya. Berpegang teguh kepada aturan itu baik dan tidak ada salahnya, namun apabila di lapangan terjadi perubahan keadaan yang harusnya dilakukan perubahan demi rasa kemanusian (terlebih-lebih soal kematian) gunakanlah konstruksi bepikir yang baru. Tidak haruslah selalu kaku. Hal ini karena dalam pandangan paradigma konstruktivisme, hukum (SOP petugas Puskesmas) itu pada dasarnya adalah merupakan kesepakatan, baik tertulis maupun tidak, yang bersifat relatif dan kontekstual. Artinya, apabila ketentuan itu adalah hukum yang berlaku adalah tidak dapat mengantar jenazah seharusnya dapat dirubahnya dengan memperolehkan menggunakan ambulance untuk jenazah apabila terdapat kesepakatan bersama dengan seluruh pemangku dan juga penanggung-jawab di lapangannya. Terbukanya hal itu dengan menggunakan konstruksi mental (berpikir) baru bahwa ketentuan yang berlaku menjadi harus diubahnya demi dan untuk rasa kemanusian yang dikedepankan.
Melalui pendekatan konstruksivisme, aturan sebagaimana SOP di dalam kasus ini, tidak menjadikannya kaku beku tanpa menghilangkan rasa kemanusian demi keadilan. Hal ini karena dengan kesepakatan dan konsensus bersama, maka persoalan yang dihadapinya akan dapat diselesaikan sesuai dengan konteks dan inti permasalahannya. Tidak selalu haruslah berpegangan dan harga mati dalam menjalankan aturan yang berlaku. Sudah waktunya untuk berpikir progresif untuk dapat menghambat dampak negatif positivisme. Kekhawatiran itu ada, karena penggunaan kaca mata kuda dalam penegakannya hanya dapat melihat penegakan hukum dalam satu arah yaitu rumusan undang-undang secara tekstual normatif tanpa ada kepedulian dan sensitivitas terhadap kondisi lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk rasa kemanusian yang seharusnya juga dimiliki para pelaksana hukum adalah pilihan yang harus mau diterimanya. Penegakan hukum haruslah dengan menempatkan keadilan dan kebenaran di atas aturan. Sebab, jika penegakan hukum yang dibuat hanya berdasarkan konstruksi-konstruksi logis yang ada dalam teks hukum positif formal, maka penegakan hukum hanya menjadi mulutnya UU. Penegakan hukum yang progresif dituntut melepaskan diri dari kungkungan pola berpikir positivistik yang kaku dan tidak membumi sebagaimana yang kita lihat dalam kasus tersebut di atas. Masihkah kita terjebak dalam kolam kesalahan yang selama ini terjadi ? Tidak seharusnya.



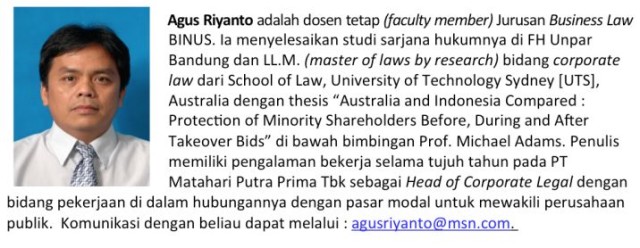
Comments :