CATATAN KECIL UNTUK PERATURAN KPPU NO. 1 TAHUN 2019
Oleh SHIDARTA (Juni 2019)
Beberapa hari lalu, seorang rekan yang menjadi koresponden untuk Policy and Regulatory Report (PaRR) Hong Kong untuk Indonesia menyempatkan diri mewawancarai saya sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penangnan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Wawancara, atau lebih tepatnya, diskusi tersebut, berjalan menarik. Intinya, ada sejumlah catatan yang kemudian dapat diberikan pada peraturan yang mulai berlaku tanggal 4 Februari 2019 tersebut, namun karena keterbatasan tempat, dalam tulisan ini hanya akan disinggung beberapa saja di antaranya. Di sisi lain, mengingat kemungkinan reportase yang dibuat oleh rekan tersebut juga tidak akan tampil utuh, maka ada baiknya cuplikan dari diskusi tadi ditulis ulang dalam artikel pendek agar dapat dijadikan bahan diskusi oleh kalangan lebih luas, terutama bagi para penstudi hukum yang mengambil mata kuliah persaingan usaha.
Ada dua pasal yang dipilih untuk diberikan catatan, yakni Pasal 57 dan Pasal 67. Kita akan membahas kedua persoalan terkait dari kedua pasal ini secara berurutan.
Pasal 57 ini ada dalam satu rangkaian dengan pasal-pasal di atasnya, khususnya mulai dari Pasal 45 sampai dengan 59. Kelompok pasal-pasal ini berbicara tentang alat bukti. Pasal 45 menyebutkan lima alat bukti yang dapat dipakai oleh KPPU, yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat dan/atau dokumen; petunjuk; dan keterangan pelaku usaha. Formulasinya persis mengikuti bunyi Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Seperti halnya rumusan di dalam UU No. 5 Tahun 1999, walaupun kelima alat bukti ini diurutkan di dalam Pasal 45 peraturan ini, juga tidak ada keterangan apakah alat bukti yang disebutkan di urutan pertama lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti di urutan berikutnya. Jika tidak ada keterangan ini, maka asumsinya, semua alat bukti ini sama kekuatannya. Perhatian kita tertuju pada alat bukti pertunjuk. Alat bukti ini menarik karena menekankan pada metode pembuktian dengan alat bukti tidak langsung (indirect evidence), yang dalam putusan-putusan KPPU sudah diterapkan.
Terminologi “petunjuk” sebagai alat bukti sebenarnya lebih dekat ke dalam hukum pidana, karena dalam hukum perdata terminologi yang digunakan adalah “persangkaan”. Intinya, petunjuk adalah alat bukti yang tidak langsung terkait dengan suatu pelanggaran, namun alat bukti ini dapat dipakai sebagai titik tolak guna menyimpulkan tentang adanya perjanjian atau perbuatan yang dilarang atau penyalahgunaan posisi dominan. Jadi, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru apabila alat bukti petunjuk ini ditegaskan kembali dalam peraturan ini karena memang alat bukti seperti itu sudah lama diterima dalam UU N. 5 Tahun 1999, juga dalam hukum acara perdata dan pidana. Hanya saja, masih tetap perlu dicatat bahwa sebagai sebuah petunjuk, alat bukti ini tidak bisa berdiri sendiri. KPPU juga sudah menggunakan ketentuan minimal dua alat bukti minimal untuk memproses suatu perkara dugaan pelanggaran pada tahap penyelidikan (lihat Pasal 21 ayat [2]). Dengan dua alat bukti minimal, berarti harus paling sedikit ada dua jenis alat bukti yang berbeda (tidak boleh diartikan sebagai dua barang bukti berbeda di dalam satu jenis alat bukti).
Alat bukti petunjuk ini antara lain berupa bukti ekonomi. KPPU tentu akan sebisa mungkin mencari perhitungan-perhitungan yang akan menguatkan tuduhan mereka kepada terlapor. Kendati demikian, terlapor tentu juga memiliki data ekonomi internal, dengan barang bukti seperti laporan keuangan atau laporan stok barang, yang bisa digunakan untuk mematahkan data versi KPPU. Walaupun KPPU diberi kewenangan melakukan proses penyelidikan sampai dengan penjatuhan putusan, KPPU tidak boleh menempatkan terlapor pada posisi yang tidak lagi dapat bebas melakukan pembelaan diri. Jadi, bukti ekonomi dari KPPU pasti terbuka untuk dibantah dengan alat bukti ekonomi (tandingan) dari pihak terlapor.
Selain bukti ekonomi ada juga bukti komunikasi. Oleh karena bukti komunikasi inipun adalah petunjuk, maka tentu bukti komunikasi tidak bisa tunggal. Harus ada beberapa bukti yang dapat/patut diduga punya keterkaitan satu dengan lainnya. Sepanjang bukti komunikasi ini bisa dijalin dengan bukti-bukti lain, yang secara logis bisa mengarahkan kepada suatu kesimpulan, maka bukti seperti ini bisa digunakan. Bukti komunikasi ini seharusnya berupa komunikasi antar-pelaku usaha pesaing. Namun, dalam kasus yang baru diputuskan oleh KPPU mengenai empat perusahaan jasa freight container rute Surabaya-Ambon, salah satu bukti yang digunakan adalah komunikasi perusahaan dengan customers tentang kenaikan harga. Jadi, ternyata bukti komunikasi yang dimaksud juga dapat berupa koomunikasi bukan sesama pelaku usaha. Di sini yang ditekankan adalah keruntutan logis yang bisa disusun agar dapat sampai pada kesimpulan tentang adanya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Dengan perkataan lain, harus ada hubungan kausalitas antara komunikasi tadi dengan bukti-bukti lain, yang bermuara pada pelanggaran undang-undang. Jika tidak terlihat jelas hubungan logis yang menggambarkan kausalitas tadi, maka bukti komunikasi tadi terputus (jumping to conclusion), yang tentu tidak dapat dibenarkan dalam penalaran hukum.
Oleh karena alat bukti “petunjuk” ini diambil dari terminologi yang sudah dimunculkan dalam hukum pidana (misal Pasal 184 dan 188 KUHAP), maka menarik juga untuk membandingkannya dengan penerapan bukti petunjuk ini di dalam ranah pidana, agar penggunaannya di dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha menjadi lebih berhati-hati. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupuan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat (2) menyatkaan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi, andaikan KPPU ingin membangun koridor terkait alat bukti petunjuk ini, maka dapat diberi pengertian yang sebangun dengan rumusan KUHAP.
Kemudian, Pasal 67 dari peraturan ini diformulasikan sebagai berikut:
Secara tegas dikatakan, jika terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU (secara sukarela), maka eksekusi dilakukan dengan terlebih dulu meminta penetapan eksekusi di pengadilan negeri. Persoalannya terletak pada ayat (2) dari Pasal 67. Kata-kata “di luar upaya” pada ayat ini mengindikasikan ada langkah-langkah hukum KPPU yang dilakukan tanpa harus menunggu penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Langkah-langkah hukum itu adalah dengan melakukan sita perdata dan/atau penagihan melalui pihak ketiga.
Pembaca peraturan ini boleh jadi akan bertanya: apakah KPPU memiliki aparat untuk melakukan sita perdata ini? Lalu, apakah melakukan penagihan melalui jasa pihak ketiga berarti termasuk menyerahkan urusan penagihan ini kepada para debt-collectors? Tampaknya, langkah-langkah ini agak sulit untuk dapat efektif dilakukan dan kemungkinan juga akan dipertanyakan seberapa jauh dapat diklaim sebagai langkah-langkah hukum (ada legitimasinya menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999). Jika harus menggunakan jasa pihak ketiga, patut diduga bahwa pihak ketiga ini bakal memungut biaya atas jasa penagihan tersebut.
Di luar langkah-langkah tersebut, masih ada lagi tindakan lain yang disebutkan dalam ayat (4). Ayat ini menyebutkan tindakan lain berupa upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak/elektronik, dan pencantuman di daftar hitam pelaku usaha. Jika dicermati, jenis-jenis tindakan lain yang tersusun pada ayat ini tidaklah paralel. TIndakan huruf a dan b seharusnya tergolong tindakan persuasif dan preventif. Lain halnya dengan tindakan huruf c dan d yang seharusnya sudah merupakan tindakan represif karena termasuk kategori sanksi. Boleh jadi, ada argumentasi bahwa tindakan pada huruf a dan b itupun diposisikan sebagai jenis sanksi yang bisa berdiri sendiri (kebetulan peraturan ini tidak menyebutkan jenis-jenis sanksi yang bisa dijatuhkan). Artinya, ada jenis sanksi yang disebut sebagai upaya persuasif dan teguran lisan untuk pelaku usaha yang tingkat pelanggarannya tergolong ringan. Bila demikian yang dimaksudkan, maka pengkategorian sebagai “tindakan lain” di sini menjadi tidak tepat karena mengesankan bahwa tindakan lain di sini sebagai pemberian sanksi tambahan, bukan sanksi pokok. Sanksi tambahan tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa sanksi pokok.
Apa yang disebut sebagai sanksi pokok, seharusnya adalah sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal ini memuat enam kategori sanksi yang disebut sebagai tindakan administratif, yang dapat dijatuhkan oleh KPPU. Keenam jenis tindakan administratif itu adalah: (1) penetapan pembatalan perjanjian; (2) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; (3) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan…; (4) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan; (5) penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau (6) pengenaan denda. Ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 menunjukkan ada tambahan kewenangan komisi dalam menambahkan jenis sanksi baru. Secara materi muatan, hal ini bisa “bermasalah” karena bertabrakan dengan UU No. 5 Tahun 1999, kecuali jika revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 segera diwujudkan. (***)



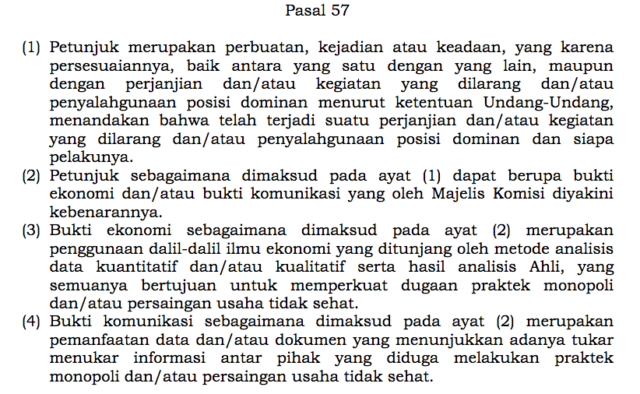
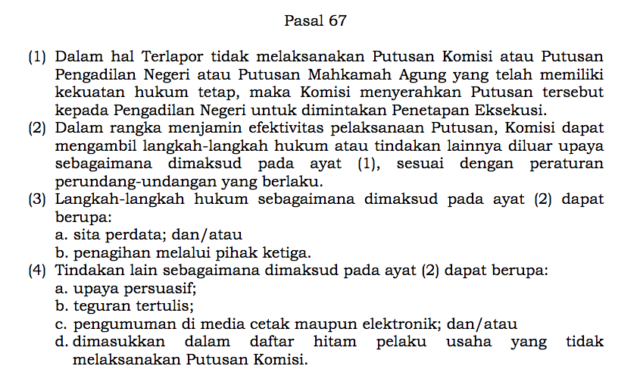

Comments :