KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA PRA DAN PASCA REFORMASI
Oleh REZA ZAKI (Desember 2018)
Setelah Indonesia memasuki masa reformasi, kebijakan pertanian Indonesia juga banyak berubah. Salah satu penyebabnya adalah adanya desentralisasi, pemerintah pusat tidak lagi memegang penuh kendali atas daerah. Sebelumnya, pada tahun 1996 Indonesia juga ikut dalam perjanjian pertanian (agreement on agriculture) yang dicetuskan oleh WTO sehingga kebijakan pertanian Indonesia mulai mencoba searah jalan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut salah satunya adalah terkait dengan pengurangan domestic support untuk pertanian. imbas dari krisis yang terjadi pada tahun 1998 juga membuat Indonesia mengurangi berbagai bentuk subsidi terhadap sektor pertanian, kebijakan ini bertahan hingga pertengahan dekade awal tahun 2000-an. Pada periode sekarang ini isu ketahanana pangan kembali menjadi isu yang terus diperbincangkan, pemerintah hampir setiap tahun mencanangkan untuk kembali bisa mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, berbagai bentuk bantuan kembali giat ditingkatkan salah satunya adalah subsdi untuk input pertaian seperti pupuk, benih, dan alsintan (alat mesin pertanian). selain itu pemerintah lewat Bulog juga aktif menjaga harga lewat kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) dimana program ini dimaksudkan untuk melindungi petani ketika harga jatuh di pasaran.
Data dari OECD menunjukkan bahwa setelah tahun 2000 PSE Indonesia terus naik. Meskipun sempat turun pada tahun 2008, akan tetapi turunnya ini disebabkan karena adanya krisis finasial dunia dan kenaikan harga BBM yang tinggi sehingga bantuan terhadap sektor pertanian menjadi terganggu. Pada tahun 2000 PSE Indonesia sebesar $1,7 miliar, kemudian pada tahun 2015 menjadi $35,96 miliar atau naik hampir 20 kali lipat. Kenaikan paling stabil terjadi dalam periode 2011 – 2015, dimana pada periode ini nilai PSE Indonesia naik rata-rata 17% per tahun. Kenaikan ini juga terlihat dari naiknya anggaran untuk subsidi input pertanian seperti pupuk dan benih setiap tahun.
Untuk data AMS sendiri, notifikasi terakhir yang diberikan oleh Indonesia kepada WTO tercatat pada tahun 2013 mengenai besaran domestic support Indonesia untuk tahun 2001-2003 dan 2009-2011. pada notifikasi tersebut Indonesia hanya mencantumkan domestic support dengan kategori yang masuk ke dalam green box dan program pengembangan pertanian, sehingga tidak terdapat data untuk domestic support Indonesia yang masuk kedalam kategori amber box. Indonesia sendiri mencantumkan program subsidi input sepert pupuk dan benih sebagai bagian dari program pengembangan pertanian bukan sebagai sesuatu yang bisa mendistorsi pasar sehingga tidak masuk kedalam amber box. Hal ini merupakan suatu keanehan karena Indonesia sendiri memiliki program dukungan harga yang dinamakan harga pembelian pemerintah yang meskipun hal tersebut dilakukan oleh Bulog akan tetapi tetap saja sama dengan pemerintah yang turun tangan didalamnya[1]. Setelah dilakuan perhitungan untuk periode 2005-2015 dengan menggunakan berbagai sumber data yang ada untuk komoditi beras. Sharma (2016) menemukan bahwa pada tahun 2015 besaran AMS beras adalah sebesar Rp 257,68 trilun (7,04% dari total produksi) sehingga bisa dikategorikan tidak melewati de minimis (level de minimis: 10%) sebagai berikut:
Tabel 3.5. AMS Indonesia untuk Beras
| Product specific support Indonesia (Beras) | ||
| Tahun | Product specific support (juta) | %tase terhadap nilai produksi (%) |
| 2005 | Rp 2.663.858 | 2,73 |
| 2006 | Rp 3.357.484 | 2,68 |
| 2007 | Rp 4.485.123 | 3,03 |
| 2008 | Rp 8.196.460 | 4,98 |
| 2009 | Rp 11.435.076 | 6,83 |
| 2010 | Rp 7.229.800 | 4,02 |
| 2011 | Rp 6.220.632 | 3,37 |
| 2012 | Rp 19.020.517 | 7,88 |
| 2013 | Rp 17.922.927 | 7,48 |
| 2014 | Rp 12.093.210 | 5,15 |
| 2015 | Rp 18.137.600 | 7,04 |
Data di atas memperlihatkan bahwa domestic support yang bisa dikategorikan kedalam amber box untuk Indonesia tidak sekalipun melewati level de minimis nya sehingga meskipun tidak mencantumkannya dalam notifikasi ke WTO Indonesia belum melanggar kesepakatan yang ada.
Tren untuk keempat negara yang ada dalam kajian ini umumnya memiliki pola kebijakan pertanian yang hampir seragam. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya beberapa kesamaan diantara keempatnya yaitu sama-sama memiliki jumlah penduduk yang banyak, tergolong negara berkembang, dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. pola yang terlihat adalah dari awal tahun 2000an hingga pertengahan bantuan terhadap sektor pertanian masih tergolong rendah, akan tetapi semakin mendekati dekade kedua tahun 2000 hingga saat ini setiap negara tersebut terus meningkatkan intervensi dengan memberikan bantuan lebih banyak kepada sektor pertaniannya. Alasan yang paling banyak dikemukan kemudian adalah untuk menjaga ketahanan pangan dinegara tersebut. jumlah penduduk yang banyak memang membuat keempat negara tersebut harus memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam hal menjaga ketahanan pangannya.
Gambar 3.4. PSE China, Brazil, dan Indonesia
Sedangkan untuk mengenai komitmen keempat negara tersebut terhadap perjanjian pertanian (agreement on agriculture) WTO bisa dibilang berjalan baik diawal tahun 2000an. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini keempat negara tersebut menjadi lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada sektor pertaniannya. Meskipun dalam notifikasi yang dilaporkan kepada WTO menunjukan tidak adanya pelanggaran, akan tetapi dalam beberapa kajian yang dilakukan justru ditemukan bahwa negara-negara tersebut telah melanggar batas kesepkatan yang ada. Oleh karena itulah, China dan India akhir-akhir ini menjadi giat untuk dilakukan negosiasi ulang mengenai AoA, terutama yang terkait dengan batas AMS atau level de minimis nya. (***)
REFERENSI:
[1] Sachin Kumar Sharma, The WTO and Food Security: Implications for Developing Countries. (New Delhi, Centre for WTO Studies, 2016), hlm 90.




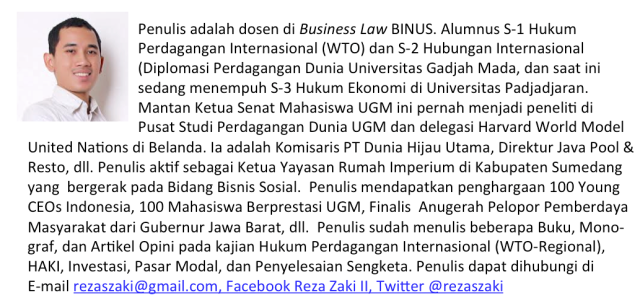
Comments :