DELIK MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR
Oleh: AHMAD SOFIAN (November 2018)
Tulisan ini merupakan bagian dari keterangan ahli yang saya sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji material (judicial review) Pasal 122 L Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan No. 34/PUU-XVI/2018.
Perkembangan delik-delik dalam hukum pidana telah mengalami pergeseran yang cukup pesat. Secara konvensional delik atau tindak pidana digolongkan menjadi tindak pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, tindak pidana terhadap jabatan, tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, tindak pidana terhadap kesusilaan dan tindak pidana terhadap harta benda. Namun dalam perkembangan terbaru, muncul delik yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP dan diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Pengaturan delik-delik pidana yang berada di luar KUHP tentu saja sejalan dengan perkembangan tindak pidana sendiri. Namun demikian pengaturan tindak pidana yang berada di luar KUHP harus senapas dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia, tidak melanggar konstitusi negara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsis (asas) hukum pidana serta memiliki landasan teori/doktrin yang kuat.
Fokus utama pembahasan dalam artikel ini adalah Pasal 122 huruf L Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20l8 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal 122 huruf L menjelaskan bahwa : Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas … “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR”. Dengan adanya aturan ini Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melaporkan perseorangan, kelompok atau badan hukum yang mengkritisi setiap kebijakan dan kinerja anggota DPR.
Unsur-Unsur Pasal dan Tafsir
Pasal 122 huruf L memiliki beberapa unsur penting yaitu :
- Mahkamah Kehormaan Dewan
- Mengambil langkah hukum/langkah lain
- Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum
- Merendahkan kehormatan
- DPR dan Anggora DPR
Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan dari bunyi Pasal 122 huruf L. Dapat ditafsirkan bahwa MKD memiliki kewenangan melakukan langkah hukum/langkah lain. Langkah hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak begitu jelas, sehingga menjadi multi tafsir. Jika mengacu pada pasal 121 huruf A, MKD memiliki kewenangan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Tentu saja yang dimaksudkan dalam Pasal 121 huruf A ditujukan kepada anggota DPR RI yang melanggar kode etik atau norma hukum, artinya berlaku dilingkungan internal lembaga DPR RI.
Dengan demikian ketika MKD melakukan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, menjadi sangat rancu dan bertentangan dengan hakekat pasal 121 huruf A. Karena langkah hukum/langkah lain itu tetap ditujukan kepada anggota DPR RI. Secara umum, langkah hukum merupakan perbuatan untuk mengajukan seseorang yang diduga melanggar hukum (perbuatan melawan hukum) ke muka pengadilan atau melaporkan seseorang ke penegak hukum. Sementara langkah lain itu sendiri sangat sulit didefinisikan karena tidak ada panduan yang digunakan untuk menafsirkannya, kalaupun dapat ditafsirkan maka perbuatan tersebut di luar prosedur hukum formal yang ada.
Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa merendahkan martabat DPR atau anggoa DPR RI. Dengan demikian subjek hukum ini dapat digugat atau dilaporkan ke penegak hukum jika merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Maka rakyat akan berhadapan dengan wakil rakyat di pengadilan. Atau rakyat yang memilih anggota DPR dilaporkan oleh anggota DPR yang telah memilihnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat kabur dan inkonstitusional karena harusnya anggota DPR yang mewakili kepentingan rakyatnya bukan malah mengkriminalkan rakyat yang telah memilihnya. Kondisi ini tidak sejalan dengan makna negara hukum, yang melindungi segenap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusionalnya.
UU MD3 tidak memberikan definisi atau tafsir terhadap pemaknaan atas delik “merendahkan kehormatan”. Oleh karena itu maka tafsirnya dapat merujuk kepada jurisprudensi dan doktrin (karena keduanya sumber hukum pidana selain undang-undang). Banyak doktrin yang memberikan tafsir terhadap “merendahkan kehormatan” secara berbeda-beda. Beberapa ilmuwah hukum pidana seperti E. Utrecht, van Bemmelen, Moeljatno, Roeslan Saleh, Adami Chazawi memberikan tafsir terhadap merendahkan kehormatan yang bisa diidentikkan dengan “menyerang kehormatan” yaitu :
“Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.”
Jika kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka kehormatan dapat diartikan sebagai harga diri atau nama baik. Ukuran terhadap “harga diri” dan “nama baik” sangatlah abstrak sehingga akan sangat berpotensi besar ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum. Karena tafsir yang sangat ekstentif, maka berpotensi besar untuk digunakan pada perbuatan-perbuatan yang dinilai mengganggu “kepentingan” DPR. Aspek lainnya adalah “harga diri” dan “nama baik” tidak melekat pada kelembagaan seperti DPR, tetapi lebih ditujukan pada perseorangan atau sekelompok orang, karena itu tidak tepat delik “merendahkan DPR atau anggota DPR” sebagai tindak pidana”.
Sebagaimana uraian saya di atas “merendahkan martabat anggota DPR” merupakan delik yang dapat ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum, karena undang-undang tidak memberikan batasan atau interpretasi atas unsur “merendahkan”, unsur “kehormatan”. Oleh karena itu, dua unsur ini akan sangat mudah ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum. Sulit dibedakan antara perbuatan “merendahkan”, “mengkritik”, “mengeluh”, “menyampaikan pendapat”. Perbuatan ini dalam konteks hukum pidana sangat sulit dibedakan dan sangat sulit ditafsirkan. Kalaupun dijadikan rumusan delik maka rumusannya ke delik materiil atau tidak dimasukkan dalam ranah pidana namun ranah perdata. Meskipun dirumuskan secara materril atau dimasukkan dalam ranah perdata, subjeknya tetap harus orang perorangan bukan lembaga negara/lembaga kekuasaan.
Dalam doktrin hukum pidana “kehormatan” dapat dimiliki oleh orang per orang, bukan kelembagaan apalagi sebuah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Sulit menakar “kehormatan” pada lembaga seperti DPR karena salah satu ruang lingkup tugasnya adalah menampung “pendapat” rapat. Cara-cara memberikan pendapat bisa dalam bentuk kritik, saran, atau cara-cara yang lain, karena beragamnya pendidikan, suku, agama dari rakyat yang diwakilinya. Karena itu, keistimewaan ini sebenarnya tidak memiliki landasan dan akar asas/teori/doktrin yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai norma hukum pidana.
Delik Verbal
Doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam hukum pidana, sedikit sekali ulasan tentang delik verbal, atau delik yang diucapkan dengan kata-kata atau perkataan. Dalam beberapa literatur, landasan teori tentang masalah ini juga tidak banyak dibahas. Secara umum, delik verbal merupakan perbuatan dengan lisan yang mengandung unsur ketercelaan. Perbuatan dengan lisan ini dapat ditujukan kepada seseorang, sekelompok orang, sekelompok etnis, agama, suku bahkan dapat juga ditujukan kepada korporasi dan sebuah negara/penguasa atau badan negara. Perkataan tersebut bisa mengandung umpatan, caci maki, merendahkan, meremehkan atau bahkan mengungkap sesuatu yang dinilai sebagai aib. Oleh karena terlalu abstraknya objek yang menjadi perbuatan yang terlarang tersebut, maka dibanyak negara delik-delik verbal ini dirumuskan dengan cara materiil dan tidak dirumuskan secara formil.
Dalam banyak literatur hukum pidana, delik materiil adalah sesuatu perbuatan menjadi delik ketika akibat yang terlarang dari perbuatan itu muncul. Artinya, ketika akibat terlarang tersebut tidak timbul meskipun perbuatan sudah dilakukan, maka perbuatan itu belum dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Misalnya, pembunuhan, jika korban belum meninggal dunia, maka perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai delik pembunuhan sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana untuk delik pembunuhan tersebut. Sementara itu, delik formil adalah delik yang tidak menunggu akibatnya terjadi, begitu delik tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.
Namun demikian, di beberapa negara lain, delik verbal ini pun dikelompokkan dalam dua bentuk, pertama delik yang ditujukan pada orang per orang/korporasi dan delik yang ditujukan pada sekelompok kaum tertentu. Untuk delik yang ditujukan kepada orang per orang/korporasi maka dirumuskan dengan cara materiil namun jika ditujukan kepada kaum tertentu maka dirumuskan secara formil. Alasan yang menjadi pertimbangan kenapa ada dua model perumusan delik verbal ini disebabkan karena korban yang menjadi target delik tersebut jumlahya besar dalam kaum tertentu, atau kelompok etnis atau kelompok agama tertentu yang dapat menimbulkan kegaduhan atau gangguan ketertiban jika delik tersebut dirumuskan secara materiil.
Dalam hukum pidana di Indonesia, perumusan delik verbal ini mengikuti teori yang kedua, sehingga delik verbal tidak hanya dijumpai dalam Bab XVI KUHP tetapi juga menyebar pada pada pasal-pasal lain di KUHP. Beberapa perbuatan yang masuk dalam delik verbal namun dirumuskan secara formil misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHP tentang pernyataan permusuhan kepada pemerintah (pasal ini akhirnya dicabut oleh MK dalam putusan No. No. 6/ PUU-V/2007) yang bersamaan pencabutannya dengan Pasal 155 KUHP. Selain itu delik verbal lain yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 156 (delik pernyataan permusuhan pada satu golongan tertentu) dan Pasal 156a (delik penodaan agama). Delik-delik ini dimasukkan dalam sub judul “kejahatan terhadap ketertiban umum”. Demikian Pasal 207-208 KUHP tentang kejahatan pada penguasa umum.
Pasal 207 KUHP harusnya juga termasuk pasal yang diminta pembatalannya di Mahkamh Konstitusi, karena pasal ini dirumuskan untuk melindungi “penguasa” dan “badan umum” sebagai alat kekuasaan pada pemerintahan koloni Belanda. Oleh karena itu delik “menghina” tidak tepat ditambalkan atau dilekatkan kepada “penguasa” secara kelembagaan maupun secara perorangan. Delik ini muncul sebelum lahirnya kebebasan menyampaikan pendapat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh penguasa. Catatan saya, Pasal 207 KUHP sudah “mati suri”, karena sejak reformasi pasal ini tidak pernah ditemukan dalam yuriprudensi. Oleh karena itu, dengan mamasukkan Pasal 122 huruf L UU MD3, seolah olah akan menghidupkan kembali pasal yang telah lama mati suri. Antara Pasal 207 KUHP dan Pasal 122 huruf L UU MD3 memiliki keterkaitan, yaitu Pasal 207 KUHP adalah lex generalis sementara Pasal 122 huruf L UU MD3 adalah lex specialis.
Delik-delik verbal (termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik) di banyak negara sudah dihapuskan sebagai delik pidana, karena akan menimbulkan rasa takut dalam menyampaikan pendapat, karena itu di banyak negara perbuatan seperti ini dimasukkan dalam ranah privat (perdata). Oleh karena itu, memasukkan delik verbal dalam Pasal 122 huruf L UU MD3 sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam perkembangan hukum pidana kontemporer. Malah memasukkan delik verbal yang dimaksudkan melindungi penguasa/parlemen membuat hukum pidana Indonesia mengalami kemunduran karena tidak mengikuti trend doktrin hukum pidana saat ini.
Kewenangan MKD
Dengan perumusan pasal ini, jika merujuk pada asas legalitas, maka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat melaporkan subjek delik yaitu orang perorang, kelompok orang termasuk korporasi ke ranah pidana jika unsur-unsur dalam norma ini dilanggar. Namun demikian, jika dilihat dari subjek deliknya, maka sepatutnya yang melakukan pelaporan adalah anggota DPR yang mengalami direndahkan martabatnya bukan malah diwakili oleh MKD. Dalam doktrin hukum pidana, setiap orang yang menjadi korban tindak pidana maka orang tersebut punya hak untuk melaporkannya atau oleh kuasanya. Artinya hukum pidana memiliki relasi dengan subjek hukumnya atas dugaan terjadinya delik pidana pada subjek tersebut. Kehadiran MKD untuk mewakili kepentingan korban, tidak memiliki landasan doktrin yang cukup kuat. Bagaimana menjelaskan relasi antara anggota DPR yang menjadi korban tindak pidana dengan kehadiran MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap orang/perseorangan/badan hukum yang merendahkan martabat anggota DPR RI.
Dalam konteks ini, dengan kewenangan yang diberikan oleh UU MD3 terhadap MKD, maka berpotensi timbulnya konflik kepentingan pada penegak hukum. Bahkan penegak hukum berpotensi akan kehilangan objektivitasnya dalam menilai perbuatan yang dilaporkan oleh MKD atas dugaan terjadinya delik yang merendahkan martabat anggota DPR RI. Sebagaimana diketahui DPR RI adalah salah satu lembaga yang melakukan fit and proper test terhadap KAPOLRI, karena itu, Polri (sebagai salah penegak hukum) berpotensi “diharuskan” oleh MKD untuk memeriksa dugaan tindak pidana tersebut, dan tentu saja objektivitas Polri akan diragukan karena adanya kemungkinan terjadinya “tekanan” terhadap Polri.
Kesimpulan
Pasal 122 huruf L UU MD3, tidak memiliki landasan doktrin dalam hukum pidana terutama ketika dikaitkan dengan subjek delik dan perbuatan “merendahkan kehormatan”, berpotensi untuk diinterpretasikan secara subjektif oleh penegak hukum. Delik ini digolongkan sebagai delik verbal sehingga dibanyak negara yang tidak lagi dimasukkan dalam ranah hukum pidana karena merupakan konflik antara perseorangan dengan perseorangan bukan konflik antara perseorangan dengan lembaga negara/lembaga kekuasaan. Dengan argumentasi ini maka Pasal 122 L seharusnya dikeluarkan dalam UU MD3, karena sangat berpotensi dilanggarnya hak-hak konstitusional warga negara dalam bentuk kriminalisasi atas setiap ucapan, perkataan, kritik, yang ditafsirkan sebagai perbuatan “merendahkan kehormatan” DPR atau anggota DPR. (***)



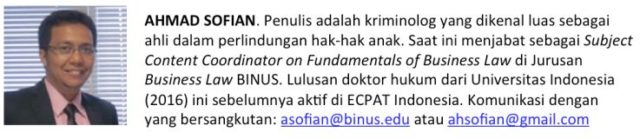
Comments :