PENGAKUAN NEGARA TERHADAP AGAMA LELUHUR/LOKAL
Oleh ERNA RATNANINGSIH (Agustus 2017)
Agama leluhur/lokal memiliki karakteristik khusus yang didasarkan pada fakta empiris bahwa jauh sebelum agama-agama yang disebutkan di atas serta agama dari luar Indonesia masuk lewat penyebaran para misionaris, leluhur atau masyarakat kuno yang telah mewariskan ajaran tuntutan keselamatan hidup dan spiritualitas yang dapat didefinisikan sebagai agama. Paling tidak berdasarkan ketentuan normatif dalam konteks hak asasi manusia, masyarakat yang mewarisi nilai-nilai adat leluhurnya itulah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat, karena dalam tata kehidupan sosialnya baik dalam tata upacara kelahiran, perkawinan dan kematian masih menggunakan tuntunan adat dan kebijaksanaan para leluhurnya.
Agama-agama luluhur/lokal yang masih hidup di Indonesia antara lain Parmalim di Sumatra Utara, Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Jawa Kawitan di Jawa Tengah, Tonaas Walian di Sulawesi Utara, Tolotang di Sulawesi Selatan, Marapu dan Boti di Nusa Tenggara, Naurus di Pulau Seram Maluku dan lainnya sebagainya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengkategorikan agama-agama tersebut di atas sebagai “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”. Akan tetapi, layaknya nasib agama-agama di luar 6 (enam) agama di atas, agama leluhur/lokal juga mengalami ketertindasan yang sama. Beberapa peraturan perundang-undangan menegaskan penindasan terhadap agama leluhur/lokal atau kepercayaan tersebut, di antaranya:
- Penetapan Pemerintah tanggal 3 Januari 1946 No. I/SO, yang menandai berdirinya Departemen Agama;
- Pembentukan Panitia interdeparmental PAKEM pada 1 Agustus 1954;
- PAKEM menjadi institusi legal dengan adanya UU no. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan RI;
- Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama;
- Instruksi Menteri Agama RI No. 4 tahun 1978 yang menetapkan bahwa aliran kepercayaan adalah bukan agama. Dan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha;
- Surat Edaran menteri Dalam Negeri RI bernomor 477/74054 tentang Petunjuk pengisian kolom Agama pada lampiran SK Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975. Dalam Surat Edaran ini dikatakan bahwa dalam mengisi formulir model 1 s.d. 7 dan formulir model A dan B tentang izin perkawinan, berkaitan dengan kolom agama, maka bagi mereka yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah seperti antara lain penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dan lain-lain maka pada kolom agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar atau (–). Ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran itu: Kata “kepercayaan” di samping kata “Agama” pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja;
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN; Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah kepada pembentukan agama baru;
- Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa pada Tanggal 28 Desember 1979.
Akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas banyak pelanggaran hak yang terjadi terhadap kelompok agama lokal. Sebut saja, kasus pendirian rumah ibadah bagi warga Parmalim Bale Parsaktian pada tahun 2005, di mana terjadi penolakan warga jemaat HKBP pimpinan Pdt. AHM Simanjuntak, hingga kemudian Pemerintah Kelurahan beserta Polsekta Medan Area memberikan somasi kepada Sdr. Ir. Maruli H. Sirait selaku Ketua Pengurus Aliran Kepercayaan Permalim dan menolak segala bentuk aktivitas keperayaan dan peribadatannya.[1] Lalu, kasus Yeti Riana Rahmadani, seorang siswi sekolah menengah atas di Bekasi, Jawa Barat, yang terpaksa memilih agama Islam untuk mata pelajaran agama di sekolahnya. Menurut Yeti, dia tak menghadapi kendala apapun Saya mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah, tapi kepercayaan saya adalah kapribaden.[2]
Hal yang sama juga dialami oleh Dewi Kanti, yang merepresentasikan nasib ketertindasannya akibat sikap dan perlakuan negara terhadap Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Dewi Kanti, seorang Penghayat Agama leluhur/lokal, yang disebut Kepercayaan Sunda Wiwitan yang menghayati spiritual leluhur Sunda Wiwitan di Desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat menceritakan jatuh bangun perjuangannya berupaya bertahan hidup dengan keyakinannya dan berperan sebagai benteng pertahanan terakhir pelestari Agama lokal di tatar Sunda Parahyangan.[3] Menurut Dewi, terminologi yang digunakan negara bagi para penghayat agama leluhur Nusantara dikategorikan sebagai “Kepercayaan” menjadi dasar pendikotomian antara agama dan kepercayaan, bahkan menjadi awal pengkerdilan terhadap nilai-nilai spiritual leluhur Nusantara.
Dalam pengalaman komunitas Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, upaya kriminalisasi dan stigma kerap di alami. Pada tahun 1964 dengan suhu politik yang memanas, beberapa pengantin dikriminalkan karena dianggap perkawinan dengan tata cara adat adalah perkawinan liar, dan untuk menyelamatkan dari tekanan dan kriminalisasi, sesepuh adat Kepercayaan Sunda Wiwitan mendapat petunjuk dari para leluhur untuk berteduh “di bawah cemara putih” bahasa simbol yang kami gunakan untuk memilih menghindari pertumpahan darah atas stigma yang dilekatkan. Periode yang cukup fenomenal sebagai tonggak sejarah upaya bertahan hidup dan menyelamatkan generasi serta menyelamatkan tradisi diantara derasnya gelombang besar. Cemara putih diidentikkan sebagai agama Kristen atau Katholik. Stigmatisasi dan kriminalisasi pada perkawinan adat sebenarnya telah terjadi sejak zaman penjajahan Jepang yang saat itu turut membidani lahirnya Shumumbu co (KUA). Jepang melarang semua kegiatan komunitas adat dan itu untuk menarik simpati dari kelompok mayoritas muslim. Dewi Kanti melanjutkan, bahwa Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan menghadapi tuduhan bahwa Kepercayaan Sunda Wiwitan sesat. Bahkan dianggap sebagai komunitas “Islam Murtad, katolik batal dan Sunda nanggung”.[4]
Paparan di atas menunjukkan inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Di dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, UU tentang HAM dan UU tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik memberikan jaminan kebebasan beragama warga negara. Namun di sisi lain peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No.1/PNPS/1965 yang dibuat pada masa demokrasi terpimpin yang sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi masih berlaku dan diikuti dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. UU ini telah diajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Namun, MK menolak permohonan para pemohon judicial review UU No. 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama, sehingga satu-satunya jalan untuk menjamin kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai undang-undang turunannya menjadi tidak berjalan. Dengan demikian, secara normatif, hambatan negara dalam menjamin kebebasan beragama disebabkan oleh inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang ada. (***)
REFERENSI:
[1] Pendirian rumah ibadah Parmalim Bale Parsaktian di atas tanah seluas 1591 meter persegi ini hasil wakaf dari M. Mulya Sirait melalui surat bertanggal 21 Mei 1995, ditolak oleh warga yang sebagian besar dari HKBP pimpinan Pdt. AHM Simanjuntakdengan alasan (1) “warga yang bermukim di sekitar gang Anda Ujung dan gang Satahi adalah sebagian besar Jemaat HKBP Air Bersih dan penganut agama Kristen”; (2) “bahwa rencana pembangunan rumah Parsaktian Parmalim sangat berdekatan dengan gereja HKBP (20 meter) yang diyakini akan sangat memengaruhi praktik kehidupan bergereja”; (3) “karena ajaran Parmalim sangat bertolak belakang dengan ajaran ke-Kristenan”. Lurah Binjai juga memposisikan ajaran Parmalim sebagai aliran yang liar dan menegasikan keberadaan Parmalim sebagai komunitas yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara. Camat pun melaporkan bahwa “Aparat Pemerintah Kelurahan beserta Polsekta Medan Area memberikan somasi kepada Sdr. Ir. Maruli H. Sirait selaku Ketua Pengurus Aliran Kepercayaan Permalim “Untuk tidak mengadakan kegiatan yang berbau aliran kepercayaan Permalim di Air Bersih Ujung”. Baca, M. Uzair Fauzan, “Berebut Kapling untuk Tuhan:..” dalam Mashudi Noorsalim, dkk. (ed), Hak Minoritas, hal. 134). Surat Camat, disertai dengan ancaman: “tindakan tegas akan diambil sesuai hukum dan peraturan yang berlaku bila komunitas Parmalim meneruskan kegiatan kepercayaannya” sehingga dianggap sebagai pengacau keamanan dan peresah masyarakat. (hal. 136).
[2] BBC Indonesia – Laporan Khusus Hak-hak Sipil yang terabaikan, pada tautan: http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/, pada tanggal 1 Juli 2017.
[3] Dewi Kanti, “Posisi masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Leluhur/Penghayat Kepercayaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, pada tautan http://elsaonline.com/posisi-masyarakat-hukum-adat-penganut-agama-luluhurpenghayat-kepercayaan-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/, tanggal 1 Juli 2017.
[4] Baca, Budi Susanto, SJ, (ed) “Sisi Senyap Politik Bising”, Kebebasan Beragama, Kanisius, Jakarta, 2007.
BACA JUGA TAUTAN BERIKUT:
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13590#.WYoJyaNh22w
http://business-law.binus.ac.id/2017/03/16/hak-mengekspresikan-keyakinan-dalam-dokumen-kependudukan/



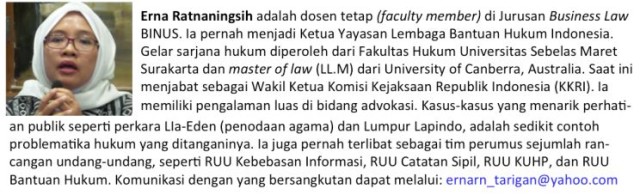
Comments :