SEKALI LAGI, TENTANG KEADILAN
Oleh SHIDARTA (Mei 2017)
Ketika kasus hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah menggelinding di pengadilan, sejumlah politisi berceloteh. “Kami akan mengawal terus kasus ini agar hukum tidak sampai mengabaikan rasa keadilan masyarakat banyak,” demikian suara yang diutarakan oleh politisi yang kontra-Ahok. Itulah sebabnya, politisi ini dan pendukungnya merasa layak bergembira menyambut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum sang gubernur mendekam dua tahun di penjara. Beberapa di antara mereka bahkan merasa perlu merayakan dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas musibah yang menimpa si gubernur. “Selamat, Ahok dipenjara,” tulis mereka di salah satu foto yang menjadi viral di media sosial. Sebaliknya, ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari sejumlah belahan dunia bereaksi sebaliknya. Mereka merespons dengan cara berkirim bunga dukacita, bernyanyi lagu-lagu perjuangan, dan/atau menyalakan lilin, bersimpati pada nasib Ahok dan menganggap hukuman itu sangat tidak adil bagi seseorang yang telah berjuang demi kemajuan ibukota negaranya.
Mana di antara dua reaksi di atas yang mewakili keadilan kita semua? Lalu, apakah dan di manakah keadilan itu? Apakah keadilan sama dengan kebenaran?
Kasus yang menimpa Gubernur DKI tersebut lebih didudukkan di sini sebagai pemicu untuk diangkatnya kembali isu keadilan di dalam tulisan singkat ini, yakni sebuah isu sinoptis yang abadi di dalam diskursus filsafat hukum. Oleh sebab pertanyaan seperti ini bersifat abadi, maka tulisan ini jelas tidak berpretensi bakal mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Cukuplah kiranya ia berguna untuk dijadikan bahan renungan bersama.
Keadilan dan Kebenaran
Apakah keadilan sama dengan kebenaran? Pertanyaan ini sekilas terkesan mudah dijawab, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian. Jawaban standar adalah bahwa keadilan berfokus pada substansi, sementara kebenaran berkorelasi dengan legitimasi formal (harap bedakan dengan legitimasi sosiologis dan legitimasi etis). Kebenaran adalah soal keabsahan penalaran, dengan kognisi sebagai modalitas utamanya. Isu kebenaran berbeda dengan isu keadilan yang memerlukan pengolahan intuitif, sehingga urusan keadilan tak lagi sekadar benar atau salah, tetapi pantas dan tidak pantas.
Repotnya, jawaban standar tak selamanya mampu menjadi sandaran. Ketika orang berbicara tentang keadilan, orang ingin sekaligus berbicara tentang kebenaran. Adil itulah yang benar, namun sebaliknya yang benar belum tentu adil. Tesis ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan keadilan, maka kebenaran lebih berpeluang untuk disepakati karena berada di ranah rasio. Muncul adigium bahwa kebenaran itu tidak berpihak, dalam arti ia seharusnya bisa diterima semua pihak sepanjang mereka mau berpikir rasional. Keadilan rupanya tidak demikian. Keadilan adalah optik yang sejak awal sudah berpihak. Wacana keadilan muncul pada saat orang merasakan ketidakadilan dari sudut pandang para korban ketidakadilan itu. Jadi, adil dan tidak adil tidak pernah dilihat dari sisi-sisi berbeda secara sejajar dan sebanding. Ketika seorang penguasa, misalnya, memindahkan para penghuni rumah-rumah yang dibangun tanpa alas hak di bantaran sungai, tindakan ini dipandang tidak adil dari kaca mata para penghuni, serasional apapun alasannya. Untuk itu, kata “memindahkan” akan lebih dramatis jika diganti dengan kata “menggusur”.
Kendati demikian tetap saja ada orang yang bersikeras bahwa keadilan itu suatu nilai yang universal, berlaku bagi siapapun, kapanpun, dan di manapun. Perspektif ini bisa saja dibantah dengan menunjukkan pandangan alternatif tentang keadilan partikular, atau bahkan personal. Mari kita cermati perspektif tersebut secara lebih dekat.
Keadilan sebagai nilai universal
Jika kita memandang keadilan sebagai nilai universal, maka konsekuensinya kita harus meyakini ada tolok ukur yang sama tentang adil dan tidak adil bagi semua orang, semua bangsa, dalam segala zaman dan keadaan. Segera kita dapat menyadari bahwa universalitas demikian hanyalah asumsi yang tidak selalu klop dengan kenyataan. Karena ada asumsi tersebut, maka sekaligus diyakini pula bahwa keadilan itu suatu realitas yang objektif. Sebagai contoh, tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (membunuh) adalah perilaku tercela yang layak untuk dikecam sampai kapanpun dalam masyarakat beradab di manapun. Oleh sebab itu, setiap kali terjadi pembunuhan, maka negara harus bertindak menghentikan dan menjamin perbuatan itu tidak akan terulang lagi. Negara yang menjalankan tugas ini adalah negara yang bertanggung jawab menegakkan keadilan.
Jika pembicaraan tentang keadilan itu hanya sebatas pada isu untuk wajib menghormati nyawa seseorang agar tidak dirampas secara semena-mena oleh siapapun, maka boleh jadi wacana tentang keadilan yang universal dapat disepakati. Persoalannya ternyata tidak sesederhana itu. Orang dapat bertanya: dalam rangka menjalankan tugasnya untuk bertanggung jawab menegakkan keadilan, bolehkan negara menghukum mati pelaku pembunuhan tersebut? Apakah penghukuman mati seperti ini adil? Jika tidak adil, maka ketidakadilan tersebut dilihat dari sudut pandang siapa? Apakah nilai ketidakadilan bagi kriminal pelaku pembunuhan sebanding dengan nilai keadilan bagi keluarga korban pembunuhan itu? Apabila kita semua tidak sepakat dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, maka hal itu membuktikan bahwa keadilan yang universal itu sesungguhnya tidak pernah hadir sebagai realitas objektif.
Pengusung paham keadilan sebagai nilai universal tentu harus konsisten bahwa universalitas yang objektif itu tadi baru akan terbentuk apabila nilai tersebut tidak terkoneksi dengan dunia empiris. Artinya, nilai tersebut berdimensi transenden, bukan imanen. Karena bersifat transenden, maka nilai keadilan bisa tetap tampil kokoh tidak tergoyahkan di segala zaman dan keadaan.
Transendensi itu dapat diambil dari dua sumber. Pertama, ajaran agama. Kedua, rasionalitas manusia. Dikotomi keduanya memunculkan perbedaan antara ‘lex a Deo aut natura data’ (hukum pemberian Tuhan atau hukum kodrat) dan ‘lex ab hominibus posita’ (hukum buatan manusia). Hukum pemberian Tuhan sebagian didapati sumbernya melalui ajaran agama, khususnya melalui kitab suci (lex divina).
Lagi-lagi, asumsi bahwa hukum pemberian Tuhan itu pun tak mampu tampil monotafsir. Dalam banyak kasus, jangankan antar-agama, dalam satu agama yang sama pun terdiferensiasi pandangan berbeda (mazhab-mazhab) tentang apa yang adil dan tidak adil untuk diputuskan untuk suatu perkara. Demikian pula halnya dengan rasionalitas manusia, yang masing-masing bisa berargumentasi mengikuti pola pikirnya sendiri-sendiri.
Keadilan sebagai nilai partikular
Jadi, apabila asumsi bahwa keadilan sebagai nilai universal, patut dipertanyakan, maka apakah keadilan kini bisa menjelma menjadi nilai partikular, dalam arti berlaku untuk kelompok sosial tertentu saja? Pertanyaan ini harus disikapi hati-hati karena pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa keadilan tidak lagi hasil pergumulan keyakinan transenden, tetapi justru bagian dari pergumulan imanen. Dengan perkataan lain, keadilan menjadi nilai yang diproduksi oleh kesejarahan. Karena Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dengan Malaysia, misalnya, maka adil bagi orang Indonesia tidak harus sama dengan adil bagi orang Indonesia. Bahkan, adil bagi orang Indonesia yang tinggal di Jakarta tidak harus sama dengan adil bagi orang Indonesia yang tinggal di Papua.
Partikularitas ini mengandung bahaya juga karena makin imanen kandungan nilai tersebut, maka makin rentan baginya untuk tercampur dengan kepentingan-kepentingan pragmatis. Orang lalu akan mudah memahami keadilan sama dengan nilai guna atau kemanfaatan. Sebagai contoh, seorang suami yang isterinya dibunuh oleh pria tetangga di kampungnya, akan merasa tidak adil apabila pria pembunuh itu sekadar menerima hukuman penjara. Katakanlah si pembunuh ini dihukum berat sampai dengan sepuluh tahun. Apabila sepuluh tahun berlalu, maka si pembunuh tersebut masih dapat pulang kembali ke rumahnya, berkumpul dengan isteri dan anak-anaknya lagi. Bagaimana dengan nasib pihak korban, yaitu suami yang isterinya telah dibunuh oleh yang bersangkutan? Baginya, kematian isterinya tersebut tidak terbayar (tergantikan) dengan hukuman pemenjaraan pada si pembunuh. Ia tidak mendapat nilai guna dari penghukuman itu. Ada ketidakseimbangan magis yang masih dirasakannya dan sekaligus oleh masyarakat yang ada di dalam komunitas tempat ia hidup. Itu juga rasa keadilan, walau partikular! Bagaimana jika sebagai jalan keluarnya: isteri, saudara perempuan, atau anak perempuan dari si pembunuh dapat diserahkan sebagai ganti dari isterinya yang terbunuh? Solusi ini sekilas terdengar logis apabila perempuan dalam perspektif masyarakat setempat masih dianggap senilai dengan benda dalam lapangan hukum harta kekayaan. Namun, tentu perspektif demikian tidak layak untuk dipertahankan di tengah era peradaban sekarang.
Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa keadilan yang partikular pun membutuhkan proses selektif untuk tidak buru-buru diusung sebagai keadilan yang hakiki. Apalagi jika keadilan partikular itu diasumsikan sebagai keadilan universal. Posisi inilah yang kerap diambil sebagai sikap sekelompok tokoh agama, yang berpura-pura tidak menyadari bahwa keadilan partikular itu sesungguhnya tidak pernah memadai untuk diklaim sebagai keadilan universal. Akibat sikap ini, maka mereka cenderung memonopoli kebenaran dengan mengenyahkan pandangan lain sebagai penyimpangan. Tragedi abad pertengahan di Eropa membuktikan betapa bahaya cara pandang seperti ini.
Keadilan sebagai nilai personal
Sekarang sampai pada pertanyaan, kalau keadilan itu diklaim sebagai nilai partikular, apakah ia juga dapat menjadi nilai personal atau individual? Magnis-Suseno menggunakan istilah ini antara lain dalam bukunya “Etika Politik” (1994: 331). Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Magnis-Suseno memberi contoh seorang pengajar yang akan memberikan nilai ujian bagi para mahasiswanya. Mana yang akan diberi nilai tinggi dan mana yang diberi nilai rendah, berangkat dari keadilan individual itu. Budiono Kusumohamidjojo dalam bukunya “Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil” (2004: 182) menolak pemakaian kata “keadilan individual” ini karena, menurutnya, mengandung contradictio in terminis.
Dengan meminjam istilah Lon L. Fuller (1964), saya meyakini keadilan individual itu ada, namun berada dalam moralitas aspirasi (morality of aspiration), bukan moralitas kewajiban (morality of duty). Moralitas aspirasi menantang manusia untuk melahirkan gagasan-gagasan cerdas guna mengejar cita-cita masing-masing. Dalam wacana tentang hukum, kita memang tidak memakai landasan moralitas aspirasi, melainkan moralitas kewajiban. Standar moralitas aspirasi bisa sangat bervariasi, kendati galibnya, ia selayaknya lebih tinggi dari standar moralitas kewajiban.
Cara pandang seorang suami yang kehilangan isteri dari contoh di atas untuk mendapatkan pengganti berupa isteri si pembunuh adalah suatu keadilan individual apabila muncul dari gagasannya sendiri. Gagasan ini tidak akan menjadi keadilan partikular seandainya tidak mendapat legitimasi (dalam hal ini sosiologis dan etis) dari anggota komunitas lain di luar dirinya. Hukum yang baik tentu tidak boleh menangkap legitimasi demikian menjadi moralitas kewajiban dan mengadopsinya sebagai hukum positif. Bagi Fuller, jika adopsi seperti itu dilakukan, maka hukum yang terbentuk bukan lagi hukum yang buruk (bad law), tetapi bukan hukum sama sekali (no law at all).
Penutup
Ketika orang berbicara tentang keadilan, maka ia berbicara tentang konsep yang sangat longgar dan terbuka untuk diisi dengan apa saja sepanjang ada pembenaran yang diajukan. Tolok ukur keadilan dengan demikian, berpotensi untuk terdistraksi mengikuti kecenderungan moralitas orang per orang. Hal ini sulit sekali untuk dihindari.
Universalitas tidak identik dengan objektivitas. Klaim tentang adanya keadilan yang universal, yaitu bahwa keadilan bisa diukur menurut parameter ketuhanan, juga tidak menjamin objektivitas keadilan tersebut. Kepala putusan pengadilan di Indonesia yang selalu berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” harus secara jujur diakui, tidak pernah tercermin sepenuh-penuhnya di dalam putusan. Ia lebih berperan sebagai moralitas aspirasi bagi hakim.
Oleh sebab itu, sebagai jalan tengah, kaum legisme menganjurkan bahwa keadilan yang paling memungkin dicapai manusia adalah keadilan yang ditegakkan secara nomothetis, yaitu mengikuti apa yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Namun, di sini lagi-lagi muncul persoalan baru dari kaum anti-legisme, bahwa keadilan menurut undang-undang itu tidak boleh sama maknanya seperti bunyi teks yang tertera. Hakim diwanti-wanti jangan berperan sebagai corong undang-undang. Keadilan di dalam hukum tidak identik dengan keadilan menurut undang-undang.
Pesan konkretnya adalah bahwa hakim wajb memberi makna yang paling relevan dan kontekstual untuk setiap kasus yang ditanganinya. Seperti apa pemaknaan keadilan yang paling relevan dan kontekstual itu, tentu tidak pernah mampu diberikan patokannya secara general. Keadilan memang tidak pernah bisa diukur melalui patokan tunggal, apakah ia harus berskala universal, partikular, apalagi personal. Kerumitan menetapkan muatan keadilan kerap memang membuat kita bergeser ke arah kesepakatan logis-rasional (common sense), bahwa benar itu ternyata juga adil. (***)



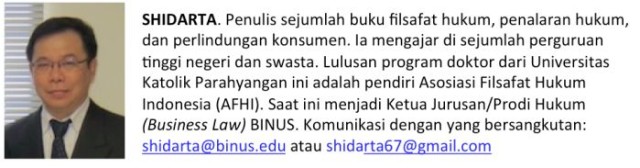
Comments :