TRANSFORMASI HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
Oleh AHMAD SOFIAN (Februari 2017)
Secara khusus tidak ada satu pun pasal dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual. Sehingga dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum tentang masalah ini. Namun demikian beberapa pasal dalam beberapa perundang-undangan telah menyinggung pengaturan masalah ini .
Tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan satu konsep yang belum banyak dibahas dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002) hanya ada menyebut satu pasal yaitu pasal 88 tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 100 juta. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang terperinci tentang eksploitasi seksual yang dimaksud.
Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP (Pasal 297 KUHP : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa,diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun) maupun di luar KUHP (Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diundangkan pada tahun 2007 menjadi UU No. 21/2007). Dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak, sangat minim pengaturan perlindungan terhadap korban, dimana tidak adanya kompensasi maupun sulitnya mendapatkan restitusi dari pelaku (kecuali untuk tindak pidana perdagangan orang (termasuk tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual) seperti diatur dalam UU 21/2007 korban telah mendapatkan hak restitusi dari pelaku dan pemulihan mental/kesehatan dari negara). Padahal tindak pidana eksploitasi seksual anak masuk dalam kategori “pelanggaran mendasar pada hak-hak anak” dan “perbudakan moderen” yang memerlukan perhatian khusus dalam hal penanganannya, dan perlakuan terhadap korban.
Aspek lain yang perlu dipersoalkan adalah mengenai minimnya pemberian restitusi pada korban tindak pidana eksploitasi seksual anak. Restitusi yang merupakan salah satu jenis penghukuman masih minim diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah memasukkan pasal tentang restitusi ini, namun ternyata jenis sanksi ini masih belum populer diterapkan oleh penegak hukum, karena itu perlu diuraikan tentang filofis ajaran restitusi, bagaimana evolusinya serta bagaimana mekanisme penerapannya.
Lawrence P. Fletcher mengatakan bahwa restitusi itu adalah bagian dari tanggung jawab dan prosedur hukum pidana yang harus diterapkan oleh pengadilan. Para korban tindak pidana tidak harus melakukan tuntutan perdata atas kerugian yang diderita olehnya akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, karena secara otomatis itu merupakan sudah tanggung jawab dari pelaku, dan negara bertindak mewakili kepentingan dari korban untuk mengembalikan kerugian yang dirampas oleh pelaku tersebut. Jika hal ini tidak bisa dilakukan oleh negara, maka sebenarnya negara telah gagal melindungi hak-hak korban tindak pidana yang dirampas oleh pelaku tindak pidana. Negara tidak harus menunggu adanya tuntututan ganti rugi dari pelaku melalui mekanisme gugatan ganti rugi di pengadilan.
Sejalan dengan pandangan di atas Jocelyn B. Lamm mengatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual apakah perkosaan, incest atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya jarang sekali mendapatkan apa yang dia sebut dengan “deserving of legal protection and remedies”. Menurutnya hukum telah gagal menyediakan apa yang dia sebut dengan “meaningful relief”. Sementara krimimalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan efek jera dan memberikan rasa “terlindungi” dan rasa “pemuliaan” yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini. Kenapa ini diperlukan ? Karena korban tindak pidana ini telah mengalami dan menderita “psychological injuries”, karena itu sudah sepantasnya korban menerima perlakuan kompensasi yang wajar akibat dari tindakan pelaku ini.
Terkait dnegan hukum acara, ternyata korban harus mengikuti proses pemeriksaan yang panjang yang dimulai dari penyidikan hingga yang penjang di kantor kepolisian hingga proses persidangan. Acap kali saksi korban harus memberikan kesaksian yang berulang-ulang dengan hal yang sama sehingga memunculkan traumatis yang berkepanjangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memberikan jaminan terhadap pemeriksaan yang cepat, biaya murah dan tidak menimbulkan traumatis kepada korban sehingga proses pemeriksaan terhadap korban akan senantiasa memberikan persoalan psikologis kepada korban. Akibatnya korban merasa tidak untuk hadir ke pengadilan sehingga berimplikasi pada bebasnya terdakwa. Karena itu perlu diciptakan satu mekanisme yang baru lebih memunculkan rasa keadilan bagi korban, sehingga korban merasa nyaman dalam memberikan keterangan, dan keterangan itu tidak perlu disampaikan secara berulang-ulang.
Hukum pidana nasional kita kurang memberikan proporsi yang sesungguhnya dalam mempergunakan pendekatan pemidanaan dalam bentuk reparasi, restitusi dan kompensasi. Dalam pendekatan ini maka perhatian pada korban sebagai bagian penting untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan suatu pidana. Fokus perhatian dari pendekaan ini meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu pemidanaan. Reparasi dapat diartikan sebagai the act of making amends for a wrong (perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar). Reparasi dikatakan sebagai suatu jalan yang harus dilalui oleh pelaku (upaya perbaikan) sebagai konsekwensi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai return of restoration of some specific thing to its rightful owner or status (mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilkikan atas status). Reparasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan fomulasi. Dalam hal ini, penghilangan kemerdekaan atau pemberian denda dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan dan diperhitungkan keberdayagunaannya serta kebutuhan yang ingin dicapaikannya. Kunci kesuksesan dalam hal ini adalah apabila subyek perbaikan secara sadar menikmati proses perbaikan tersebut.
Soal restitusi yang dikaitkan dengan hukum pidana sudah mendapat banyak perhatian dan pembahasan, salah satunya adalah Anne O’Driscoll. Dia mengatakan bahwa untuk korban-korban kejahatan terutama kejahatan seksual pada prinsipnya tidak selamanya menyetujui pidana yang seberat-beratnya pada pelaku, tetapi bagaimana agar mereka memperhatikan luka fisik, luka mental dan luka seksual yang dialami oleh korban. Hal ini jauh lebih penting daripada mengirimkan para pelaku bertahun-tahun di dalam penjara-penjara yang mewah. Karena itu lebih baik-baik mereka diperkenankan bekerja dan uang hasil kerjanya dipergunakan untuk membayar sesuatu yang hilang dari diri korban. Dia mencontohkan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan orang untuk keperluan seksual. Bertahun-tahun anak-anak dan perempuan ini tenaganya diperas, lalu melayani para tetamu, dan ketika polisi berhasil membongkar sindikasi dan menangkap pelaku, maka yang terjadi mereka dipulangkan ke keluarga dan dibiarkan begitu saja, dimanakah hasil rampasan dari pelaku?
Memperbandingkan konsepsi, pengaturan dan penerapan tindak pidana ekspolitasi seksual anak dengan OPSC menjadi penting dalam memperkuat hukum nasional di Indonesa yang pada akhirnya akan memberikan suatu perkembangan baru dalam mengkrimininalisasi pelaku dan memperbaiki mekanisme hukum acara yang melindungi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak. (***)



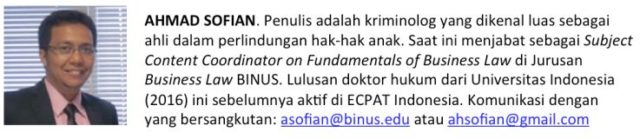
Comments :