SIAPA SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA?
Oleh VIDYA PRAHASSACITTA (Februari 2017)
Berbicara mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat banyak permasalahan baik dari sisi penafsiran maupun dalam penerapannya. Salah satunya adalah mengenai subjek atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Terdapat silang pendapat mengenai apakah pihak swasta atau non-pegawai negeri dapat menjadi subjek dari undang-undang ini. Mulai dari apakah ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dapat diterapkan bagi pihak swasta sampai dengan apakah pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diterapkan terhadap undang-undang ini.
Jika kita melihat sejarah pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001maka kita harus mencermati pembentukan kedua undang-undang tersebut, yang mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1917). Khusus untuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971. Pada saat pembentukan UU No. 3 Tahun 1971, Oemar SenoAdji, Menteri Kehakiman pada saat itu yang menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pengawai negeri sipil atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971. Apabila non-pegawai negeri atau swasta yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara akan dikenakan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang menempatkan non-pegawai negeri atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti undang-undang tindak pidana ekonomi.[1] Oleh karena itu, meskipun dalam rumusan kedua pasal tersebut menggunakan frase “barangsiapa” namun bukan berarti kedua pasal tersebut merupakan communa delict tetapi merupakan delict propria.
Dalam praktiknya Pasal 2 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non-pegawai negeri atau pihak swasta,[2] sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/Pid.Sus/2009, tatkala Majelis Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA. yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah memenuhi dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001. Dalam perkembangannya Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 pun diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan tersebut tidak bisa lepas dari pengertian pegawai negeri dalam UU No. 31 Tahun 1999 sendiri. Terjadi perluasan makna pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Inilah yang kemudian ditarik untuk diterapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 936K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/PID. Sus/2014.
Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 21 Tahun 2000memang diatur mengenai pihak swasta atau non pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam public official bribery para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap sedangkan non-pegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap.[3] Dengan demikian pihak swasta dan korporasi hanya dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi apabila korporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau aktieve omkoping.
Memang terdapat perbedaan pendapat mengenai perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Menurut Indriyanto SenoAdji, hubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan hubungan genus delict dengan species delict. Dalam hal ini unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan genus delict sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan species delict.[4] Akan tetapi beberapa sarjana hukum tidak sependapat karena apabila hubungan kedua pasal tersebut adalah genus delict dan species delict, maka dalam bentuk delik yang dikualifikasi (gekwalificeerd delict) dengan delik yang diperingan (geprivilegieerd delict) seharusnya ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) lebih berat dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.[5]
Terkait hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 mengenai kriteria kerugian negara untuk membedakan penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Para hakim agung sepakat bahwa kerugian negara kurang dari Rp. 100.000.000,- maka yang dipergunakan adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan jika kerugian negara lebih dari nilai tersebut maka Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang dipergunakan. Akan tetapi hal ini tidak tepat dan tidak menyelesaikan perdebatan yang ada.[6]
Terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pegawai BUMN dan BUMD, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari silang pendapat mengenai aspek hukum administrasi keuangan. Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 telah memberikan definisi yang panjang mengenai keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pengertian keuangan negara yang berada dalam Penguasaan BUMN, masih terdapat silang pendapat apakah termasuk dalam cakupan keuangan negara dalam kaitannya dengan aspek hukum keuangan negara. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, negara atau lembaga negara tidak memiliki kewenangan publik dalam BUMN karena telah terjadi transformasi status kekayaan atau keuangan dari status uang negara menjadi uang privat. Hal tersebut didasari pandangan bahwa tata kelola dan tanggung jawab BUMN memiliki kapasitas hukum privat di mana ketentuan yang mengaturnya adalah peraturan perundangundangan yang bersifat privat. Negara, dalam kedudukannya pada BUMN adalah badan hukum privat, yang tindakan dan pengelolaannya dalam badan hukum privat. Ketika terjadi transformasi status hukum uang negara dalam BUMN menjadi berstatus hukum privat. Negara dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik menetapkan keputusan memisahkan keuangan negaranya untuk menjadi modal pendirian BUMN. Selanjutnya ketika uang tersebut masuk ke dalam BUMN, kedudukan negara tidak dapat dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum publik. Dengan demikian terputus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik di dalam BUMN.[7] Oleh karenanya apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMN tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Tidak adanya kesamaan pandangan terkait hal ini menyebabkan terjadi dualisme dalam praktik seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2012, dan Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/PID.SUS/2014. (***)
REFERENSI:
[1] Oemar Seno Adji, “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya” dalam Albert Hasibuan, ed., Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 49.
[2] Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT Citr ditya Bakti, 2002)., hlm. 29.
[3] Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Permasalahannya, (Jakarta: Diadit Media, 2012), hlm. 93.
[4] Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 172.
[5] Shinta Agustina, et al., Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Judicial Sector Support Program, 2016), hlm. 72.
[6] Ibid., hlm. 14-15.
[7] Arifin P. Soeria Atmadja, “Transformasi Status Hukum Uang Negara sebagai Teori Keuangan Publik yang Berdimensi Penghormatan terhadap Badan Hukum” (Paparan Ilmiah Disampaikan pada Acara Syukuran Pemberian Pengharagaan Guru Besar Pengabian Pendidikan Anugerah Sewaka Winayaroha, Jakarta, 2007), hlm. 3-5.



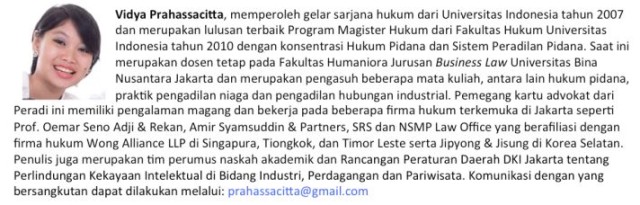
Comments :