BENTUK BARU INTERVENSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Oleh VIDYA PRAHASSACITTA (Desember 2016)
Apabila kita mencermati perkembangan sosial masyarakat di Indonesia saat ini, terdapat kesan adanya upaya intervensi terhadap sistem peradilan pidana kita. Hal yang menarik adanya perbedaan pola intervensi tersebut. Jika dahulu intervensi umumnya dilakukan melalui korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dewasa ini terdapat pola intervensi yang berbeda (meskipun korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut masih terjadi). Tindakan melakukan demonstrasi yang terus menerus (public pressure), pembentukan opini melalui sosial media maupun pemberitaan oleh pers (trial by the press), merupakan bentuk-bentuk intervensi tersebut. Lihatlah salah satu contohnya bagaimana demonstrasi besar-besaran dan terus menerus serta postingan informasi dan pendapat di sosial media terhadap dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan menuntut agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian tentu kita masih ingat bagaimana pemberitaan yang gencar melalui media pers dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana Jessica Kumala Wongso yang pada akhirnya membentuk opini di masyarakat. Tentu masih banyak upaya lainnya seperti #saveyuyun dan tanda pagar save lainnya di sosial media.
Upaya tersebut sekilas memang cara-cara yang dilindungi oleh undang-undang. Hal tersebut kerap dipandang merupakan bagian dari freedom of expression dan freedom of speech yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di tengah situasi lembaga sistem peradilan pidana kita yang masih jauh dari kata bersih dan ideal memang tindakan-tindakan tersebut dipandang menjadi suatu upaya untuk mengawasi jalan dan penggunaan wewenang lembaga sistem peradilan pidana di Indonesia. Hak-hak dasar tersebut pun memiliki batasan hukum formal dan materil yang harus dipertanggungjawabkan di mana secara formil tata cara untuk menyampaikan pendapat tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan secara materil apa yang disampaikan tidak boleh melanggar asas praduga tidak bersalah dan due proces of law. Satu yang menjadi catatan penting yaitu apa yang disampaikan baik sebagai bagian dari freedom of expression dan freedom of speech tersebut haruslah murni disampaikan sebagai bentuk koreksi terhadap jalannya proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tanpa ditunggangi oleh kepentingan apapun, termasuk politik.
Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, membuat masyarakat antipati terhadap suatu keputusan lembaga sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan kehendak si pelapor maupun masyarakat. Seolah-oleh ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana maka aparat penegak hukum harus memproses dan membawa si terlapor ke dalam sistem peradilan pidana. Kemudian ketika seorang terlapor atau tersangka yang didukung oleh kelompok tertentu ditetapkan sebagai tersangka dan diproses dalam sistem peradilan pidana, masyarakat seolah-olah alergi dengan proses ini dan menganggap telah terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Alih-alih menggunakan upaya hukum pra-peradilan yang disedikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya intervensi melalui demonstrasi, pembentukan opini melalui sosial media maupun pemberitaan oleh pers pun dilakukan. Hal tersebut kemudian diikuti dengan dilakukannya pelaporan kepada lembaga pengawas ekstral pada tiap tingkatan lembaga tersebut seperti ke Komisi Polisi Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial maupun Ombusman. Memang hal ini pun merupakan cara yang legal namun dalam praktiknya ada alergi dan ketidaknyamanan dari aparat penegak hukum apabila dirinya dilaporkan kepada pengawasan eksternal meskipun kadangkala apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut aparat penengak hukum mengiyakan intervensi tersebut.
Dalam negara hukum yang terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan sesuatu yang mutlak. Demikian pula dengan keberadaan lembaga peradilan pidana di Indonesia yang harus menganut asas fair, impartial, impersonal and objective di mana peradilan harus dilaksanakan secara bebas, jujur dan tidak memihak di seluruh tingkatan peradilan. Artinya tidak ada intervensi baik dari antar lembaga baik eksektuif maupun legislatif maupun intervensi dari dalam lembaga peradilan itu sendiri. Meskipun demikian, asas pengawasan tetap diberlakukan baik oleh pengawasan internal maupun mengawasan eksternal yang tidak mencangkup isi dari putusan suatu perkara yang telah dibuat oleh hakim.
Hal yang menarik adalah serangan dan intervensi terhadap lembaga peradilan begitu kuat sehingga pola intervensi dilakukan dalam bentuk tahap-tahap proses pra-ajudikasi baik di tingkat tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang semuanya seolah-olah dilakukan sebagai suatu pembenaran dengan yang berlindung di balik asas legalitas (SenoAdji, 2007, 20). Dalam tahap penyelidikan seringkali terdapat intervensi berupa tuntutan untuk ditetapkannya seseorang menjadi tersangka kemudian pada tahap penyidikan adanya tuntutan untuk dilakukannya panangkapan dan penahanan bagi tersangka dipandang menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan yurispudensi tanpa melihat adanya syarat formil dan materil yang diatur dalam KUHAP. Demikian pula pada saat proses penuntutan intervensi untuk tetap dilakukan penahanan dan untuk mempercepat proses hukum.
Asas Kekuasaan Kehakiman yang bebas dalam hukum acara pidana hendaknya harus dipandang tidak hanya terbatas pada proses di peradilan saja. Dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, peradilan merupakan pusat dalam sistem ini akan tetapi keberadaan peradilan merupakan salah satu komponen dari komponen lainnya seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lembaga pemasyarakatan. Ketika terjadi suatu intervensi untuk dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan maka dalam prakteknya Majelis Hakim akan memutus terdakwa bersalah dan hukuman penjara yang dijatuhkan akan melebihi dari masa tahanan. Terlepas dari apakah benar atau tidak terdakwa melakukan tindak pidana dan apakah sesuai hukuman tersebut sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang terpidana lakukan, hal ini tentu akan mencederai kebebasan lembaga peradilan tersebut.
Pada akhirnya, di tengah masyarakat kita yang meminta untuk dihibur oleh aparat penegak hukum untuk dipenuhi sebagai tuntutannya tersebut, maka perlu adanya ketegasan dan keberanian dari aparat penegak hukum di setiap bagian dari sistem peradilan pidana kita agar tetap bebas, jujur dan tidak memihak dalam menjalankan wewangnya sesuai KUHAP. Akan tetapi hal ini saja tidak cukup kalau tidak ditunjang dengan oleh tiga komponen lainnya. Pertama, adanya perbaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, adanya pengetahuan dan kesadaran untuk menghormati proses hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari masyarakat. Dan ketiga, keberanian dan ketegasan dari lembaga pengawas internal dan eksternal untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun untuk tidak memproses laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (***)



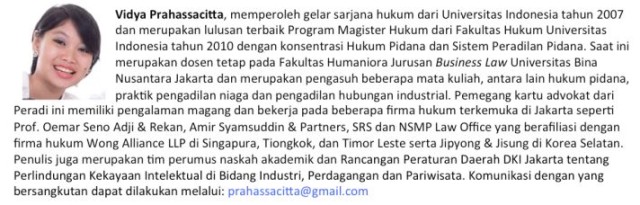
Comments :