SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) DI DALAM UU TAX AMNESTY
Oleh REZA ZAKI (Oktober 2016)
Ada frasa penting yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru berlaku beberapa waktu lalu. Penjelasan Pasal 20 dari undang-undang ini memasukkan frasa “Pidana Lain.” Frasa ini menciptakan inkonsistensi terhadap rezim hukum perpajakan kita. Kemudian, Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) juga menunjukkan upaya tidak kooperatif di dalam membangun transparansi untuk kepentingan perpajakan maupun perdagangan internasional, mengingat dalam hukum perdagangan internasional terdapat satu prinsip penting: transparency. Di samping itu, pasal tersebut bertentangan pula dengan kesepakatan negara-negara OECD bahwa di tahun 2018 akan ada upaya untuk merevisi prinsip kerahasiaan bank (bank secrecy) yang dianggap menghambat laju keterbukaan informasi. Pasal 22 kemudian mengesankan imunitas hukum pejabat negara dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak ini yang mencederai semangat equality before the law. Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan tekhnis yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 142/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle (SPV) yang terdiri dari 8 (delapan) pasal hasil perubahan. PMK tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Mekanisme ini juga diatur di dalam pasal 13 PMK Nomor 118/PMK.03/2016.
Apa yang dimaksud dengan Special Purpose Vehicle (“SPV”) dan mengapa pengusaha atau grup perusahaan menggunakan SPV ? Lalu apakah SPV dapat disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hukum?
Special Purpose Vehicle (SPV) diungkapkan pula oleh Robert L. Symonds, Jr., sebagai berikut: “A Special Purpose Vehicle (SPV) is a company with a limited purpose or focus. It is created by a corporation to conduct a specific or temporary activity. It is normally, but not necessarily, owned almost entirely by the sponsoring corporation. It must be distanced from the sponsor both in terms of management and ownership (not 100%), because if the SPV were to be owned or controlled by the sponsor, there is no difference between a subsidiary and an SPV.”
Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. Oleh sebab itu SPV ini harus dijauhkan dari sponsor baik dalam bidang manajemennya maupun pemilikannya (tidak 100%), karena jika SPV sudah dikuasai atau diatur oleh sponsor, maka tidak akan ada perbedaan antara cabang perusahaan dan SPV.
SPV bukanlah objek hukum yang sering dikaji secara akademik di Indonesia, walaupun dalam praktik bisnis, penggunaannya tidaklah asing sama sekali bagi para pengusaha. SPV secara keuangan dan perdagangan mendapat garansi dari lembaga-lembaga keuangan independen yang terlibat seperti Finance Consultant, Appraisal, Tax Consultant dan lain-lain. Melalui kesempatan ini, saya berharap saya dapat memberikan penjelasan yang memadai bagi masyarakat awam mengenai keberadaan SPV dan bagaimana hukum di Indonesia sebaiknya menghadapi potensi positif dan negatif dari SPV melalui pendekatan ekonomi terhadap hukum (atau disebut juga sebagai pendekatan Hukum dan Ekonomi (Law & Economics).
Lalu apa yang membedakan SPV dari Korporasi pada umumnya? SPV diciptakan dengan fungsi yang sangat khusus/terbatas, terutama untuk membatasi risiko finansial dari pemilik SPV yang bersangkutan (dan dalam konteks tertentu, kepentingan kreditor SPV tersebut) (Pearce II & Lipin, 2011-2012: 179).4 Oleh karena itu, SPV memiliki beberapa ciri khusus yang cukup mudah untuk diidentifikasi, antara lain: tidak memiliki karyawan, tidak memiliki lokasi fisik, dan tidak mengambil keputusan bisnis/ekonomi yang substantif (tidak menjalankan kegiatan usaha) (Tylor, 2009). Ciri-ciri di atas membedakan secara tegas peranan SPV dengan Korporasi yang pada prinsipnya menjalankan kegiatan usaha secara aktif untuk mencari keuntungan (Mueller, 2003).
Dalam praktiknya, SPV dapat digunakan untuk menyamarkan identitas dari pemiliknya melalui konsep pemisahan pemilik dengan badan hukum Korporasi (OECD, 2001). Penyamaran identitas ini umumnya dilakukan dengan jalan mendirikan belasan, puluhan atau mungkin lebih banyak lagi SPV dan menciptakan struktur kepemilikan atas SPV-SPV tersebut yang berlapis-lapis di berbagai yurisdiksi (yang tentunya melibatkan banyak negara).
Penyamaran identitas melalui SPV ini, ditambah dengan keberadaan konsep tanggung jawab terbatas, dapat memberikan insentif negatif kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum termasuk dalam bentuk pencucian uang, korupsi, transaksi orang dalam, penggelapan pajak, dan sebagainya (OECD, 2001).
Mengapa karakteristik SPV di atas dapat menimbulkan insentif negatif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali ke asumsi awal dalam pendekatan hukum dan ekonomi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Sebagai makhluk rasional, seseorang akan melakukan kejahatan apabila keuntungan dari kejahatan tersebut melebihi biaya yang harus dikeluarkan olehnya sehubungan dengan kejahatan tersebut (Becker, 1974). Formula ini berlaku umum untuk segala jenis tindak pidana, baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, sampai dengan korupsi dan pencucian uang.
Mendirikan puluhan sampai ratusan lapisan kepemilikan yang rumit melalui SPV tidak membutuhkan modal yang besar. Dalam praktiknya, US$100 sudah cukup untuk mendirikan suatu korporasi di berbagai negara tertentu yang memang mengkhususkan dirinya untuk berbisnis di bidang pendirian Korporasi (OECD, 2001). Selain itu, biaya operasional menjalankan SPV juga tidak besar karena sesuai dengan fungsinya yang terbatas, SPV tidak memerlukan tenaga kerja, kantor fisik dan kegiatan usaha.
Sekalipun proses pendiriannya mudah, melacak struktur kepemilikan SPV justru merupakan pekerjaan yang sulit, apalagi kalau sampai harus melibatkan otoritas multi-yurisdiksi. Belum lagi fakta bahwa negara-negara yang khusus bergerak di bidang pendirian SPV juga memang umumnya sangat menjaga kerahasiaan identitas pemilik SPV tersebut (OECD, 2001). Kerumitan yang tidak perlu tersebut menambah biaya penegakan hukum, dan sesuai dengan hukum ekonomi, biaya penegakan hukum yang mahal akan menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih sulit. Sebagai akibatnya, biaya untuk melakukan kejahatan akan menjadi berkurang. Kemudahan menciptakan struktur kepemilikan yang berlapis ditambah dengan tingkat kerahasiaan identitas yang tinggi memberikan sarana yang murah dan efektif bagi suatu pihak untuk menyamarkan keberadaannya. Tentu saja sebagai akibatnya terdapat insentif yang besar bagi pihak yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana karena ia dapat berlindung dari tanggung jawab hukum dengan jalan menciptakan lapisan kepemilikan SPV tersebut.
Tidaklah mengherankan kalau hal di atas dapat memicu si pemilik SPV untuk membiarkan saja SPV-nya digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum, atau menggunakan SPV untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha yang berdampak buruk atau berbahaya bagi lingkungan/masyarakat (Hansmann & Kraakmann, 1991: 1883).
Laporan repatriasi yang terus melonjak jangan hanya dianggap sebagai laporan positif bagi pendapatan Negara yang tumbuh. Dalam praktik tax avoidance, kita mengenal istilah Integration atau bisa disebut dengan repatriation and integration atau spin dry. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Begitu uang tersebut dapat diupayakan sebagai uang halal melalui cara layering, maka uang yang dianggap halal tersebut dibelanjakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan atau organisasi kejahatan yang akan diualngi lagi oleh pelaku, dan para pelaku ini dapat memilih penggunaannya dengan cara menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate (barang-barang maupun perusahaan).
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah: (1) Kesepakatan para pihak; (2) Kecakapan untuk membuat perikatan (misal: cukup umur, tidak dibawah pengampuan dll); (3) menyangkut hal tertentu; (4) adanya kausa yang halal. Hal ini berlaku juga pada Hukum Perdata Internasional. Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dengan demikian selama, perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap, mengikat para pihak layaknya, perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat objektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum. (J.Satrio, 1992). Jadi, dalam kaitannya jual beli rumah, misalnya, tidak hanya rumah yang dijadikan objek hukum, melainkan juga uangnya. Asal-usul uang ini juga perlu untuk diketahui apakah berasal dari causa halal atau tidak.
Di samping itu, menurut Konvensi Viena 1980 Covention on Contracts for The International Sales of Goods (CISG) yang terdiri dari 101 pasal. Terkait dengan hal keabsahan dari suatu perjanjian, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini. Hal kedua berkaitan dengan objeknya, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli itu sendiri. Dalam permasalahan kedua ini, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ketentuan hukum materiil mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG bertentangan dengan ketentuan hukum domestik yang berlaku di suatu Negara tertentu yang merupakan Negara salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan perjanjian jual beli menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.
Pada tahun 1995 sempat terjadi skandal pencucian uang besar yang dilakukan oleh Barings Bank, salah satu Bank tertua di Inggris, Bank of Credit & Commerce International (BCCI). Bank sebagai subjek hukum perdagangan internasional mewakili korporasi atau juga bisa disebut sebagai intermediary dalam transaksi bisnis internasional dengan pihak swasta lainnya. Kejadian tersebut mengakibatkan kekacauan sejumlah bisnis di dunia yang berasal dari berbagai Negara karena BCCI memiliki anak perusahaan di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Amerika Serikat. Bahkan BCCI juga terlibat dengan Luxemberg sebagai Tax Haven Country. Patut dicermati, bahwa IMF mencatat jumlah uang haram yang beredar di dunia mencapai 5% dari Gross Domestic Product (GDP) Dunia. (***)



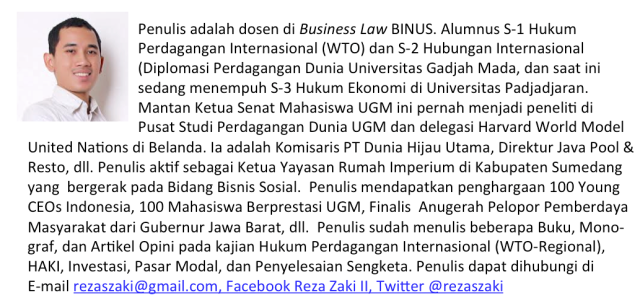
Comments :