WEWENANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO.93/PUU-X/2012
Oleh ABDUL RASYID (Mei 2016)
Pada tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara No. 93/PUU-X/2012 mengenai Judicial Review Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad. Perkara ini secara umum terkait dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Pasal 55 ayat (2) dalam penjelasannya dijabarkan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Menurut Pemohon, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas mengatur bahwa undang-undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Lebih lanjut menurutnya, terdapat kontradiksi antara Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ayat (1) secara tegas mengatur apabila terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama . Namun ayat (2)-nya memberi pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih pengadilan lain, yakni pengadilan umum, untuk menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan isi akad yang disepakati. Hal ini bisa melahirkan multitafir sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada. Sedangkan ayat (3) tidak perlu terbit apabila tidak ada ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, antara lain, akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KHUPerdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, pilihan forum (choice of forum) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menimbulkan persoalan konstitutionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi nasabah dan unit usaha syariah. Di samping adanya ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian, Pasal 55 ayat (2) tersebut juga menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga ekonomi syariah. [Lihat Putusan MK MK No. 93/PUU-X/2012, h. 37]. Dalam Amar Putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Putusan Majelis Hakim MK ini merupakan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutief karena berisi pernyataan dan tidak mengandung unsur penghukuman yang bersifat condemnatoir dan putusan tersebut meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru [Maruarar Siahaan, 2012, 206]. Berdasarkan putusan ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Peradilan lain, yakni peradilan umum tidak berwenang untuk menyelesaikna sengketa perbankan syariah.
Namun, putusan MK tersebut masih menimbulkan polemik dikalangan para praktisi dan akademisi, terutama bagi kalangan yang masih enggan sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan agama. Argumentasi yang dinyatakan adalah bahwa Putusan MK tersebut hanya menghapuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), bukan menghapus Pasal-nya, sehingga Pasal 55 ayat 2 tersebut masih tetap berlaku. Para pihak tetap diberikan kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad yang mereka sepakati (asas kebebasan berkontrak). Jadi apabila mereka sepakat di dalam kontrak menunjuk pengadilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, maka hal tersebut dibolehkan. Ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bukan merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Ini juga sejalan dengan asas pacta sunt servanda yang disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena persetujuan tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini diperkuat kembali oleh Pasal 1338 ayat (2) yang mengatakan “perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pasal 1338 menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang sepakat dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa/menundukkan diri kepada lembaga selain peradilan agama. Hal ini juga tidak kontradiktif karena para pihak diberi kebebasan untuk memilih forum yang lain namun tetap menggunakan prinsip syariah [Nindyo Pramono].
Penulis sepakat dengan argumentasi di atas, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak, semua orang bebas untuk membuat perjanjian, bebas menentukan sendiri isi dan syarat-syarat perjanjiian dan bebas untuk menundukkan diri kepada hukum mana perjanjian yang mereka buat. Intinya mereka bebas membuat semua perjanjian, namun yang perlu diingat kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Dengan kata lain, kebebasan tersebut dibatasi; tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPer). Berdasarkan Pasal 49 huruf (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jelas menyatakan bawah perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Hal ini diperkuat kembali Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
Berbicara mengenai kompetensi absolut antarlingkungan peradilan, empat lingkungan peradilan yang ada, yaitu peradilan umum, peradilan agama, Peradilan meliter dan peradilan tata usaha negara, sebagai pelaksana fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman, telah ditentukan batas-batas kekuasaannya oleh undang-undang dalam melaksanakan fungsi kewenangan mengadili. Masing-masing lingkungan peradilan telah diatur kewenangannya dan kewenangan tersebut bersifat absolut. Dengan kata lain, peradilan hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan dan sebaliknya tidak berwenang menyelesaikan perkara di luar kewenangannya. Menurut Yahya Harahap (2001: 102) tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan setiap lingkungan peradilan agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing berjalan sesuai dengan rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak saling berebut kewenangan. Di samping itu juga bisa memberi ketentraman dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan, memberi arah yang lebih pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara. Apabila kekuasaan absolut masing-masing lingkungan peradilan tidak ditentukan, maka akan tercipta kekuasaan hakim yang kacau balau dan penegakan kepastian hukum akan hancur berantakan. Oleh karena itu berdasarkan argumentasi di atas, maka tidak tepat apabila dikatakan memberikan kewenangan absolut kepada kepada dua pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tidak menimbulkan ketidak pastian hukum. Namun sebaliknya, penyelesaian sengketa akan menjadi semakin tidak jelas. Para pihak akan memilih lembaga peradilan yang mereka suka. Pihak penggugat bisa mengajukan ke pengadilan negeri, atau pengadilan tata usaha negara dan pihak lawan mengajukan ke pengadilan agama. Lalu Masing-masing pengadilan memberikan putusan yang berbeda-beda sehingga menjadi kacau balau dan tidak ada lagi penegakan dan kepastian hukum. Menurut Prof. Abdul Manan, dalam kuliah umum yang diadakan oleh Jurusan Business Law, (21/05/2016, juga menyatakan tidak ada masalah lagi atas putusan MK tersebut. Berdasarkan putusan MK, peradilan agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara perbankan syariah dan hal ini sudah disepakati dalam internal MA. Wallahu ‘alam. (***)



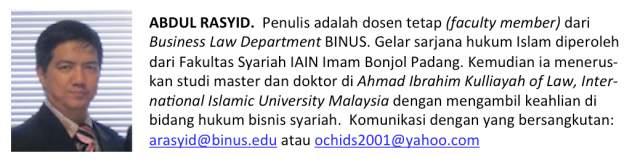
Comments :