KONSEP “OUTSOURCING” DAN PENGUATAN HAK PEKERJA
Artikel penulis di bawah ini ingin dimulai dengan menampilkan cuplikan tulisan Mulyanto berjudul “Qua Vadis Buruh Kontrak” (Majalah Varia Peradilan No. 295, Juni, 2010, hlm. 59-63). Tulisan ini menarik untuk dijadikan prolog tentang cerminan (arketipe) pelaksanaan outsourcing dalam perspektif buruh, pengusaha, dan pemerintah (ketiganya lazim disebut tripartit). Ia menulis sebagai berikut:
“Salah satu isu tuntutan kaum buruh dewasa ini adalah penghapusan buruh kontrak termasuk outsourcing (pengalihan tenaga kerja) dalam sistem perburuhan nasional, aksi buruh akhir-akhir ini yang salah satu tuntutannya adalah menolak pengalihan status ke karyawan kontrak. Aksi Buruh akhir-akhir ini sering mengangkat isu antara lain: menolak sistem kerja outsourcing / penyerahan sebagian pekerjaan yang diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan, serta menghapus sistem buruh kontrak untuk semua pekerjaan, karena hal tersebut jelas dirasa tidak menguntungkan bagi pekerja/buruh. Sejauh ini belum ada pengaturan teknis yang jelas soal pekerja/buruh kontrak atau outsourcing, khususnya mengenai jenis pekerjaan apa saja yang termasuk pekerjaan pokok (core business) dan bersifat penunjang (non-core business).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur jenis pekerjaan yang bersifat pokok dan penunjang tanpa merinci secara jelas mana yang termasuk jenis pekerjaan pokok dan penunjang. Hal ini banyak menimbulkan persoalan dalam praktik. Akibatnya, pihak pengusaha outsourcing kerap memaksakan untuk memborongkan hampir semua jenis pekerjaan ke perusahaan pengguna tenaga kerja. Sistem outsourcing dalam konteks hubungan kerja perlu diperjelas, karena selama ini ada semacam ketidaktegasan dengan siapa pekerja/buruh mempunyai hubungan kerja.
Dalam situsai yang seperti ini harus dicari pemecahan persoalan secara elegan dengan prinsip win-win solution. Kita tidak menginginkan perusahaan banyak gulung tikar yang dikarenakan menanggung berat ongkos produksi yang cuma termasuk anggaran untuk tenaga kerja, akan tetapi kita juga tidak ingin para pekerja/buruh diperas keringat dan tenaganya. Dengan adanya pengaturan yang jelas tentang pekerja/buruh kontrak, diharapkan dikemudian hari tidak muncul tuntutan akan penghapusan atas hal tersebut.”
Dalam tulisan tersebut terkesan kuat bahwa dalam rangka “mengurangi pengangguran” pemerintah tidak dapat berbuat banyak dan menyerahkan semuanya pada market prevalence, dalam hal ini kelaziman yang dilakukan dalam tatanan hubungan kerja. Filosofi utamanya adalah tercapainya hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam penyerahan dan penerimaan pekerjaan. Hal ini berimplikasi ironis bahwa motif untuk “mengurangi pengangguran” itu terbukti tidak berjalan berimbang, mengingat dasar hubungan perburuhan juga harus tunduk pada hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) dalam lapangan hukum perikatan perdata, yaitu suatu perjanjian dinyatakan sah sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Padahal, subjek-subjek hukum yang terlibat dalam perikatan itu tidak dalam posisi tawar yang sama kuatnya. Kondisi ini mengemuka tatkala kita berbicara tentang bentuk hubunga kerja yang dijalin oleh para pekerja (buruh) “outsourcing”.
Tidak mengherankan apabila muncul tuntutan buruh untuk melakukan penghapusan terhadap bentuk hubungan kerja tersebut. Bahkan, ada rencana akan dilakukan mogok nasional untuk menunjukkan perlawanan kelompok pekerja dalam rangka memperjuangkan [salah satunya] penghapusan sistem kerja kontrak outsourcing.
Istilah outsourcing dalam terminologi hukum disebut “pemborongan pekerjaan”. Dalam tulisan ini istilah terakhir ini sengaja tidak digunakan karena memang kata “outsourcing” tampaknya lebih memasyarakat. Selain itu, pemborongan pekerjaan merupakan istilah yang sudah cukup dikenal dalam Pasal 1604 KUHPerdata, yang maknanya tidak identik dengan outsourcing. Istilah “alih daya” juga kerap dipakai, tetapi tampaknya belum terakomodasi dalam hukum positif dalam bidang ketenagakerjaan kita.
Outsourcing telah memiliki dasar dalam ketentuan hukum positif dengan diberlakukannya Permenakertrans No. 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Aturan ini dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya yang merupakan juklak pemerintah terhadap Permenakertrans tersebut, yakni dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE. 04/MEN/VIII/2013. Kedua produk hukum positif ini mempunyai kekhususan dalam tatanan pengaturannya dengan produk perundangan sebelumnya. Kekhususan tersebut menjadikan pekerjaan rumah bagi kalangan dunia usaha dalam hal penggunaan jasa pekerjaan (job supply) dan jasa tenaga kerja (labor supply).
Kekhususan tersebut adalah karena jenis kegiatan pekerjaan yang diperkenankan untuk diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa outsourcing harus berada dalam klasifikasi jenis kegiatan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (core bussines) suatu perusahaan, yakni: cleaning service, catering, security, driver, dan administrasi pada kantor pertambangan/perminyakan. Lengkapnya, Pasal 17 dari Permenakertrans No. 19 tahun 2012 berbunyi sebagai berikut:
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
Asosiasi bidang usaha dapat juga menetapkan core business dalam bidang usaha mereka sendiri, dengan syarat harus didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan. Akibatnya, seringkali anggota asosiasi bidang usaha tersebut relatif bisa bebas menginterpretasikan area-area kerja yang bisa diikat dengan sistem kontrak outsourcing.
Dalam praktik, tidak bisa dihindari bahwa ketidakharmonisan dalam kontrak outsourcing ini terus terjadi. Kontributor dari ketidakharmonisan ini sebagian justru berasal dari ketidakjelasan sikap pemerintah. Pemerintah terkesan ingin “lepas tangan” dalam rangka menata sistem outsourcing, mengingat pola-pola outsourcing (khususnya berupa pemborongan pekerjaan) memang telah berlangsung sebelum adanya produk hukum positif seperti yang disebutkan di atas. Pemerintah sekadar berusaha menyediakan produk baru dalam hukum positif, yang sebenarnya tidak banyak memberi kekuatan lebih bagi pihak pekerja outsourcing tersebut.
Oleh sebab itu, penulis berpendapat, sangat perlu bagi pemerintah untuk memperjelas definisi dan penjabaran dari konsep core dan non-core tersebut. Celah-celah hukum yang mungkin sengaja diciptakan oleh asosiasi-asosiasi bidang usaha juga harus dicermati agar dalam praktiknya tidak dimanipulasi oleh pihak pengusaha.
Nasib pekerja outsourcing menjadi sangat rentan karena posisinya berdiri dalam dua area hubungan hukum. Secara hukum ia adalah karyawan perusahaan penyedia jasa outsourcing, tetapi secara teknis biasanya ia tunduk untuk melayani permintaan si pemakai jasa outsourcing. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan penyedia jasa akan menerima dan menjatuhkan penilaian kinerja pekerja semata-mata atas informasi dari pemakai jasa. Hak pekerja untuk memberikan pembelaan diri jika diperlakukan secara tidak adil, apalagi pembelaan itu akan disalurkan melalui serikat pekerja, praktis tertutup aksesnya.
Pemerintah sudah saatnya untuk mengambil sikap yang tegas untuk memperhatikan nasib pekerja outsourcing ini dengan terutama memperkuat posisi tawar mereka. Pertama, dengan melakukan pengawasan terhadap konsistensi pengusaha dalam mengimplementasikan area core dan non-core business mereka. Kedua, menertibkan perusahaan-perusahaan penyedia jasa outsourcing yang tidak profesional. Ketiga, memberi akses lebih luas bagi pekerja outsourcing untuk menjalani mekanisme pembelaan diri dalam hal terjadi perlakuan yang tidak adil dalam hubunga kerja yang dijalani. (***)



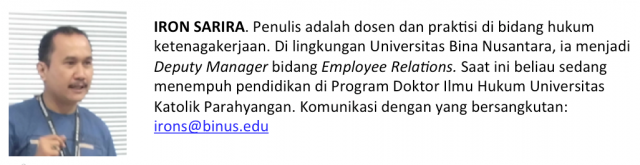
Comments :