KOTA-KOTA BUATAN DAN FILOSOFI ALUN-ALUN
Oleh SHIDARTA (April 2016)
Di sekeliling kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung, saat ini telah tumbuh kota-kota ‘satelit’ yang sengaja didesain melalui tangan-tangan para arsitek tata kota. Kota-kota satelit tersebut tidak tumbuh secara alami, melainkan buatan (by design).
Ada fenomena menarik bahwa kota-kota satelit model baru ini berawal dari kompleks perumahan yang luas. Bumi Serpong Damai (BSD) yang terletak di bagian Barat kota Jakarta, misalnya, memiliki luas lahan sebesar 6.000 hektar (60 km2). BSD juga mengklaim dirinya sebagai kota mandiri, kendati secara admnistratif ia ada di wilayah kota Tangerang Selatan yang total mencapai luas 147,19 km2. Artinya, wilayah BSD sudah menempati setengah dari area kota Tangerang Selatan tersebut. Dengan area seluas itu, BSD sendiri di luar area Tangerang Selatan lainnya, sudah hampir mendekati seperempat kota Serang, ibukota provinsi Banten (266,77 km2).
Namun, ketika kita memasuki kota-kota buatan seperti ini, kendati mencakup area yang luas, tetap saja terasa ada sesuatu yang hilang. Kota-kota buatan ini terasa jauh dari nuansa keindonesiaan. Jangan persoalkan soal nama-nama cluster dan tipe arsitektur bangunannya, yang terkadang membuat kita bertanya-tanya apakah benar bahwa nama-nama “Indonesia” sangat tidak benilai komersial? Benarkah nama “Cluster Jasmine” lebih bernilai jual dibandingkan “Tandan Melati”? Tulisan ini tidak darahkan ke sana. Sesuatu yang hilang yang dimaksudkan di sini adalah sebuah fasilitas sosial berupa ruang publik yang sebenarnya telah diamanatkan dalam desain kota-kota di Indonesia sejak era kerajaan dan bahkan diteruskan di masa kolonial Belanda, yakni alun-alun.
Alun-alun (konon diambil dari kata “alunan”) memuat filosofi sangat mendalam, sebagai wahana pertemuan gelombang berdimensi mikro- dan makrokosmos kehidupan. Apabila manusia diasumsikan sebagai mahluk mikrokosmos (hidup di alam konkret yang imanen) maka ada dimensi lain di luar manusia (kehidupan alam abstrak yang transenden). Kedua alunan gelombang itu berinteraksi secara intens setiap saat. Intensitas ini akan menjadi makin harmonis jika tersedia momentum dan ruang publik, tempat manusia dari berbagai kalangan dapat bertemu, bersenda gurau, dan beraktivitas secara massal. Alun-alun kota adalah tempat yang dirancang untuk mempertemukan alunan gelombang kosmis itu.
Benar bahwa di beberapa kota buatan itu terkadang disediakan jalur-jalur hijau (biasa dipakai untuk jogging track) atau bahkan hutan kota, tetapi sering tempat-tempat ini tidak menarik perhatian karena berada di lokasi yang tidak strategis. Alun-alun seyogianya tidak demikian. Alun-alun justru harus berada di tempat yang paling strategis, di jantung (pusat) kota. Alun-alun diapit oleh setidaknya empat jalan utama yang mengelilinginya, dengan dikelilingi bangunan penting seperti balai kota dan rumah-rumah ibadah.
Persoalannya adalah, seringkali membangun alun-alun dianggap bukan pilihan yang rasional bagi para pengembang kota-kota buatan ini. Tidak banyak pengembang yang rela berbagi lahan strategis untuk sebuah alun-alun, mengingat harga lahan di lokasi strategis minimal seluas 22.500 m2 itu bisa saja mencapai angka Rp20 juta/m2, bahkan lebih! Artinya, pertimbangan rasional-komersial akan mengalahkan pertimbangan filsofis demikian. Kedua, ada anggapan bahwa alun-alun akan menjadi pemancing bagi daya tarik pengunjung yang tidak lagi terseleksi. Hal ini justru dikhawatirkan karena alun-alun bisa menjadi pemicu kriminalitas. Di sisi lain, kota-kota buatan kerap menjual eksklusivitas sebagai modal penting. Makin eksklusif makin menarik bagi para calon pembeli. Mengingat kota-kota buatan ini berdiri dari awalnya lahan-lahan permukiman penduduk yang tidak semuanya sukses dipindahtangankan, maka tatkala kota-kota buatan itu resmi berdiri, permukiman tersebut masih eksis dan mereka pun ikut menikmati fasilitas kota-kota buatan ini. Namun, apakah anggapan ini benar-benar valid?
Banyak kota di Indonesia menunjukkan kondisi sebaliknya. Kerawanan kriminalitas yang kerap dilabelkan pada alun-alun ternyata tidak terbukti di banyak kota. Sepanjang tata tertib ditegakkan, banyak alun-alun kota yang menjadi daya tarik karena mampu menjadi landmark kota masing-masing. Dalam kajian semiotika, alun-alun adalah petanda dan penanda sebuah kota.
Patut dicatat bahwa alun-alun kota sesungguhnya merupakan arena terjadinya kanalisasi akibat keterpisahan sekat-sekat sosial, yang notabene merupakan salah satu cikal bakal kriminalitas di sejumah permukiman baru. Penduduk di kota-kota buatan ini, tidak selalu harus dipersepsikan datang dari kalangan “the have” yang harus dijaga (atau menjaga) jarak sosialnya dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di pinggiran permukiman baru itu. “Orang-orang kampung” demikian mereka kerap disapa, adalah rekan sebangsa yang bukan tidak mungkin malahan sangat dibutuhkan karena mereka inilah yang sering mengisi posisi sebagai tenaga-tenaga informal (bahkan juga formal) di kota-kota buatan tersebut. Mereka inilah yang kebanyakan menjadi tenaga pengamanan, tenaga penjual di toko-toko setempat, penjual keliling (jika memang masih diizinkan masuk ke permukiman), dan seterusnya. Simbiosis mutualistis seperti ini adalah tugas yang tidak boleh diabaikan sebagai bagian dari tanggung jawab pengembang permukiman kota-kota buatan untuk menciptakan dan memeliharanya. Mereka bukan agen-agen pencipta eksklusivitas dan pemelihara sekat-sekat sosial. Mereka malahan harus diminta untuk mencegah terbentuknya gaya hidup eksklusif itu, dengan cara hidup berdampingan secara harmonis dengan semua kalangan. Negara tidak boleh membiarkan sekat-sekat sosial antara penduduk pendatang (pemukim baru) dan penduduk asli setempat (pemukim awal) tetap terdistansi melalui tembok-tembok fisik yang dibangun menjulang mengikuti garis lahan yang dikonsesikan.
Oleh sebab itu, jika kita ingin mengembalikan roh dari hadirnya ruang-ruang publik di kota-kota buatan ini, maka selayaknya ada regulasi baru yang memberi kewajiban bagi pengembang (dengan luas konsesi lahan tertentu) untuk membangun fasilitas sosial alun-alun kota. Alun-alun ini wajib dijadikan ruang terbuka tempat semua warga masyarakat tanpa terkecuali berinteraksi. Nuansa religio-magis, komunalitas, dan semangat kolektivitas, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia diharapkan dapat tercermin dari sekeping lahan yang sejak nenek moyang kita dulu sudah pernah ada, yang sedemikian penting sehingga sampai-sampai disakralkan, yang disebut “alun-alun”. Jika tidak, sungguh tidak ada yang perlu dibanggakan dari bertumbuhnya kota-kota satelit di sekeliling kita karena pada hakikatnya kita baru pandai pada taraf membangun raga, bukan jiwa suatu kota! (***)

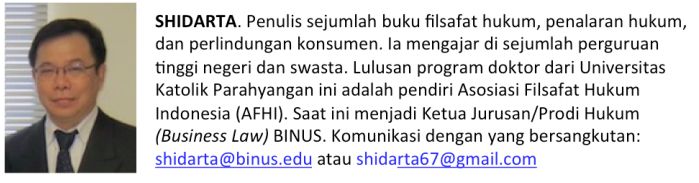
Comments :