PEMOSISIAN LANDASAN TEORETIS DALAM PENELITIAN HUKUM
Oleh SHIDARTA (Februari 2016)
Kerap muncul pertanyaan dari kalangan peserta program doktor tentang bagaimana harus mendudukkan teori-teori yang mereka gunakan dalam penelitian. Di beberapa perguruan tinggi, termasuk di universitas yang menyelenggarakan program doktor ilmu hukum, ada keharusan bagi peneliti yang tengah menyusun disertasi agar mendudukkan tiga landasan teoretis untuk topik penelitian mereka, yang disebut teori dasar/besar (grand theory), teori menengah (middle range-theory), dan teori aplikatif/terapan/rendahan (applied theory). Sering ada kesulitan bagi para peneliti tersebut untuk memastikan mana yang harus diposisikan sebagai teori dasar, menengah, dan aplikatif, serta apa tolok ukurnya.
Dalam ilmu-ilmu sosial, pemilahan ketiga jenis teori itu biasanya didasarkan pada seberapa kuat kedekatannya pada ruang dan waktu. Teori aplikatif adalah teori yang sangat empirikal karena langsung terikat dengan ruang dan waktu. Pada sisi sebaliknya terdapat teori dasar, yaitu teori yang paling abstrak, dalam arti ia sudah atau hampir-hampir lepas dari ikatan ruang dan waktu. Nah, di tengah-tengahnya terdapat teori menengah. Teori dasar dan teori menengah selalu berdimensi banyak (multidimensional), sedangkan teori aplikatif berdimensi tunggal (unidimensional). Oleh karena berdimensi tunggal, maka konsep-konsep dalam teori rendahan akan mudah untuk dioperasionalisasikan dalam berbagai bentuk atribut dan/atau variabel.
Tolok ukur (aras) abstraksi itu, menurut John Ihalauw (Konstruksi Teori, 2008: 95) dapat dicermati dari kandungan nilai informatif dari konsep dan proposisinya. Makin tinggi nilai informatif sebuah proposisi, maka makin banyak sifat fenomenon yang dapat diramalkannya. Ini berarti, katanya, memberi tugas yang amat penting kepada para ilmuwan untuk merampatkan (menggeneralisasi) sejumlah besar proposisi bernilai informatif rendahan supaya menjadi sejumlah kecil proposisi yang memiliki nilai informatif tinggi.
Dengan bahasa yang lebih sederhana, kita dapat memaknai pesan dari Ihalauw di atas dengan mengatakan bahwa di dalam suatu teori rendahan, nilai informatif yang ditunjukkan dari kaitan antar-konsep (proposisi)-nya tidaklah menggambarkan banyak sifat fenomenon. Lain halnya dengan teori dasar. Dengan perkataan lain, teori aplikatif mengandung proposisi-proposisi yang nilai informatifnya lebih konkret. Saya berikan contoh sebagai berikut. Kata “pelanggaran hukum” adalah sebuah konsep yang lebih abstrak dibandingkan dengan konsep “pelanggaran rambu lalu lintas”. Jadi, “pelanggaran hukum” memiliki nilai informatif yang lebih tinggi daripada “pelanggaran rambu lalu lintas” karena ia dapat menggambarkan sekaligus meramalkan lebih banyak sifat fenomenon. Kita dapat menurunkan lagi nilai informatif dari “pelanggaran rambu lalu lintas” ini, katakan misalnya, dengan membuat konsep yang lebih konkret, yakni “pelanggaran tanda larangan parkir”. Jika sebuah konsep dapat dicermati nilai informatifnya, maka demikian juga dengan proposisi. Sebagai contoh, kita menghubungkan antara konsep “pelanggaran hukum” itu dengan konsep “kualitas penegakan hukum,” sehingga memunculkan proposisi yang menjelaskan seperti apa kaitan di antara keduanya. Teori dasar akan bersinggungan dengan konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang mengandung nilai informatif tinggi. Sebaliknya, teori aplikatif bersingungan dengan konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang mengandung nilai informatif rendah.
Dalam disiplin hukum, tidak selalu mudah untuk menemukan tolok ukur untuk keperluan pemilahan teori dasar, menengah, atau aplikatif. Hal ini antara lain karena definisi setiap konsep hukum tidak selalu konstan. Makna sebuah konsep hukum pada sebuah undang-undang, sangat mungkin berbeda dengan makna pada undang-undang atau sumber hukum lainnya. Apalagi jika makna itu dikomparasi dengan sistem hukum dari negara yang berbeda. Oleh sebab itu, saya ingin menawarkan alternatif menggunakan indikator pemosisiannya dengan memakai strategi kognisi dalam penyusunan suatu bangunan ilmu. Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Lazimnya, suatu bangunan ilmu akan terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling bawah adalah fakta. Dalam ilmu hukum pun, fakta ini merupakan susunan paling bawah, yang berdimensi empiris karena terikat pada ruang dan waktu. Penting dicatat bahwa dalam perkembangannya kemudian fakta yang berdimensi empiris ini bisa diabaikan oleh ilmu hukum yang berkarakter normatif. Itulah sebabnya, kita mengenal apa yang disebut dengan fiksi hukum. Saya ingin mengatakan bahwa dalam ilmu hukum yang berkarakter normatif itu, tidak semua bangunan kognisi kita harus bersumber dari fakta. Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu empiris. Sebagai contoh, semua orang dianggap tahu hukum, jelas tidak faktual. Itu adalah sebuah anggapan, bahkan suatu fiksi.
Dari beraneka ragam fakta itulah kemudian lahir konsep-konsep. Setiap konsep pada hakikatnya adalah hasil generalisasi fakta-fakta. Kita membentuk konsep karena kognisi kita melakukan penelaahan dan kemudian pemilahan terhadap fakta-fakta itu. Semua fakta yang masuk dalam klasifikasi karakteristik yang sama kita masukkan ke dalam satu konsep. Karakteristik atau ciri-ciri ini merupakan konotasi yang seyogianya komprehensif atas semua fakta terkait. Dengan perkataan lain, konotasi ini merupakan komprehensi dari fakta-fakta itu. Ada konsep yang kita beri nama dan ada yang tidak. Nama untuk konsep itu kita sebut terma (dari kata “term” atau “terminology”). Apa terma yang kita berikan, sangat bergantung pada bahasa yang digunakan. Jadi, dengan mengacu pada satu terma, kita sekaligus dapat membayangkan ciri-ciri dari konsep itu dan anggota-anggota yang secara faktual memenuhi kriteria ciri-ciri itu tadi. Anggota-anggota ini merupakan denotasi dari konsep tersebut. Sebagai contoh, di dalam satu ruangan kita melihat terdapat fakta telah hadir sebanyak 20 orang. Kognisi kita akan mencermati ciri-ciri mereka dan kita menarik kesimpulan ada 10 orang pria dan 10 orang wanita. Pria dan wanita adalah terma untuk konsep jenis kelamin. Tentu kita punya konotasi tentang ciri-ciri untuk bisa disebut pria dan wanita. Berangkat dari konotasi tadi kita dapat menentukan siapa saja dari ke-20 orang itu yang menjadi anggota (denotasi) kelompok pria dan wanita.
Kognisi manusia tentu tidak akan membatasi diri pada tataran konsep. Kognisi kita memiliki kemampuan menghubungkan konsep-konsep itu, yang kita sebut proposisi. Dalam ilmu hukum, asas-asas hukum biasanya masuk ke dalam tataran ini. Demikian juga klausula-klausula dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Jika kita mengacu pada asas legalitas, misalnya, maka tentu kita dapat memahami bahwa di dalam asas tersebut tidak hanya terdiri dari satu konsep. Ada sejumlah konsep yang terhubungkan di situ, seperti konsep hukum tertulis (lex scripta), larangan retroaktif (lex temporis delicti), dan larangan analogi (lex stricta). Semua konsep itu terhubungkan satu sama lain. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sudah mapan tentu dapat menjelaskan bagaimana pola hubungan itu.
Nah, dalam suatu penelitian, kita dituntut untuk membangun kerangka konsep. Bangunan keangka konsep itu penting untuk membantu kita memahami dan menjelaskan tentang hubungan satu konsep dengan konsep lainnya. Oleh karena rumusan masalah yang kita ajukan kerapkali cukup kompleks, maka kita sering dituntut untuk membuat beberapa proposisi sekaligus yang kemudian dijalin menjadi satu aliran berpikir. Jadi, pada akhirnya terdapat suatu kerangka berpikir, yang sebenarnya merupakan rangkaian satu proposisi yang terhubung ke proposisi lainnya, sehingga kita menemukan satu landasan kognitif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Rangkaian antar-proposisi ini sesungguhnya dalam skala kecil sudah merupakan “teori” juga karena sudah memiliki fungsi deskriptif dan preskriptif. Suatu teori pada hakikatnya merupakan bangunan “inter-related propositions”. Teori di tataran ini sangat aplikatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kalau begitu, kerangka konsep ini sebenarnya bisa dipakai sebagai ‘applied theory’ dalam penelitian tersebut.
Lalu bagaimana dengan posisi teori menengah (middle-range theory)? Teori di tataran ini dapat ditemukenali dari cara kita mengalirkan konsep-konsep di dalam proposisi yang ada dalam kerangka yang sudah kita susun. Mungkin pada saat kita menyusun rangkaian konsep dan rangkaian proposisi untuk keperluan menjawab rumusan masalah, kita sebenarnya sudah menggunakan referensi teoretis tertentu. Sebagai contoh, dalam rumusan masalah penelitian kita mempertanyakan tentang benturan antara asas legalitas dan asas oportunitas dalam kasus “X”. Setelah konsep-konsep dari kedua asas itu dipetakan, kita tentu perlu memikirkan bagaimana harus mengaitkan keduanya di dalam satu kerangka konsep. Apakah ada teori yang bisa membantu? Jika ada, maka inilah teori menengah yang bisa diajukan.
Teori di tataran ini, dengan demikian, lebih luas daripada teori aplikatif. Teori di tataran menengah memiliki kontribusi untuk membantu kita menjelaskan bagaimana hubungan antar-proposisi itu dijalin dalam rangka mengalirkan konsep-konsep yang kita bangun dalam kerangka konsep.
Sekarang kita masuk ke teori dasar (grand theory). Teori di tataran ini sudah harus berhubungan dengan ilmu atau rumpun ilmu hukum terkait. Orang mengatakan bahwa teori itu perkara pilihan terkait jendela mental yang kita gunakan. Walaupun relatif arbiter, tidak lalu berarti kita bisa memilih teori secara sembarangan. Harus ada pertanggungjawaban ilmiah tentang pilihan-pilihan itu. Biasanya, pada level ini peran paradigma mulai dirasakan pengaruhnya. Sebagai contoh, dalam hal kita ingin menjawab rumusan masalah tentang perbenturan asas legalitas dan oportunitas tadi, akan terlihat bahwa jika kita menggunakan suatu teori yang berada dalam area legisme, maka hasilnya bisa sangat berbeda dengan jika kita memakai teori di area realisme.
Persoalannya sekarang, apakah kita harus memulainya dari penentuan teori dasar menuju ke teori aplikatif; atau sebaliknya dari teori aplikatif dulu baru menuju ke teori dasar? Pertanyaan ini juga membawa konsekuensi tersendiri. Sebab, apabila kita sudah sejak awal memiliki preferensi paradigmatis tertentu, misalnya memahami hukum seperti layaknya kaum realis, akan ada kecenderungan kuat kita mencari konsep-konsep hukum dan kemudian menyusun kerangka konsep yang sejalan dengan pandangan kaum realis itu. (***)




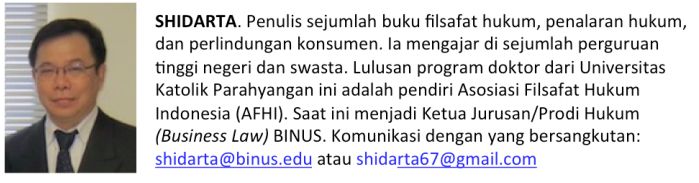
Comments :