KEARIFAN LOKAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Oleh IRON SARIRA (Februari 2016)
Kearifan lokal (local wisdom) dapat diartikan sebagai nilai-nilai dalam wujud gagasan setempat atau suatu daerah yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik (berupa anjuran dan larangan) yang tertanam, diakui, dan diikuti oleh masyarakat setempat.[1] Konsep ini pertama kali diutarakan oleh Quaritch Wales (1948-1949). Jika pandangan Quaritch Wales (QW) ini dikaitkan dengan hukum, maka kearifan lokal itu tadi akan mendekati konsep tentang hukum yang berlaku atau hidup dalam masyarakat (living law), meliputi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Wujudnya bisa berupa hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.[2]
Ajip Rosidi menggunakan terminologi lain, yaitu local genius untuk konsep yang kurang lebih sama. Dengan mengambil pendapat dari QW, ia memaknainya sebagai “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan tersebut berhubungan.” Oleh karena itu, nilai-nilai lokal setempat dapat dijelaskan sebagai wujud dari suatu kepribadian setempat, identitas kultural masyarakat setempat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus (kebijakan) yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara turun-temurun sebagai suatu aktualisasi sikap dan tingkah laku masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan penuh rasa kearifan. Nilai-nilai ini sekiranya dapat diakomodasi sebagai aturan atau kebijakan yang dapat diberlakukan sebagai hukum positif, karena dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan dan berinteraksi terhadap perubahan yang terjadi.[3] Pengakomodasian nilai kearifan lokal sebagai upaya dalam perwujudan keadilan memerlukan kajian filosofis (nilai-nilai filsafat terhadap pemahaman filos, cinta dan sophia, kebijaksanaan), sebagai manisfestasi terhadap ide/gagasan pada ranah kenyataan yang mewujud dalam tata aturan tentang mana yang baik dan buruk, untuk kemudian nilai-nilai tersebut dikonkretkan sesuai dengan cara pandang, ideologi ataupun konsensus yang berlaku.[4]
Penulis sendiri berpendapat bahwa kearifan lokal adalah gagasan kebaikan yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat suatu daerah yang diwujudkan sebagai indentitas budaya yang unik dan memiliki daya tahan dalam berhadapan dengan pengaruh eksternal. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kearifan lokal harus mengandung nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya kearifan lokal ini bisa berkesinambungan, dijaga dan dipelihara dalam perjalanan kehidupan masyarakat setempat.
Kita menghadapi satu kondisi saat ini, yaitu adanya tantangan dan hambatan terkait implementasi sistem hukum positif Indonesia. Kuat sekali terkesan bahwa terjadi disfungsi hukum positif karena hukum tidak berpihak pada masyarakat miskin dan termarginalkan. Untuk itu diperlukan penyusunan kebijakan oleh pemerintah dalam rangka mengatur perilaku warganya. Strategi penyusunan kebijakan dilakukan dengan cara mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang di dalamnya termasuk mekanisme warga dalam penyelesaian perselisihan (konflik). Nilai-nilai ini diadopsi ke dalam hukum positif dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Misalnya, setelah kemerdekaan, pernah ada peraturan daerah di Propinsi Kalimantan Tengah yang memberi tugas kepada damang untuk menyelesaikan segala perbantahan di masyarakat dengan jalan damai, serta memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang.[5] Perda Propinsi Kalimantan Tengah di atas merupakan contoh bagaimana nilai-nilai kedaerahan diakomodasi ke dalam hukum positif, yang tentu sangat berpotensi untuk dielaborasi menjadi kearifan lokal untuk penyelesaian perselisihan permasalahan ketenagakerjaan.
Terminologi “kearifan lokal” ini sayangnya tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undng Nomor 2 Tahun 20014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Undang-undnag ini hanya mengedepankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya tidak ada kontradiksi antara konsep kearifan lokal sebagaimana mungkin sudah tertuang dalam banyak peraturan daerah dengan konsep nilai-nilai Pancasila sebagaimana terrcantum dalam Undang-Undang PPHI. Hal ini dapat dipahami karena nilai-nilai Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi dari kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat berbagai daerah.
Oleh sebab itu, dalam penyelesaian kasus-kasus hubungan industrial, setiap mediator atau hakim, sepanjang relevan, wajib mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal ini. Relevansi ini penting digarisbawahi karena tidak setiap kasus hubungan industrial itu bermuatan nilai-nilai lokal yang memerlukan kajian kearifan lokal.
Masalahnya adalah bahwa tidak mudah mencari nilai-nilai kearfian lokal dalam PPHI. Kearifan lokal lebih banyak bersinggungan dengan hukum keluarga, lingkungan, agraria, dan sangat jarang muncul pada hukum ketenagakerjaan. Sangat disarankan agar para mediator dan hakim dapat menggali nilai-nilai kearifan lokal dan menuangkan dalam akta perdamaian atau putusan-putusan hakim, sehingga menjadi referensi bagi para pengkaji hukum ketenagakerjaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjadi masukan dalam pembangunan hukum ketenegakerjaan yang bernuansa Indonesia sesuai dengan amanat UU PPHI, yaitu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila. (***)
CATATAN:
[1] LIhat artikel Sartini, yang dipublikasi ulang dalam: <http://biolog-indonesia.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-kearifan-lokal-local-wisdom.html> akses 2 Februari 2016.
[2] Lilik Mulyadi, Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun, XXVI, No. 303, Februari, 2011, hlm. 66.
[3] Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 29.
[4] Haryo Kunto Wibisono, et.al., Dimension of Pancasila Ethics in Bereaucracy: Discourse of Governace, Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan, Globalethics, 2013, hlm. 16.
[5] Perda ini konon bernomor 16/DPR-GR/1969 tentang Penyatuan, Pengangkatan, Pemecatan Sementara, Pemberhentian, dan Penetapan Sementara Wilayah Kedamangan serta Tugas dan Kewajiban Damang Kepala Adat dalam Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Lihat Winda Mariani, “Kajian tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalimantan,” <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250557&val=6702&title…> akses tgl. 2 Februari 2016.
[6] Adrian Sutendi, Hubungan Industrial, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 129. Disebutkan bahwa pentahapan proses dalam Pengadilan Hubungan Industrial dalam Acara Biasa minimal melalui pentahapan sebagai berikut: (1). Permohonan gugatan, (2). Pemeriksaan berkas gugatan, (3). Jawaban gugatan, (4). Replik – Duplik, (5). Pembuktian, (6). Pemanggilan saksi, (7). Putusan.
[7] Damanhuri Fattah, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2013. Keputusan Moral adalah sederet evaluasi moral yang telah dibuat atau diputuskan yang sekiranya menjadi sebab dari tindakan sosial berdasarkan evaluasi moral yang dibuat secara refleksif.
[8] Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 47. Keadilan Protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan berupa perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia, sehingga tak seorangpun akan mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenangnya.
[9] Ibid., hlm. 48.



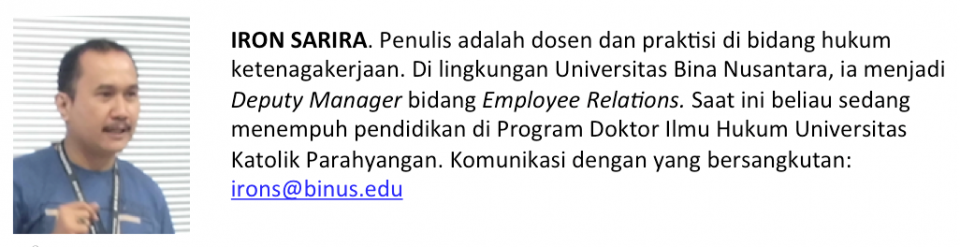
Comments :