ASAS “DIE NORMATIVE KRAFT DES FAKTISCHEN”
Oleh SHIDARTA (Februari 2016)
Asas ini sebenarnya berasal dari ajaran Georg Jellinek, yang disebut “Die Lehre von der Normativität des Faktischen.” Atas dasar ajaran ini, Gustav Radbruch dalam bukunya ‘Rechtsphilosophie’ (cet. 8, 1973, antara lain hlm. 25), menyebutkan adanya asas ‘die normative Kraft des Faktischen’ tersebut. Secara harifiah asas ini bermakna tentang kekuatan normatif yang timbul dari fakta-fakta. Artinya, jika suatu fakta dilakukan berulang-ulang, maka secara sosiologis akan lahir ketentuan normatif yang mengikat. Dalam bahasa Belanda, L.J. van Apeldoorn (1985: 42, terjemahan Oetarid Sadino) pernah mengungkapkan juga hal serupa dengan kata-kata, “die normatieve kracht van het feitelijk gebeuren” (terjemahan bebasnya: apa yang biasa, acapkali diangkat menjadi kaidah).
Sudah menjadi kenyataan bahwa manusia senang membuat pola-pola tertentu dalam perilakunya sehari-hari. Orang-orang cenderung untuk duduk atau parkir di tempat yang sama setiap kali ia berkunjung di satu tempat. Kecenderungan ini akan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga di satu meja makan keluarga, misalnya, tempat duduk ayah, ibu, dan anak-anak biasanya akan terdistribusi secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Perubahan distribusi akan terjadi apabila konteks material ruangnya berubah. Misalnya, meja itu digeser menghadap arah berbeda dengan susunan kursi yang berubah.
Hukum mengadopsi kecenderungan yang sama. Hukum dengan demikian beranjak dari pola-pola perilaku (nomos), yang kemudian dinormakan. Pola baru akan terbentuk jika ada konsistensi atas perilaku tertentu secara terus-menerus (berkelanjutan) dalam jangka waktu lama (longa et inveterata consuetudo). Konsistensi tersebut menimbulkan kesadaran (conscientie) pada rakyat bahwa pola ini perlu dipertahankan. Kesadaran inilah yang dianggap oleh Apeldoorn sebagai kekuatan yang esensial dalam hukum. Ia menolak menerima pandangan bahwa kekuasaan politik sebagai unsur esensial dalam hukum. Kekuasaan politik hanyalah unsur tambahan (accessoir) karena yang utama adalah kesusilaan. Sebab, kekuasaan selalu terletak pada orang-orang yang diperintah, bukan orang-orang yang memerintah. Ia menunjuk pada fakta sejarah tentang lamanya kekuasaan Romawi dapat bertahan karena mengandalkan kekuatan pada kekuasaan susila itu tadi. Begitu kekuatan susila ini memudar, maka hukum pun akan kehilangan legitimasi sosialnya.
Jadi, asas “die normative Kraft des Faktischen” adalah sebuah asas hukum yang mengedepankan pentingnya kebiasaan sebagai sumber hukum. Pengakuan terhadap pentingnya sumber hukum ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, hakim diperintahkan oleh undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009). Perjanjian juga dipandang tidak hanya mengikat atas apa yang secara tegas-tegas diperjanjikan, melainkan juga atas apa yang sudah menjadi kebiasaan (Pasal 1339 KUH Perdata).
Dalam hal ada kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang, maka memang muncul problematika apakah asas “die normative Kraft des Faktischen” harus dijadikan patokan. Lazim diterima suatu pandangan umum, bahwa asas ini akan didahulukan jika norma undang-undang itu bersifat mengatur. Sebaliknya, jika norma undang-undang itu bersifat memaksa, maka asas ini harus mengalah pada asas ‘lex dura sed tamen scripta’ (hukum itu keras, demikianlah ia tertuis).
Tentu saja, dalam praktik tidak selalu mudah untuk memilah antara hukum yang bersifat mengatur dan memaksa. Tolok ukur yang kerap dipakai adalah sanksi. Jika ada sanksi, maka norma itu dianggap memaksa, jika tanpa sanksi diangap mengatur. Padahal, tidak selalu sanksi hadir secara eksplisit meyertai norma primer dalam formulasi di dalam undang-undang. Di sinilah terlihat bahwa tarik-menarik antara sumber-sumber hukum, termasuk antara kebiasaan yang mencerminkan kesadaran (conscientie) rakyat dan undang-undang sebagai hukum positif tertulis, menjadi area diskursus hukum yang tidak pernah selesai. Hal ini akan makin terasa signifikan ketika pola-pola kebiasaan itu mulai merambah ke subjek-subjek yang makin terpolarisasi, tidak lagi ditandai oleh ruang dan waktu yang sama. Interaksi para pengguna media sosial, misalnya, tidak lagi berada dalam koridor satu teritori negara, sehingga pola-pola perilaku yang mereka ciptakan akan menimbulkan versi baru dalam pemaknaan sumber hukum kebiasaan ini. (***)

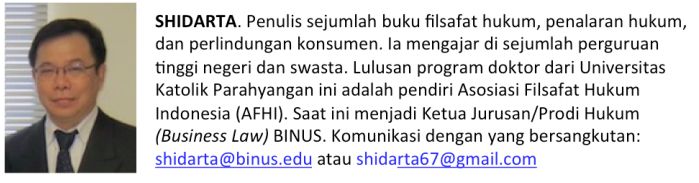
Comments :