POLITIK HUKUM KEBERPIHAKAN DAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI KAUM TERMARGINAL
Oleh SHIDARTA (Januari 2016)
Percayakah Anda bahwa separuh dari kekayaan penduduk dunia saat ini dikuasai oleh hanya 62 orang? Demikianlah fakta yang dirilis oleh lembaga amal Oxfam menjelang pertemuan tahunan the World Economic Forum di Davos, Swiss awal tahun ini. Tercatat ada 62 orang terkaya di dunia saat ini yang kekayaannya sama dengan harta milik 3,5 milyar warga dunia. Akumulasi kekayaan segelintir orang ini mencapai angka US$1.76 trilyun atau meningkat 44 persen sejak tahun 2010. Ironisnya, harta milik 3,5 milyar penduduk dunia di luar mereka rata-rata menunjukkan penurunan 4,1 persen. Hampir separuh dari 62 orang kaya ini berasal dari Amerika Serikat. Ada 17 orang di antaranya berasal dari kawasan Eropa. Sisanya berasal dari negara-negara seperti China, Brazilia, Meksiko, Jepang, dan Saudi Arabia.
Sangat mengejutkan bahwa orang-orang superkaya ini ternyata menikmati kemudahan pajak senilai US$7.6 trilyun, yang apabila pajak ini mereka bayarkan, akan mampu memberi pendapatan ekstra bgi pemerintah negara-negara di dunia ini senilai US$190 milyar per tahun. Di kawasan Afrika saja, ada senilai US$14 milyar/tahun pendapatan pajak yang hilang dan ini cukup untuk menyelamatkan nyawa 4 juta bayi setiap tahun dan membayar gaji guru-guru sekolah guna menjamin setiap anak Afrika bisa menempuh pendidikan mereka.
Gambaran ini menunjukkan kondisi dunia kita saat ini masih jauh dari harapan tentang keadilan sosial karena secara umum ternyata yang kaya makin kaya dan yang miskin juga makin miskin. Menariknya, kondisi mayoritas masyarakat termiskin di dunia, menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tidak lagi bercokol di negara-negara miskin, tapi justru di negara kelompok menengah seperti India.
Ilustrasi di atas menarik perhatian karena pada saat bersamaan Pemerintahan Jokowi justru meluncurkan kebijakan baru pemotongan pajak apabila kaum pemodal kita mau menarik harta kekayaan yang mereka simpan di luar negeri untuk dibawa pulang ke Indonesia. Konon ada hampir US$194 milyar dana orang Indonesia yang diparkir di luar negeri (the Jakarta Post, 19 Januari 2016).
Dari kaca mata disiplin hukum, ilustrasi tersebut juga membuat kita perlu mempertanyakan bagaimana seharusnya kaum terpinggirkan (marginalized people) harus diselamatkan melalui kebijakan hukum yang lebih adil. Berbicara tenang kebijakan hukum membawa kita ke ranah politik hukum. Artinya, perlu ada politik hukum keberpihakan di sini, tetapi bukan diarahkan ke politik hukum diskriminatif-negatif. Pemikiran ini mengingatkan saya pada satu tulisan yang pernah saya buat tujuh tahun lalu untuk Newsletter KHN (Komisi Hukum Nasional) Vol.9, No.1, Januari-Februari 2009, hlm. 15-20. Tulisan pendek tersebut berangkat dari renungan filosofis yang memang tidak ditujukan untuk menjawab isu-isu teknis seputar ketidakadilan distributif kekayaan dunia sebagaimana diutarakan di awal tulisan ini. Saya hadirkan kembali renungan itu dengan menamplkan beberapa cuplikannya di bawah ini.
Cita-cita untuk membuat dunia lebih adil dengan mengedepankan kesamarataan tentu bukan lagi idealisme yang layak diperjuangkan. Saya ingat tatkala Henry Hazlitt (Dasar-Dasar Moralitas, 2003) merefleksikan satu pertanyaan filosofis, yakni tentang mengapa “keadilan” seringkali mengundang kesamaan dalam perlakuan dan seringkali juga ketidaksamaan dalam perlakuan. Hazlitt pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadilan yang menjadi inti dari tuntutan kesamaan perlakuan itu lebih mengandung makna proporsionalitas daripada makna kesamaan itu sendiri. Perlu ada lingkungan yang tepat untuk dapat menerapkan kesamaan perlakuan. Kesamaan tidak boleh diartikan sebagai penolakan untuk memperbolehkan pengecualian, atau membolehkan pengecualian untuk sesuatu yang lain selain dari kepentingan umum, dan tidak boleh hanya demi kepentingan pengecualian diri sendiri. Peraturan lalu lintas yang memberi hak yang sama bagi pengguna jalan, ternyata harus dikecualikan bagi mobil pemadam kebakaran, ambulans, atau mobil polisi. Pengecualian yang disebutkan oleh Hazlitt di atas hanya mungkin diterima jika ada tuntutan kepentingan yang lebih besar dalam jangka panjang, yakni demi keutamaan kepentingan persekutuan.
Gagasan untuk membuat desain hukum yang berpihak kepada kaum miskin/termarginal adalah suatu politik hukum keberpihakan yang bukanlah tanpa dasar, walaupun juga bukan tanpa risiko. Dalam konteks yang lebih luas, politik hukum seperti ini adalah upaya pemberdayaan dengan cara memberikan kekuatan posisi tawar pada kaum miskin/termarginal. Tindakan demikian dikenal sebagai tindakan afirmatif (affirmative action), yang secara konseptual bukan “barang baru” dalam perjalanan politik hukum di republik ini. Contoh dari praktik ini (terlepas dari gagal tidaknya) adalah program “benteng” oleh Menteri Kesejahteraan Djuanda para era Orde Lama, yang berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959. Konon, politik hukum ini di kemudian hari ditiru oleh Malaysia dengan diberi label “Kebijakan Ekonomi Baru” dari Partai UMNO dan terus berlangsung sampai sekarang. Contoh tindakan afirmatif yang lebih aktual di Indonesia adalah ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang mewajibkan partai politik menempatkan paling sedikit 30% perempuan pada daftar calon anggota legislatif yang mereka susun.
Pemberdayaan ini merupakan tindakan afirmatif yang harus didesain secara cermat sejak awal dan diperlakukan sebagai tindakan sementara. Seyogianya, fasilitas dari tindakan afirmatif hanya boleh dinikmati oleh sebagian kecil saja dari keseluruhan masyarakat. Sebab, makin banyak jumlah subjek yang diberi fasilitas ini, akan makin berat beban masyarakat lain untuk menanggung dampak diskriminasi tersebut, sehingga dalam tenggang waktu tertentu hal ini merupakan bentuk ketidakadilan juga. Harus dicermati bahwa bagaimanapun suatu diskriminasi positif hanya dinilai “positif”-nya oleh penikmat fasilitas itu saja, sementara bagi anggota masyarakat lainnya tetap saja kebijakan itu dirasakan “negatif”-nya.
Akhir dari politik hukum keberpihakan ini adalah apabila pemberdayaan tersebut telah mencapai sasarannya. Pada tahap ini, harus ada jaminan bahwa segera setelah tindakan afirmatif dihentikan, kelompok yang telah diberdayakan ini tidak lalu kembali lagi mundur kualitas hidupnya. Di sisi lain, harus juga ada jaminan yang sama bagi kelompok lain bahwa politik hukum keberpihakan ini tidak akan mengurangi tingkat kesejahteraan yang sudah mereka nikmati saat pertama kebijakan ini dijalankan.
Harapan di atas mengingatkan pada dua konsep dari Vilfredo Pareto, yang disebut Pareto optimality dan Pareto superiority. Kedua konsep ini mencoba menjelaskan tentang pengalokasian sumber-sumber daya yang memberi keuntungan bagi masyarakat. Sesuatu disebut Pareto-optimal jika pembagian keuntungan itu bisa sampai pada satu tingkat yang sama-sama membuat semua orang bahagia. Jika satu orang saja dapat ditingkatkan kebahagiaannya, tetapi hal itu menyebabkan ada satu orang lain menjadi lebih menderita, maka cara tersebut tidak lagi dapat dipertahankan. Untuk itu harus dicari perbandingan terhadap cara lain, sehingga sampailah pada konsep Pareto-superior. Konsep yang disebutkan terakhir ini merupakan perbandingan antara dua cara pengalokasian sumber keuntungan yang sama. Katakanlah bahwa selain cara X, ada cara lain yang disebut cara Y. Dalam konteks perbandingan itu, cara X akan disebut sebagai Pareto-superior terhadap Y jika paling sedikit ada satu orang yang merasa lebih berbahagia (dibandingkan dengan cara Y) tanpa membuat ada satu orang lain merasa lebih menderita. Jika kedua cara itu tidak berhasil mencapai kondisi seperti di atas, maka tidak ada satupun di antara mereka yang patut disebut Pareto-superior.
Kekhawatiran Vilfredo Pareto tersebut memang patut dipertimbangkan dalam penerapan politik hukum keberpihakan, namun risiko seperti disampaikannya sangat mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Dalam kondisi tertentu, pembentuk hukum sering dihadapkan pada pilihan untuk berbuat sesuatu (sekalipun harus berpihak) atau mendiamkan saja kondisi yang sudah ada, yang berarti melanggengkan ketidakadilan pada sekelompok orang, sekecil apapun jumlah mereka. Keadilan bukanlah sesuatu yang layak untuk ditunda-tunda. Sebab, sebagaimana disampaikan oleh seorang hakim agung Inggris Lord Dening, “Justice delayed is justice denied.”
Demikianlah, kebijakan pemerintah untuk pemotongan pajak dan lain-lain kebijakan serupa tidak boleh dipicu semata-mata demi tujuan pragmatis. Harus ada payung besar kebijakan hukum yang intinya lebih berpihak kepada kaum miskin/termarginal. Kebijakan itu harus dikontrol secara baik agar tidak meleset. Apabila dunia saat ini menyaksikan ada 62 orang superkaya menguasai separuh kekayaan penduduk dunia dan menikmati “tax havens” berlebih-lebihan, maka tidak seharusnya di lingkup negeri yang katanya menjunjung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kita mendapati kenyataan serupa. (***)



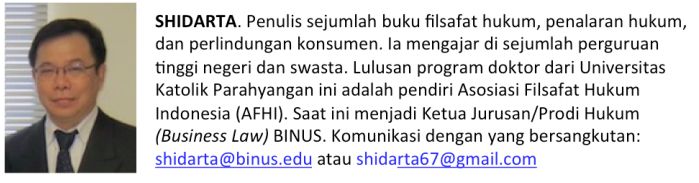
Comments :