KEJAHATAN BISNIS DI SEKTOR KEHUTANAN
Oleh AHMAD SOFIAN (November 2015)
Kabut asap yang menyelimuti beberapa provinsi di Indonesia beberapa waktu lalu telah menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum. Pelaku pembakaran hutan yang sebagian besar adalah perusahaan yang berbadan hukum mulai diungkap oleh penegak hukum. Polisi sudah menetapkan beberapa perusahaan sebagai tersangka pembakaran hutan. Dalam kaca mata hukum pidana Indonesia, sebuah perusahaan dapat dijadikan subjek norma, artinya dapat diminta pertanggungjawaban pidana, hanya saja bagaimana bentuk konkret pertanggungjawaban pidananya, hingga sekarang masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat.
Artikel pendek ini bermaksud untuk mengurai benang kusut pertanggungjawaban pidana korporasi, dan juga menguraikan tentang kejahatan bisnis yang dilakukan korporasi di sektor kehutanan. Terminologi kejahatan bisnis jarang diungkap dalam pembahasan pembakaran lahan yang terjadi akhir-akhir ini. Kabut asap yang terjadi disebabkan oleh pembakaran lahan hutan yang dilakukan oleh korporasi dan individual. Kejahatan korporasi mempersempit pelaku kejahatan hanya terbatas pada pengurus korporasi, yaitu direktur, para atau kepala bagian/kepala divisi sementara pemilik perusahaan tidak akan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Dengan kata lain, pemilik korporasi terlindungi karena perbuatannya diwakili oleh pengurus korporasi tersebut. Sementara itu, jika menggunakan terminologi kejahatan bisnis, maka pemilik korporasi termasuk dalam kategori dan satu kesatuan subjek hukum yang tidak bisa dipilah-pilah dengan pengurus korporasi.
Dalam konsepsi kejahatan bisnis, pemilik korporasi merupakan organ yang mengendalikan bisnis tersebut, meskipun hukum positif suatu negara membatasi pertanggungjawaban suatu korporasi hanya pada pengurus. Pemilik korporasi memiliki tanggung jawab pidana ketika perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam kaitan ini, pertanggungjawaban pidana dapat ditarik dengan menggunakan teori kausalitas. Hart dan Honore dalam bukunya yang sangat popular yaitu Causation in Law (1985) mengemukakan teori Necessary and Sufficient Cause (NSC). Dalam teori ini beliau mengemukakan bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, diukur dengan indikator: (1) apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan satu-satunya yang sangat penting menimbulkan akibat yang dilarang, artinya tanpa adanya perbuatan tersebut tidak akan mungkin muncul akibat yang dilarang? Lalu, (2) apakah ada sebab-sebab lain yang cukup yang memberikan kontribusi pada munculnya akibat yang dilarang?
Jika menggunakan teori tersebut, maka perbuatan pengurus korporasi bukan satu-satunya yang menjadi menyebab timbulnya akibat yang dilarang yaitu munculnya asap yang berkepanjangan yang menimbulkan penyakit pada ratusan ribu warga di beberapa propinsi di Indonesia. Perbuatan lain yang menimbulkan akibat yanf dilarang tersebut adalah kebijakan dari pemilik korporasi yang menggunakan hutan sebagai bisnis mereka dan kebijakan yang menyangkut tata kelola hutan. Dari teori Hart dan Honore ini, dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus korporasi bukanlah satu-satunya yang menjadi penyebab timbulnya kebakaran hutan tetapi ada penyebab lain dari pemilik korporasi tersebut. Karena itu dalam konteks kejahatan bisnis, pemilik korporasi dapat diminta pertanggungungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin causation tersebut.
Pelaku Pelanggaran HAM
Aspek lain yang perlu ditelisik adalah tentang apakah dimungkinkan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dapat dijadikan sebagai subjek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)? Dalam instrumen hukum internasional dan juga dalam hukum nasional yang bisa dijadikan subjek pelanggaran HAM hanyalah negara (state actor), korporasi belum dapat dijadikan subjek pelanggaran HAM. Meskipun demikian dalam beberapa tahun terakhir ini telah muncul polemik di kalangan ahli hukum pidana internasional tentang mencari jalan terbaik untuk memperluas jangkauan pelanggaran HAM tidak saja pada state actor tetapi juga pada Trans-National Corporation (TNC).
Terkait dengan hal ini, pada tahun 2005 seorang pelapor khusus PBB pada bidang bisnis dan HAM yaitu John Ruggie mendapat tugas khusus dari sekjen PBB untuk mengkaji dampak bisnis pada pelanggaran HAM. Pada tahun 2011, kajian dari Ruggie menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut dengan “The Guiding Principles on Business and Human Rights. The Guiding tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi, ini hanya sebuah “kode etik” yang tidak memiliki sanksi atas pelanggar-pelanggarnya, karena itu telah muncul gerakan dari negara-negara berkembang di Amerika Latin dan Afrika untuk mendorong meningkatkan status dari The Guiding ini menjadi sebuah instrumen hukum internasional yang memiliki kekuatan untuk mengontrol korporasi bahkan memberikan remedy kepada korporasi yang terbukti melanggar HAM. Perdebatan ini hingga sekarang masih belum tuntas, muncul pro dan kontra atas proposal ini.
Menjadikan korporasi sebagai pelaku pelanggaran HAM menarik untuk diikuti, karena berbagai kepentingan dan idiologi hukum ikut bermain dalam perdebatan ini. Bagi Negara-negara yang pro untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pelanggaran HAM dengan alasan ditemukannya fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi. Misalnya, Kasus yang terjadi di Congo, di mana korporasi terang-terangan membayar tentara untuk membantu membebaskan lahan dan akhirnya muncul konflik yang menngakibtkan terbunuhnya penduduk sipil. Pemasangan pipa saluran air, merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan korporasi, dan dalam menjalankan bisnis ini ternyata menimbulkan bencana kemanusiaan, meskipun bencana kemanusiaan itu dilakukan oleh tentara, namun tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan sektor bisnis.
Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Indonesia saat ini, maka terminologi bencana asap seperti yang dirilis oleh beberapa media kurang tepat, karena akan menggeser perbuatan manusia yang menimbulkan dampak terhadap kemanusiaan, menjadi seolah-oleh perbuatan alam. Karena itu, jika dikaitkan dengan statuta Roma (instrumen hukum internasional yang mendefinikan tentang kejahatan HAM), maka apa yang terjadi saat ini dengan pembakaran hutan, sudah masuk dalam lingkup pelanggaran HAM. Dampak dari perbuatan pembakaran hutan telah memunculkan bencana kemanusiaan pada puluhan ribu warga masyarakat yang kehilanggan hak-hak dasarnya sebagai manusia, menimbulkan gangguan pada kesehatan, dan terancam keselamatannya, bahkan telah menimbulkan kematian. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kasus kebocoran radio aktif pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl yang terjadi tahun 1986. Serbuk radio aktif akibat dari kebakaran pembangkit listrik tenaga nuklir, terbawa angin hingga ke wilayah barat Rusia, Eropa Timur, bahkan Skandinavia, Inggris, dan Amerika Timur. Lebih dari 200.000 penduduk yang bermukim dalam radius 30 km dari tempat ledakan Chernobyl telah dievakuasi. Ledakan pada pembangkit listrik tersebut dianggap sebagai kecelakaan dan bencana biasa sehingga pelaku tidak dikriminalisasi, masyarakat internasional sangat kecewa atas putusan tersebut.
Untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah kejahatan bisnis di sektor kehutanan, maka diperlukan langkah-langkah hukum untuk memastikan pelaku kejahatan bisnis diperluas tidak hanya pada pengurus korporasi tetapi sebagaimana yang diungkapkan oleh Hart dan Honore termasuk juga pelaku lain yang memberikan kontribusi munculnya akibat yang dilarang. Secara internasional Indonesia pun seharusnya memainkan peranan penting untuk mendukung upaya “kriminalisasi” korporasi sebagai subjek hukum HAM, jika tidak maka apa kejadina hangusnya hutan tropis Indonesia dan munculnya kejahatan kemanusiaan akan terulang kembali. (***)



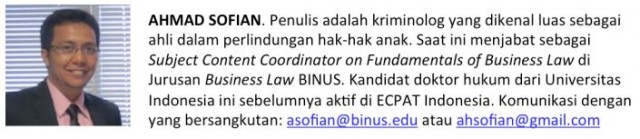
Comments :