IRONI INTERVENSI NEGARA: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
Oleh AHMAD SOFIAN (September 2015)
Kekisruhan yang terjadi atas ditetapkannya sebagai tersangka dua komisioner Komisi Yudisial masih belum menemukan titik terang. Status tersangka terhadap dua pejabat negara ini masih melekat. Pengaduan hakim Sarpin Rizaldi atas tuduhan pencemaran nama baik belum bisa dihentikan polisi sepanjang pengaduan tidak dicabut. Atas nama negara “Bareskrim Polri” bertindak untuk mewakili kepentingan korban yang dicemarkan namanya oleh kedua komisioner tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah benar korban dicemarkan? Bagaimana membuktikan bahwa nama korban tercemar akibat penetapan ini? Bisakah dibuktikan bahkan korban kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan atau hal-hal yang menimbulkan kerugian lain dari penetapan pejabat negara tersebut?
Artikel singkat ini akan mengulas persoalan di atas dari perspektif viktimologi yang kurang banyak disorot oleh ahli-ahli hukum lainnya. Perspektif yang kurang popular, namun penting, karena dalam melihat dan menganalisis sebuah peristiwa hukum tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi saja, saya ingin meminjam istilah Dr. Shidarta yaitu perlu melihatnya dari multidimensi atau “multifaset” sehingga hasilnya lebih komprehensif dan lebih profesional.
Korban atau viktim menurut the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi , melalui perbuatan atau pembiaran yang melanggar hukum pidana. Ketika adanya pengaduan korban maka negara meresponnya dengan asumsi melindungi kepentingan korban dan mengurangi kegiatan kriminal. Namun respon negara tidak boleh berlebihan dalam melindungi kepentingan korban, menurut John Braithwaite (Australian National University) menarik tersangka dalam sistem peradilan secara berlebihan untuk melindungi kepentingan korban malah bisa memperburuk persoalan, karena itu menurutnya respon negara dalam melindungi kepentingan korban harus proporsional dan tidak selamanya harus menariknya dalam sistem peradilan pidana.
Karena itu, jika kita melihat kasus Komisioner Yudisial yang ditersangkakan sudah masuk dalam arena perbuatan viktimisasi. Negara “menciptakan” viktim untuk dapat memasukkan orang-orang tertentu dalam sistem peradilan pidana. Wolhuter (2009) mengatakan bahwa viktimisasi dapat dimaknai sebagai pelabelan korban yang tidak sesuai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk “meniciptakan” atau “merekayasa” viktim. Negara ikut serta menciptakan viktim sebagai bagian dari bentuk perlawanan pada kelompok tertentu. Bahkan kasus ini dapat dimasukkan dalam kategori viktimisasi struktural, karena korban digunakan secara terstruktur untuk “memukul” siapa saja yang coba-coba untuk melawan rejim yang berkuasa.
Negara melalui aparat penegak hukumnya telah menciptakan “the politic of victimization” untuk membungkam para pengritiknya. Praktik seperti ini, sebagaimana ditulis oleh Robert Elia merupakan strategi jitu di negara-negara berkembang untuk dipergunakan melawan kelompok-kelompok oposisi. Karena itu, jalan keluar yang perlu didisikusikan dalam akhir tulisan ini adalah perlu menciptakan mekanisme “pembuktian viktim” atas viktimisasi sejumlah viktim tertentu. Viktim yang disebut-sebut telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh pelaku, perlu diperdengarkan kesaksiannya dan bukan semata-mata diwakili oleh penegak hukum. Penegak hukum bukan menyuarakan kepentingan viktim semata tetapi kepentingan keadilan. (***)



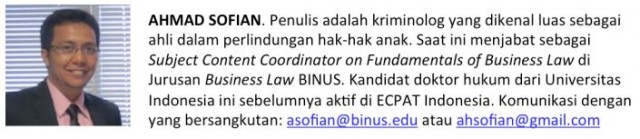
Comments :